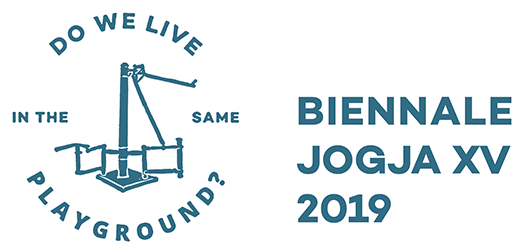Satu di antara rangkaian program Biennale Jogja XV adalah Residensi Kelana. Lewat program ini para seniman terpilih dibagi menjadi tiga kelompok, mereka menyusuri daratan, sungai, dan lautan.
Di Kalimantan, para seniman Residensi Kelana Sungai akan mengeksplorasi sungai Kapuas, dengan titik berangkat dari Pontianak. Di Pulau Borneo ini, para seniman yang terdiri dari Suvi Wahyudianto, Tajriani, dan Sutthirat Supaparinya (Thailand) tinggal di Balaan tumaan, sedangkan selama di Singkawang, mereka menetap di Sanggar Simpur.
Pada awalnya ketiga seniman ini menjalani proses bersama di Sintang, di sana mereka tinggal di rumah panjang, yang merupakan rumah adat setempat. Selain mengadakan beberapa kegiatan, termasuk melakukan presentasi karya, para seniman ini juga mencari fokus masing-masing untuk program Residensi Kelana ini.


Seniman Residensi Kelana Sungai bersama masyarakat di Rumah Panjang, Sintang
Suvi Wahyudianto adalah seorang seniman kelahiran Bangkalan, Madura. Suvi, panggilan akrabnya, merupakan lulusan Universitas Negeri Surabaya. Sebagai orang Madura, perjalanan ke Kalimantan ini merupakan hal yang menantang bagi Suvi. Meski di sepanjang sungai ia lebih banyak bertemu dengan bekas kerajaan-kerajaan tua Melayu, namun di kota kecil, Suvi akan bertemu dengan suku Dayak.
Hal ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari tragedi Sampit yang merupakan salah satu bentuk pecahnya konflik antar etnis di Indonesia. Konflik ini terjadi di kota Sampit Provinsi Kalimantan Tengah ini tentunya menjadi sejarah kelam bangsa Indonesia, dimana pertikaian berdarah ini melibatkan kelompok suku asli Dayak dan juga suku Madura sebagai pendatang dari Pulau Madura. Tercatat 500 orang menjadi korban jiwa dari peristiwa ini, serta 100.000 warga Madura harus kehilangan tempat tinggalnya.
Sejak awal terlibat di Residensi Kelana, Suvi memang fokus tentang politik identitas, terutama memori bersama konflik di Sampit dan Sambas. Karena itu setibanya di Pontianak, ia langsung mengejar dan menggali hal-hal yang berkaitan dengan memori tersebut. Di sana Suvi bertemu dengan banyak narasumber, di antaranya Andre WP, seorang tokoh muda Madura. Ia juga sempat bertemu keluarga korban, bahkan dan keluarga pelaku pertikaian tersebut.
Hingga kini Suvi mengaku untuk berhati-hati dalam mengeluarkan statement, karena masih berlaku aturan tidak tertulis bahwa orang Madura tidak bisa masuk di Sambas.
Selain mewawancari banyak narasumber, Suvi juga melakukan ziarah ruang, di antaranya mendatangi kuburan massal yang tidak teridentifikasi. Info tentang kuburan di Singkawang tersebut didapatnya dari video yang dibuat 10 tahun lalu. Suvi juga mendatangi bekas tempat penampungan, dan perkampungan Madura di sana.
Dalam penciptaan karyanya, Suvi sering berangkat dari cerita pengalaman hidupnya. Ia sering merefleksikan memori personal dan kaitannya dengan sejarah serta realitas sosial di masyarakat. Salah satu karyanya yang berjudul “Angst”, merupakan hasil dari refleksi pengalaman pribadinya terkait dengan konflik Sampit. Karyanya yang berjudul “Angst” ini juga meraih penghargaan UOB Indonesia “Painting of The Year”. Rencananya untuk pameran Biennale Jogja mendatang, Suvi akan membuat karya seni instalasi yang diadaptasi dari persentuhannya dengan masyarakat di Kalimantan.
Residensi Kelana menurutnya pribadi adalah sesuatu yang penting untuk membaca sejarah masyarakat di Kalimantan, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah sungai dimana banyak terjadi pertemuan berbagai identitas, selain itu Kerajaan-Kerajaan tua di Kalimantan juga berpusat di dekat sungai.


Seniman lainnya Sutthirat Supaparinya, atau akrab dipanggil Som memilih fokus untuk mengangkat kembali peristiwa Mandor. Salah satu peristiwa genosida yang pernah terjadi di Indonesia adalah peristiwa Mandor yang terjadi pada 28 Juni 1944. Peristiwa tersebut terjadi di Kalimantan Barat. Mandor sendiri merujuk pada sebuah kecamatan di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
Saat peristiwa Mandor terjadi, pemerintah militer Jepang masih berkuasa di Kalimantan Barat. Pemerintahan Jepang di Kalimantan Barat dijalankan oleh Armada Angkatan Laut (Kaigun) Selatan ke II. Mereka inilah yang melakukan pembunuhan secara besar-besaran terhadap penduduk Kalimantan Barat. Pembunuhan ini didahului dengan penangkapan orang-orang yang akan dibunuh dengan cara disungkup dan dibawa dengan truk. Sehingga masyarakat juga mengenal peristiwa ini sebagai tragedi Oto Sungkup.
Som tinggal dan berkarya di Chiang Mai, Thailand. Karya-karyanya hadir dalam beragam medium, misalnya instalasi, benda-benda temuan, dan gambar bergerak. Dalam karya-karyanya, Som banyak mempertanyakan dan menerjemahkan informasi publik serta struktur yang memengaruhinya dan masyarakat. Proyek-proyek terbarunya fokus pada dampak aktivitas manusia pada manusia dan alam.
Karya-karya Som telah dipamerkan di berbagai museum dan galeri, antara lain Hiroshima City Museum of Contemporary Art, Mori Art Museum, Sherman Contemporary Art Foundation, Solomon R. Guggenheim Museum, dan sebagainya. Som juga pernah ikut serta dalam gelaran festival dan biennale, semacam Koganecho Bazzar 2011 dan Yebisu International Festival for Art & Alternative Visions di tahun 2012 dan 2018, Gwangju Biennale 12, dan Cairo Biennale.
Lain halnya dengan Tajriani yang berasal dari Polewali Mandar. Perempuan lulusan Psikologi, Universitas Makassar ini banyak bekerja dalam wilayah Mandar. Tajri juga aktif dalam pengajaran melalui kegiatan Nusa Pustaka, berlayar untuk membagikan buku dan mengajar ke daerah-daerah pelosok di Sulawesi. Selain itu, Tajri juga ahli dalam bermain kecapi yang membawanya untuk tampil dalam berbagai pertunjukan musik. Salah satu penampilannya adalah di Bangkok dalam acara “Wonderful Indonesia Festival” tahun 2018.
Sesuai dengan disiplin ilmu yang dikuasainya, untuk program Residensi Kelana ini, Tajri meriset tentang tradisi yang memengaruhi psikologis masyarakat setempat. Awalnya ia ingin mencari tahu lagu-lagu pengantar tidur anak-anak. Namun ketika berada di Rumah panjang Sintang dan melakukan wawancara, ia menemukan bahwa lagu-lagu tersebut sudah tidak dinyanyikan lagi. Bahkan masyarakat sudah tidak lagi hafal lagu pengantar tidur untuk anak-anak.
Karena itu ia merubah fokus yang semula ingin diangkatnya, lalu memilih untuk mendalami tradisi lisan, terutama lagu-lagu dan ritual untuk menanam padi. Ia pun mulai berinteraksi dan mengamati keseharian para petani di ladang.
Menurutnya, sesuatu yang inti dari kehidupan adalah bagaimana cara masyarakat mengisi perutnya, karena hal tersebut turut memengaruhi tradisi yang ada. Rencananya karya yang akan ia tampilkan di Biennale Jogja mendatang adalah berupa audio, video, dan seni intalasi. Bagi Tajri, program Residensi Kelana penting baginya untuk belajar dan berinteraksi dengan masyarakat yang ada di luar budayanya. Lewat residensi ini, ia juga bisa melihat bagaimana cara hidup orang lain.


Kurator Biennale Jogja XV Arham Rahman menjelaskan bahwa poin dari program ini adalah untuk melihat kembali dan berusaha mencari narasi lain yang telah memudar, dan nyaris dilupakan terutama karena efek kolonialisme dan kemunculan nasionalisme (nation-state).
Residensi Kelana yang diselenggarakan bersama dengan Cemeti Institute for the Arts and Society ini berusaha menjangkau tiga wilayah dan tiga pendekatan yang berbeda, yakni Sumatera (susur darat), Kalimantan (susur sungai), dan Sulawesi Barat (susur laut). Narasi tentang darat, sungai, dan laut menjadi titik sentral residensi ini.
Setiap seniman didorong untuk mencari dan mengeksplorasi narasi jenis apa yang ada pada saat sebelum/semasa era kolonial dan kini telah diabaikan, disembunyikan, dan tidak dibicarakan di wilayah-wilayah yang mereka susuri. (*)