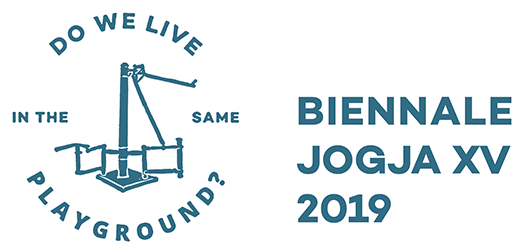Hingga saat ini ada dua teori kanon mengenai asal usul bangsa Asia Tenggara. Yang pertama adalah informasi yang menjelaskan bahwa nenek moyang bangsa Asia Tenggara berasal dari daratan Yunan di China Selatan. Teori ini menyebutkan bahwa nenek moyang bangsa-bangsa di Asia Tenggara berasal dari satu sumber, yaitu bangsa Austronesia. Teori yang kedua adalah teori Nusantara, yang menyatakan bahwa asal mula manusia yang menghuni wilayah Nusantara ini tidak berasal dari luar, melainkan mereka sudah hidup dan berkembang di wilayah Nusantara itu sendiri.
Yayasan Biennale Yogyakarta (YBY) merasakan pentingnya untuk melakukan komparasi atas kedua teori kanon tersebut. Untuk itu, tahun ini Biennale Jogja mengadakan sebuah program bertajuk “Residensi Kelana”. Seperti namanya, program ini dikemas dalam bentuk perjalanan yang menelusuri beberapa titik lokasi.
Kurator Biennale Jogja XV Arham Rahman menjelaskan bahwa poin dari program ini adalah untuk melihat kembali dan berusaha mencari narasi lain yang telah memudar, dan nyaris dilupakan terutama karena efek kolonialisme dan kemunculan nasionalisme (nation-state). Selain itu, ide mengadakan Residensi Kelana ini adalah untuk mencari benang merah dari kedua teori di atas. Arham menerangkan bahwa nenek moyang bangsa Asia Tenggara mempunyai karakteristiknya sendiri. Mereka hidup berpindah tempat, bermigrasi, dan membawa pengetahuan baru, baik ilmu bercocok tanam hingga agama lokal yang dekat dengan alam.
Residensi Kelana yang diselenggarakan bersama dengan Cemeti Institute for the Arts and Society ini berusaha menjangkau tiga wilayah dan tiga pendekatan yang berbeda, yakni Sumatera (susur darat), Kalimantan (susur sungai), dan Sulawesi Barat (susur laut). Narasi tentang darat, sungai, dan laut menjadi titik sentral residensi ini. Setiap seniman didorong untuk mencari dan mengeksplorasi narasi jenis apa yang ada pada saat sebelum/semasa era kolonial dan kini telah diabaikan, disembunyikan, dan tidak dibicarakan di wilayah-wilayah yang mereka susuri.
Di Sumatera, Aceh akan menjadi titik berangkat para seniman partisipan. Mereka menempuh jalan darat hingga ke Pekanbaru. Di wilayah ini akan ada banyak hal yang bisa dibicarakan, di antaranya menggali tradisi bahari di bekas kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera. Sementara di Kalimantan, para seniman residensi akan mengeksplorasi sungai Kapuas, dengan titik berangkat dari Pontianak, dan di Sulawesi Barat, desa Pambusuang, Polewali-Mandar, akan menjadi terminal bagi para seniman residensi untuk mengeksplorasi wilayah lautan.
Ada sembilan seniman yang terlibat di dalam program ini, mereka dibagi ke dalam tiga kelompok dan wilayah. Seniman-seniman di masing-masing wilayah mencakup; satu seniman Indonesia yang berasal dari luar wilayah sasaran, satu seniman lokal atau yang berasal dari wilayah sasaran, dan satu seniman asing (dari wilayah Asia Tenggara). Mereka akan tinggal bersama di wilayah-wilayah yang telah dipilih selama satu bulan. Setiap kelompok seniman nantinya akan membuat karya individu dan/atau karya kolaborasi.


Arham menjelaskan bahwa paska keruntuhan Majapahit kekuatan maritim kita hanya ada di tiga wilayah kerajaan; Aceh, Banten, dan Makassar. “Pelaut ulung banyak yang berasal dari Mandar, Sulawesi Barat. Jika orang Bugis berlayar untuk keperluan berdagang, maka kebanyakan nahkodanya berasal dari Mandar. Selain itu di desa Pambusuang, Sulawesi Barat memiliki tradisi maritim yang sangat kuat,” ujarnya.
Hingga saat ini mitos dan mantra-mantra laut di wilayah tersebut masih kuat dan tetap lestari. Awalnya, sebagai kurator Arham berharap kalau para seniman Residensi Kelana bisa ikut berlayar. Namun karena beberapa faktor, terutama cuaca, akhirnya mereka lebih banyak beraktifitas di wilayah pesisir kawasan tersebut. Sebagaimana para nenek moyang di masa silam, para seniman tersebut juga melakukan pertukaran pengetahuan. Diharapkan para seniman Residensi Kelana akan menampilkan sesuatu yang berbeda di perhelatan Biennale Jogja XV nantinya. “Hal yang harus mereka hindari adalah tidak sekadar meromatisir atau mengeksotisasi kebudayaan di sana,” jelas Arham.
Tanggal 10 Juni 2019 lalu, kelompok seniman residensi kelana laut berangkat dan mulai tinggal di Mandar hingga satu bulan ke depan. Mereka adalah Arif Setiawan, Ipeh Nur, Syamsul Arifin, dan seniman asal Filipina Nerisa Del Carmen Guevara. Kurator Biennale Jogja XV Akiq AW menjelaskan proses mencari seniman Residensi Kelana bukan hanya dilihat dari produksi karya saja, namun juga katalis yang ada di skena wilayah tersebut.


Residensi kelana laut juga dibantu oleh Muhammad Ridwan Alimuddin yang merupakan seorang penulis, fotografer, jurnalis, fixer film dokumenter, dan pustakawan asal Mandar, Sulawesi Barat. Iwan banyak terlibat dalam proyek-proyek penulisan buku dan dokumenter, khususnya dengan tema-tema tentang kehidupan di wilayah pesisir. Selain itu, ia juga aktif dalam gerakan literasi di wilayahnya. Salah satunya dengan mendirikan Nusa Pustaka, sebuah perpustakaan komunitas di daerah pesisir Sulawesi Barat yang juga menjadi basecamp seniman Residensi Kelana di sana.
Menurut Iwan, di minggu ke empat Residensi Kelana, para seniman sudah mematangkan hasil observasi mereka. Ke empat seniman tersebut juga sempat melihat proses pembuatan kapal phinisi di Bulukumba. Di sela-sela pembuatan kapal tersebut, mereka juga menyaksikan bagaimana upacara dan ritual yang ada di sana.
Sejak minggu kedua residensi kelana, Nerisa Del Carmen Guevara yang dikenal sebagai seorang penampil, penari, dan penyair asal Filipina ini fokus pada mitos kawao. Kawao’ dalam mitologi orang Mandar, setidaknya di pesisir, adalah sosok hantu laut berbahaya yang menjelma sebagai seekor gurita raksasa bertentakel tiga. Sebelum berlayar, para pelaut biasanya melakukan ritual khusus agar tidak diganggu oleh kawao.
Belum lama ini warga pesisir digemparkan dengan hilangnya 5 nelayan saat melaut. Nerisa juga mendatangi salah satu keluarga korban. Ia mendapatkan bahwa keluarga korban yang percaya bahwa korban masih hidup, sempat mendatangi dukun dan melakukan ritual tradisional dengan praktik agama leluhur.
Beberapa hal tersebut nantinya akan direpresentasikan Nerisa dalam karyanya di pameran Biennale Jogja XV. Sebagai seorang penampil, Nerisa sering menggabungkan instalasi dengan performans. Karya-karya Nerisa sebelumnya menyentuh beragam tema, antara lain tentang agama, kekerasan, kehidupan setelah kematian, dan sebagainya. Dua karyanya, masing-masing berjudul “Elegy 8: Pacific Ocean” dan “Infinite Gestures: Equinox” menghadirkan laut dan pesisir sebagai latar sekaligus simbol.
Sedangkan Arif Setiawan yang dikenal telah lama bergelut dalam dunia pertunjukan teater sebagai seorang sutradara di Pontianak mengunjungi pedalaman Alu yang terdapat banyak hutan bambu. Ia berusaha membandingkan tradisi Mandar di sungai dengan wilayah pesisir.
Para seniman residensi kelana laut ini juga sempat camping di atas bukit Pulau Karamasang. Di pulau tak berpenghuni ini, para seniman bisa merasakan bagaimana kehidupan di tengah lautan luas, dimana pada kegelapan malam hanya terlihat bintang-bintang bertaburan dan bimasakti dengan jelas. Mereka juga sempat mengamati bagaimana proses penangkapan ikan di laut dangkal.


Menurut Iwan pada Residensi Kelana ini juga menjadi pertama kalinya perpustakaan dan museum Nusa Pustaka yang didirikannya digunakan untuk tempat tinggal. Ke depannya sebagai bentuk layanan untuk kegiatan literasi, Nusa Pustaka akan terbuka sebagai tempat tinggal untuk proyek penelitian dan program kesenian lainnya.
Kurator Biennale Jogja XV Akiq AW menjelaskan bahwa perjalanan berkelana menjadi sesuatu yang penting. Tradisi seniman saat ini, menurutnya lebih banyak berkutat di studio, media sosial, internet, dan budaya pop lainnya, sehingga ada hal yang kurang dari sisi ‘pengalaman tubuh’. Karena itu Residensi Kelana bukan hanya sekadar riset, namun para seniman juga perlu ikut mengalami dan mengamati. “Di sini pengalaman tubuh menjadi sangat diperlukan. Bagaimana mereka merasakan perjalanan dengan bis, perahu, pesawat, bertemu masyarakat setempat, dan menemukan pengalaman lainnya,” ujarnya.
Hasil dari Residensi Kelana ini nantinya akan dipamerkan di lantai 3 Jogja National Museum saat pameran Biennale Jogja mendatang. Menurut Akiq pada pameran Biennale Jogja XV sudah tidak ada lagi alasan untuk ‘optimis’. Pameran ini akan berbeda dari gelaran Biennale Jogja sebelum-sebelumnya, “Pameran ini nantinya akan lebih gelap, suram, minor, dan mengangkat titik kulminasi kehancuran,” tegasnya. (*)


Teks: Kiki Pea
Foto: Ridwan Alimuddin & Relawan Perahu Pustaka