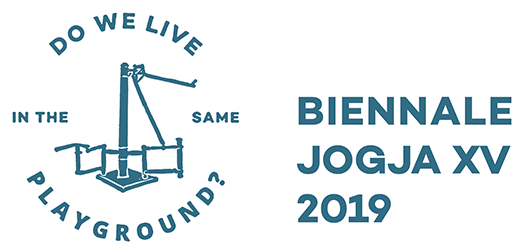Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kami merasa perlu untuk terlebih dahulu mendedahkan secara sederhana bagaimana pinggiran akan dipandang. Secara istilah, pinggiran selalu dikaitkan dengan lokasi geografis yang berada di luar kawasan pusat, entah kawasan satelit maupun rural (dalam istilah lain; pelosok).
Padahal, pinggiran tidak melulu soal tempat, tetapi yang juga penting adalah tentang subjek atau komunitas yang menghidupinya. Subjek-subjek yang tidak diuntungkan atau dirugikan secara ekonomi-politik di dalam struktur masyarakat tertentu. Karena itu, (subjek) pinggiran sudah barang tentu juga hadir di kawasan utama, yang secara antagonistik menjadi antinomi bagi “yang pusat”.
Secara ringkas, pinggiran mencakup isu-isu, praktek hidup atau subjek yang tidak/belum masuk menjadi wacana akademis, kebijakan publik, dan wacana media. Juga terkait dengan masalah relasi kuasa, perihal bagaimana subjek pinggiran berhadap-hadapan dengan kekuasaan yang hegemonik di manapun subjek-subjek atau masyarakat pinggiran itu hadir.
Pandangan ini setidaknya bisa membantu kita untuk memperluas cakupan pembicaraan mengenai pinggiran dan melihat narasi jenis apa yang berupaya ditawarkan oleh sesuatu yang ditandai atau menandai dirinya sebagai “pinggiran”.
Sebagai isu, pinggiran bisa kita kaitkan dengan berbagai persoalan yang berlangsung di sekitar kita. Masalah ketidakadilan gender, pelanggaran hak asasi atas kelompok masyarakat tertentu, persoalan perburuhan terutama yang terkait dengan isu buruh migran, diskriminasi berdasarkan ras atau agama, dan lain-lain. Sementara dalam soal praktek hidup, bisa kita lihat dari berbagai laku hidup yang telah dipraktekkan secara turun-temurun, yang diwariskan melalui pengajaran tradisi, mitos-mitos yang dituturkan, serta yang melihat hubungan manusia dengan alam sebagai sebuah kesatuan, yang tersingkir karena cara hidup eksploitatif-kapitalistik yang melihat kuasa manusia atas alam.
Isu-isu dan praktek hidup dari subjek-subjek pinggiran semacam itu yang kiranya perlu dilihat, dipelajari, dan memungkinkan untuk dibicarakan dalam konteks Biennale. Meskipun rentan jebakan, membicarakan pinggiran di dalam konteks Biennale bukanlah hal yang mustahil dilakukan. Lagipula, sebagai sebuah perhelatan seni rupa, Biennale mempunyai cara ungkapnya sendiri untuk membicarakan persoalan-persoalan yang berusaha diusung. Biennale perlu diposisikan sebagai salah satu metode atau instrumen untuk membicarakan berbagai jenis persoalan, yang di dalam konteks ini, mengenai persoalan pinggiran.
Pinggiran yang hendak dibicarakan di dalam Biennale Jogja perlu diberikan konteks, sehingga tidak sekadar menampilkannya sebagai sekumpulan data telanjang lalu merayakannya dengan gegap-gempita, tetapi melihat pinggiran dalam konteks terkininya dan dengan siapa mereka berhadap-hadapan.
Biennale Jogja Equator #5 yang menggandeng negara-negara di kawasan Asia Tenggara sebagai mitra kolaborasi, tidak diarahkan untuk “merepresentasikan” pinggiran itu sendiri–atau dalam istilah yang cukup menyebalkan: “sebagai sumber inspirasi”. Akan tetapi dengan berusaha menunjukkan bagaimana yang pinggiran mengekspresikan dirinya dan membicarakan narasi atau persoalan tentang dirinya sendiri.