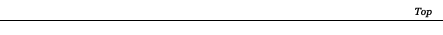GUGUR GUNUNG, GOTONG ROYONG, dan JAMMING
February 15, 2011

Yoshi Fajar Kresno Murti, Koordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan “Indonesia Visual Art Archive”, Yogyakarta, Indonesia
Tiga kosakata yang meriah dan menarik untuk diperiksa dari perhelatan Biennale Jogja (BJ) X 2009 yaitu penggunaan idiom lokal seperti “gugur gunung” dan “gotong royong” yang bersanding dengan penggunaan kosakata Bahasa Inggris sebagai representasi idiom global yaitu: “jamming”. Ketiga kata atau idiom tersebut selalu hadir disebut-sebut dalam setiap terbitan dan menjadi kata kunci perhelatan BJ X 2009. Gugur gunung dan gotong royong maknanya mirip. Gugur gunung lebih mengacu kepada arti yang lebih aktif yaitu bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan (bersama). Sedangkan gotong royong mengacu kepada sifat kebersamaan yang dihasilkan dari bekerja bersama-sama (tolong- menolong, bantu-membantu). Jamming ada di dalam kalimat “Jogja Jamming” yang merupakan tema BJ X. Sedangkan gugur gunung dan gotong royong merupakan dua kata yang hampir selalu diucapkan dalam setiap pidato, tulisan dan wawancara selama perhelatan BJ X. Persandingan kosakata lokal dan global tersebut oleh Butet Kertaredjasa – Direktur BJ X 2009 dalam pidato malam pembukaan BJ X – dipakai untuk menggambarkan situasi dan semangat yang menyelimuti BJ X, yaitu sebagai berikut:
Situasi ini kiranya bisa diibaratkan dalam sebuah idiom Jawa, gugur gunung, dimana gotong royong, kebersamaan, masih kental dalam proses berkesenian di Yogyakarta. Dinamika ini bisa juga dilukiskan sebagai jam session dimana masing-masing seniman saling berdialog, berbagi, serta menciptakan kreasi dalam harmoni. Inilah JOGJA JAMMING yang sebenar-benarnya.
Selama perhelatan Biennale Jogja X berlangsung, aroma gugur gunung dan gotong royong paling sering dilukiskan dari keberadaan sekretariat BJ X yang disokong, ditanggung dan dihidupi dengan cara bersama-sama, dari mulai soal konsumsi, fasilitas hingga peralatan yang digunakan. Sokongan dan dukungan bersama ini telah menghadirkan suasana kebersamaan yang sukar dilukiskan dan romantisme yang membekas dalam hati setiap orang yang datang kesana. Gugur gunung dan gotong royong ini tampaknya juga terlukiskan melalui kerja bersama dalam proses penciptaan karya yang dipamerkan dalam BJ X. Seperti saya saksikan sendiri, ketika suatu sore di rumah salah seorang pengurus BJ X, saya melihat kain kanvas bergulung-gulung hasil sumbangan dari seseorang yang akan digunakan untuk dilukis seniman-seniman yang nantinya akan dipajang di jalan-jalan. Semangat gugur gunung dan gotong royong ini secara lebih besar telah terjadi ketika penyelenggaraan BJ X yang notabene bersih dari transaksi penjualan karya, dalam pelaksanaannya tidak akan bisa berjalan tanpa didukung oleh berbagai pihak yang memberikan perhatian, kerja, bantuan fasilitas dan dana baik dari perorangan, komunitas, institusi pemerintah, lembaga nirlaba, maupun sponsor dari perusahaan-perusahaan profit.
Gugur gunung dan gotong royong dalam konteks masyarakat Yogyakarta dan BJ X sebagai contoh kasus seperti diuraikan diatas sesungguhnya merupakan sebuah praktik dari semangat subsidiaritas. Sebuah semangat yang berkaitan erat dengan cara bagaimana berbagai lapisan dan tingkatan dalam masyarakat saling berhubungan, berkomunikasi, dan membantu dalam mengupayakan hasil terbaik bagi semua orang dan pihak. Semangat subsidiaritas masih terus bisa dipraktikkan hingga sekarang di Yogyakarta. Dalam hal ini, perhelatan BJ X selain menjadi ruang eksperimentasi penyelenggaraan Biennale Jogja yang sudah berlangsung sepuluh kali, sekaligus ia juga menjadi tempat untuk memotret bentuk-bentuk (perubahan) inter-relasi dalam kehidupan medan seni rupa dan medan sosial masyarakat Yogyakarta. Semangat subsidiaritas (masih) hadir dan dirasakan tidak saja dalam BJ X tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Yogyakarta. Semangat itu pula yang menandai BJ X sebagai sebuah awal yang baik dan sebuah transisi (kembali) kepada penyelenggaraan biennal-biennal berikutnya.
Sebagai semangat, gugur gunung dan gotong royong dalam BJ X 2009 rupanya cukup tepat untuk mengawali transformasi perubahan perhelatan Biennale Jogja di masa depan. Ia mampu menggerakkan medan seni dan medan sosial masyarakat Yogyakarta dalam kebersamaan yang khas dan dalam momen perubahan yang pas. Namun, selanjutnya ia juga harus diterjemahkan dengan konteks dan tantangan yang baru. Demikian juga, sebagai sebuah bentuk, kosakata jamming rupanya juga cukup akurat untuk menggambarkan cara menggerakkan individu, komunitas, lembaga dan sumber daya yang ada di dalam Yogyakarta, yang selalu berada di dalam ketegangan antara individu dan kolektivitas, yang lokal dan yang global. Ia tidak hanya berhenti pada tema. Jamming sudah dipraktikkan, tetapi tidak bisa mapan dan harus ber-improvisasi terus. Gugur gunung dan gotong royong sudah teruji, tetapi tidak harus mandeg dan menjadi slogan, ia juga harus bergerak dalam dinamika perubahan masyarakat Yogyakarta.
Perdebatan soal-soal mengenai manajerial, bentuk penyelenggaraan dan konsep Biennale Jogja memang harus terus-menerus dibangun dan dimunculkan secara sehat. Apakah ia mau berbentuk festival maupun bersifat internasional. Apakah ia dikelola dengan cara non profit ataupun disesuaikan selera pasar. Apakah Biennale Jogja bisa menjadi ruang eksperimentasi ataupun ruang promosi bahkan sebagai ruang advokasi, dan lain sebagainya… Biennale Jogja memang harus berubah dan menghadapi tantangan yang lain setiap saat. Bagaimana ia menggerakkan semangat subsidiaritas, dan pada akhirnya memutar sumber daya dan energi dalam dinamika masyarakat Yogyakarta sendiri.
(Yoshi Fajar Kresno Murti, Koordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan “Indonesia Visual Art Archive”, Yogyakarta, Indonesia)