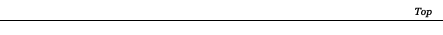Seniman dan Masyarakat
February 15, 2011

Nuraini Juliastuti, Peneliti Kunci Cultural Studies Center, Yogyakarta, Indonesia
Dari waktu ke waktu, para seniman Indonesia selalu berputar di perdebatan tentang definisi hubungannya dengan masyarakat. Turunan dari perdebatan tersebut sangat banyak, tetapi rasanya ia berputar pada hal-hal berikut ini: Apakah arti masyarakat, atau publik? Apakah masyarakat hanya dimaknai sebagai subyek, atau sekedar sebagai sumber inspirasi dan tempat dilakukannya praktik berkesenian? Apa cara terbaik untuk mendekati dan merespon persoalan masyarakat? Lebih jauh, perdebatan ini mengarah kepada soal ‘model seniman macam apa yang diinginkan’? Apakah ‘seniman sebagai pencatat’, ‘seniman sebagai peneliti’,, ‘seniman sebagai fasilitator’, atau yang lain? Semuanya adalah kategori-kategori yang kita tahu jauh dari ketat dan punya batasan-batasan yang tidak jelas.
Juga, dengan jelas kita bisa melihat bahwa perdebatan tersebut tak terelakkan selalu mengarah kepada tema klasik ‘seni untuk seni’ atau ‘seni untuk masyarakat’.
Dan dalam usaha mencari definisi-definisi atas apa yang dilakukannya di tengah masyarakat, di saat yang bersamaan, terus menerus bisa kita lihat upaya penolakan untuk dilekati dengan sistem nilai tertentu oleh yang lain. Hal ini bisa dengan jelas kita lihat, misalnya, pada peristiwa dimana seorang seniman dilabeli dengan ‘fasilitator’ dan penolakan keras si seniman terhadap pelabelan tersebut. Terdapat kesan ‘memberi intervensi’ dalam pelabelan tersebut, yang ditolak, sementara tahu bahwa memang terdapat intervensi dalam tiap praktik budaya, dalam arti terdapat metode tertentu yang berusaha ditanamkan oleh si seniman, atau fasilitator dalam hal ini, kepada masyarakat. Dalam catatan lain, ia juga tampak dalam suatu peristiwa dimana si seniman dituntut untuk terus menerus mencari cara untuk berperan lebih aktif, dan mendorong batas-batas, tetapi sekaligus terdapat ketakutan dari si seniman sendiri untuk dianggap melangkah terlalu dalam dengan pilihan praktik berkeseniannya.
Perdebatan seperti saya gambarkan di atas terasa tidak pernah tuntas. Jika suatu kesadaran akan situasi jaman merupakan prasyarat mutlak untuk melakukan pendefinisian ulang peranan seniman dalam masyarakat, maka saat ini kita berada dalam situasi dimana kesadaran tersebut tidak datang dengan mudah. Hasilnya, seperti kita lihat pada pelaksanaan Biennale Yogyakarta X dua tahun lalu, dengan limpahan karya-karya seni di ruang publik, adalah perdebatan tentang misalnya ‘apakah arti publik’ bagi seniman, dan apakah ini adalah ‘seni publik’ atau ‘seni di ruang publik’, tampak menghadapi kemunduran. Yang kita lihat adalah pengulangan debat lama, dan bukan langkah maju menuju produksi budaya yang lebih produktif.
Tidak berarti saya berpendapat bahwa sampai sejauh ini, para seniman tidak kunjung bisa menemukan metode-metode kerja yang tepat bagi dirinya. Merentang pandangan dari Mooi Indie, Gerakan Seni Rupa Baru, Apotik Komik, Taring Padi, Ruang Rupa, dan lain-lain, dengan jelas ditemukan bahwa ada usaha demikian.
Persoalannya adalah: apakah semua pencarian metode kerja tersebut juga dibarengi dengan usaha untuk memikirkan serangkaian strategi untuk membuat ciptaan metode tersebut berkelanjutan?
Tanpa punya kehendak untuk merancang strategi penjamin keberlangsungan metode tersebut, maka ke dalam, seperti saya sebutkan diatas, seni rupa hanya akan terus diputar di perdebatan lama. Dan ke luar, pencarian metode kerja tersebut tidak akan punya pengaruh apapun terhadap situasi terkini jaman karena ia berarti tidak meletakkannya dalam kerangka eksperimen terus menerus. Dan tidak meletakkannya dalam kerangka eksperimen berarti tidak meletakkannya berhubungan dengan konteks-konteks jaman sekarang. (Nuraini Juliastuti, Peneliti Kunci Cultural Studies Center, Yogyakarta, Indonesia)