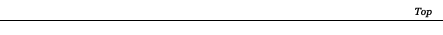Yogyakarta, Situs dan Penduduknya : Dilahirkan untuk menjadi Artistik
February 16, 2011
Pandangan atas aset wisata utama propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disebut DIY), yakni budaya klasik Mataram dan Jawa, nampak jelas jika kita masuk ke situs web Dinas Pariwisata DIY. Ilustrasi foto yang dimaksudkan jadi ciri DIY, yakni bangunan Kasultanan seperti Kraton dan Tamansari, atau bukti peradaban kuno seperti Candi Prambanan, Ratu Boko, dan Borobudur. Peletakannya sebagai ilustrasi yang mewakili Propinsi DIY dianggap wajar karena, sebagian besar pengunjung Candi Prambanan adalah wisatawan yang berkunjung dan tinggal sementara di pusat Kota Yogyakarta (selanjutnya disebut Jogja). Sebagai titik bertolak, Jogja memang menyediakan banyak pilihan obyek wisata di dalam maupun luar wilayah administratifnya.
Infrastruktur Jogja dinilai sudah mampu mengakomodir wisatawan dengan lebih dari 450 hotel berbintang dan melati, juga jalur transportasi luar kota dan internasional melalui Stasiun Kereta Api dan Bandar Udaranya. Situs web Bandara Internasional Adisutjipto menyebutkan 8 maskapai penerbangan beroperasi di gerbang udara wisata terpenting dalam kawasan segitiga Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang) ini, termasuk dua maskapai yang melayani penerbangan internasional Jogja-Singapura dan Malaysia.
Relasi pariwisata dengan seni dan budaya di Indonesia diturunkan langsung dari cara pandang negara terhadap pariwisata sejak Kabinet Pembangunan VII hingga Kabinet Indonesia Bersatu II. Signifikansinya terletak pada dua elemen kunci yang dikandung, yakni interaksi dan keterlibatan. Ia adalah refleksi dinamika masyarakat setempat, yang mengambil wujud mulai dari reproduksi ritual tradisional, festival dan arak-arakan, hingga pameran dan pertunjukan seni kontemporer. Sehingga, peristiwa seni budaya bukan komoditi dagang, melainkan substansi dari keinginan masyarakat kontemporer untuk terhubung dengan kondisi global, menjadikannya medium dimana pertukaran berlangsung. Peristiwa seni budaya adalah bahasa universal untuk arena tatap muka.
Indonesia mengenal pertukaran budaya melalui adanya peristiwa. Jika ritual tradisional dilakukan di bangunan peradaban kuno atau di atas bentang alam dan dalam kampung, maka festival/arak-arakan dan pameran/pertunjukan seni kontemporer berlangsung di ruang-ruang interaksi masyarakat masa kini. Di Jogja, seluruhnya terlanjur berlangsung simultan dan sering nampak tidak mengalami intervensi negara. Pelaku seni Jogja baik yang intens di wilayah tradisi maupun ekspresi kekinian, sama-sama tidak bekerja dalam infrastruktur yang murni berasal dari kebijakan pemerintahan formal. Gali lubang tutup lubang dan gotong royong adalah mekanisme bertahan hidup. Mekanisme yang barangkali menyulitkan peneliti saat menyusun statistik sederhana untuk mendeteksi taraf keterlibatan pelaku seni Jogja dalam dinamika seni Indonesia. Namun, mekanisme ini telah membuktikan bahwa seni budaya, sebagaimana banyak sektor lain di Indonesia, mampu terus direproduksi dengan segala konsekuensinya, tanpa intervensi pemerintah pusat.
Sampel signifikan untuk pernyataan di atas dalam peristiwa seni kontemporer, bisa ditemukan dalam penyelenggaraan Biennale Jogja X 2009 “Jogja Jamming” (selanjutnya disebut BJ X). Perhelatan dua tahunan ini berulangkali dimodifikasi secara visi maupun pelaksanaan, ditentang dan ditantang, dipuji dan dihujat, namun tidak pernah sepi dari ekspos. Perubahan signifikan dalam BJ X dari Biennale Jogja sebelumnya terletak pada mekanisme penyelenggaraan dan kepanitiaan yang liar, antisipatif, sekaligus akrobatik.
Liar karena perhelatan ini kembali mencatatkan diri sebagai kota yang mampu menampilkan bermacam-macam medium di ruang interaksi sehari-hari yang tidak dimaksudkan sebagai ruang seni, sejak Aksi Seni Rupa Publik 1998, Disini akan Dibangun Mal 2004, dan Biennale Jogja VIII 2005. Ruang yang dimaksud adalah jalan raya, dimana banyak kepentingan bertemu dan beradu. Ia menyerupai pasar, plaza, alun-alun, taman, seraya terus memenuhi fungsinya sebagai infrastruktur fisik untuk lalu lalang. Selama satu bulan, jalan raya Jogja utara dan selatan dihinggapi bentuk-bentuk jenaka nan absurd. Ia menjadi wilayah transit seniman penggenjot becak yang dinaiki replika fiberglass berwujud Presiden Amerika Serikat ke-44, sampai seniman yang mengajak 500 orang untuk pura-pura mati selama dua kali 60 detik, sekaligus wilayah sengketa karena ketidaknyamanan beberapa pihak terhadap bentuk karya seni yang diletakkan dalam yurisdiksinya.
BJ X antisipatif dan akrobatik karena cepat menangkap gejala-gejala yang belakangan berlangsung dalam tarik menarik kepentingan pelaku seni. “Jogja Jamming” adalah keinginan untuk meleburkan berbagai kepentingan dalam kuali besar Biennale ala Jogja. Fokus narasi Jogja Jamming terletak pada dinamika seni di Indonesia, persis di perilaku berkarya seniman di Jogja yang punya beragam latar belakang budaya. Lebih dari 200 pelaku seni tua, muda, masih hidup, sampai yang sudah meninggal bisa menyertakan karyanya. Belum cukup menampilkan karya-karya seniman Indonesia di Jogja, stabilitas posisi Jogja sebagai kota seni budaya dibuktikan melalui pameran dokumen dan replika karya seni temporer. BJ X telah merealisasikan mimpinya dengan mendandani Jogja dengan tata rias yang berhasil menarik perhatian warga Jogja maupun wisatawan nusantara dan mancanegara.
Dinas Pariwisata DIY mencatat kunjungan 715.610 orang wisatawan mancanegara, dan 7.589.044 orang wisatawan nusantara sepanjang 2009. BJ X sendiri dikunjungi lebih dari 7000 orang sepanjang pelaksanaannya, belum termasuk orang-orang yang berfoto di sebelah karya seni di jalan raya dan tidak tercatat dalam buku pengunjung. Perhitungan kasar menunjukkan bahwa BJ X punya kontribusi sebesar 5% untuk jumlah wisatawan bulan Desember 2009, sementara 1% penduduk Jogja dari kategori non-seni menunjukkan minatnya pada suatu peristiwa seni kontemporer. Persentase ini diperoleh dari asumsi 50-50 antara pengunjung yang termasuk wisatawan atau penduduk, dan peristiwa seni dengan rasio 1:8 terhadap obyek wisata lain. Sektor yang dilibatkan dalam penyelenggaraan mencakup sektor seni budaya, katering, pendidikan, jasa angkut dan transportasi, parkir, perizinan, dan sektor informal lain. Dengan kata lain, 70% sektor yang beroperasi di Jogja telah dilibatkan dalam BJ X, sebagaimana peristiwa seni masif serupa.
Di sisi lain, pelukis, pematung, dramawan, penyair, penulis, pemain musik, penyanyi, pembuat film, dan pengrajin dengan capaian internasional, yang sebagian tidak lahir di DIY namun memilih untuk tinggal di Jogja, adalah sumber daya manusia yang jarang diapresiasi di rumah mereka sendiri. Ruang-ruang seni yang sejak awal dibangun di atas lahan layak dan strategis, hanya ditanggung secara de jure. Kondisi ini menghambat sirkulasi wisatawan untuk menyaksikan peristiwa kesenian sehari-hari.
Memiliki jaringan solid adalah kunci untuk optimalisasi peluang dan kemampuan kedua belah pihak dari sektor yang beroperasi dengan logika berbeda, pariwisata dan kesenian. Keinginan pelaku seni untuk mendekatkan karyanya pada audiens tidak perlu bertahan sebagai mitos, karena terbatasnya infrastruktur Indonesia untuk kesenian sudah terbukti tidak menghambat produksi kreativitas di Jogja.
Bagi promotor wisata, keterbatasan teknis seperti penyediaan alat transportasi bisa disiasati dengan rekomendasi agenda kunjung di kawasan berdekatan. Jogja boleh bangga karena mampu mempertahankan becak dan sepeda di jalan rayanya sebagai sarana transportasi mudah, khas, ramah lingkungan; ditinggali orang-orang yang ramah juga senang bergurau; dan menjadi laboratorium seni budaya untuk pelaku seni Indonesia. Selamat datang di Jogja, selamat menikmati sajian seni kontemporer dalam menu wisata Anda. (Pitra Hutomo, Archivist, Indonesia Visual Art Archive, Yogyakarta, Indonesia)
* Sumber untuk tulisan ini diperoleh terutama dari Newsletter Biennale Jogja X 2009 “Jogja Jamming”, situs web dan laporan penelitian UNWTO, situs web Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI, situs web Dinas Pariwisata DIY, dan situs web Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Yogyakarta
** Dua karya yang disebutkan dalam paragraf ketujuh tulisan ini adalah karya berjudul “Membuat Obama dan Perdamaian yang Dibuat-buat” oleh Wilman Syahnur, dan “Semenit Senyap” oleh Agung Kurniawan