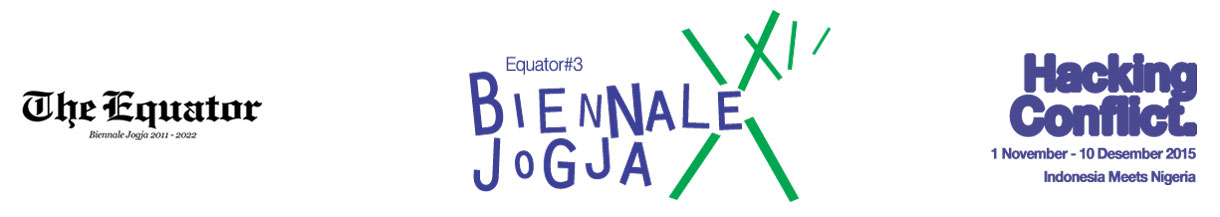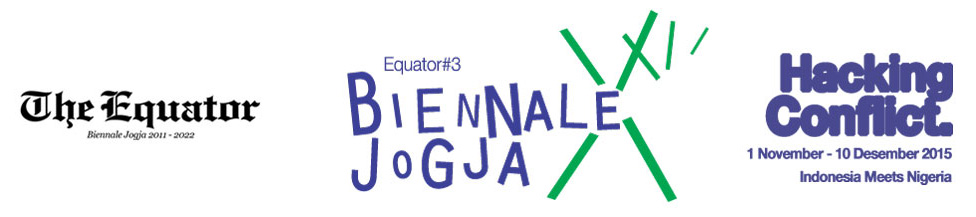Selama sebulan, saya dan kurator BJ XIII, Wok The Rock, berkesempatan mempelajari Nigeria, tepatnya dari tanggal 5 November hingga 5 Desember 2014. Pulang dari Nigeria tentu tidak serta-merta membuat kami menjadi ‘pakar’ atau ‘ahli’ tentang negara itu. Namun pengalaman merasakan hidup di sana mampu menjadi energi sekaligus jalan masuk untuk mempelajari Nigeria lebih lanjut. Barangkali, kesempatan sebulan itu lebih tepat disebut sebagai perjalanan observasional daripada perjalanan riset, mengingat keberadaan tema yang masih bergulir dalam proses. Jika dalam penelitian lapangan, peneliti membekali diri dengan metode dan rumusan masalah yang mengandaikan kejelasan tema, perjalanan kali ini juga berangkat dengan bekal meski sedikit berbeda, yakni bekal catatan perjalanan singkat pertama yang sudah dilakukan Arham Rahman, Rain Rosidi dan Yustina Neni. Selain bekal di atas, tentunya kami juga memiliki minat serta pandangan pribadi yang tidak bisa dilepaskan dalam proses pencarian, yang bahkan mempengaruhi alur pencarian.
Melampaui Stereotype
Seperti yang dituliskan dalam catatan perjalanannya, salah satu bekal yang dibawa dalam perjalanan tim pertama adalah bayangan atau imajinasi orang kebanyakan ketika membicarakan Nigeria. Bayangan tersebut tidak jauh-jauh dari apa yang dikabarkan media secara masif, seperti berita pengeboman yang dilakukan Boko Haram, penyebaran virus Ebola, serta persoalan Narkoba yang sering kali diberitakan melibatkan warga Nigeria. Dalam laporan perjalanannya, hal-hal itu kemudian disebut sebagai “Gosip dan Mitos”.
Ebola yang dibesar-besarkan media sudah ditangkis dengan temuan lapangan yang menunjukkan adanya antisipasi yang tegas dari pemerintah serta masyarakat Nigeria. Di lapangan, tim riset pertama mengalami beberapa lapis pemeriksaan suhu tubuh di tempat-tempat umum. Tim keduapun menemukan kondisi serupa. Masyarakat memang nampak sudah sadar dengan bahaya penyebaran Ebola ini.
Sementara mengenai Boko Haram, catatan riset pertama menunjukkan bahwa fenomena ini kurang lebih merupakan warisan kolonial. Sejak dulu, pemerintah kolonial dengan sengaja membuat perbedaan serta jarak antara masyarakat Nigeria yang berada di wilayah Utara dan Selatan. Keterlibatan masyarakat sipil sangat dibatasi dalam politik lokal di wilayah Utara. Hanya orang-orang lokal patuh yang diberikan pekerjaan administrasi dalam pemerintah kolonial. Sementara daerah yang tidak mau patuh, ditundukkan dengan kekuatan militer setelah diplomasi buntu. Lain halnya dengan wilayah selatan. Di sana, pemerintah kolonial mendukung berkembangnya elit terdidik dengan sekolah gaya Eropa.
Dari temuan tim riset pertama, jarak dan bahkan kebencian antara Utara-Selatan yang ada di Nigeria justru dipelihara untuk kepentingan kolonial. Jika dilihat secara lebih global maka fenomena Boko Haram ini lebih dijadikan sebagai isu strategis bagi negara penjajah (atau yang sekarang sering disebut sebagai negara dunia pertama) untuk mempertahankan posisinya di hadapan negara di luar negara “pertama”. Hal ini terkait dengan wacana besar yang sering kita dengar dari media arus utama, yakni wacana “perang melawan teror”. Dengan adanya fenomena Boko Haram ini, wacana perang melawan teror semakin mendapatkan pembenaran.
Dari catatan di atas, saya sepakat untuk melanjutkan semangat dari tim pertama untuk mematahkan stereotype yang dibangun, terutama oleh media, kemudian melampauinya dengan data-data yang tidak jarang analitis dalam melihat suatu peristiwa.
Mengenai persoalan Ebola, saya menemukan sebuah kolom yang dimuat di harian Leadership, Nigeria tertanggal 10 November 2014. Kolom opini ini ditulis oleh Robtel Pailey, dengan judul “Nigeria, Ebola and The Myth of White Saviours”. Lewat opininya itu, Pailey menulis bahwa dalam persoalan Ebola ini, orang-orang kulit putih seolah muncul sebagai penyelamat yang datang ke negeri Afrika untuk memberangus Ebola. Kesan yang kemudian berkembang menjadi mitos tersebut ia rasakan sendiri, mengingat kebanyakan ahli yang berbicara tentang Ebola didominasi oleh orang kulit putih. Padahal selama tiga bulan, Nigeria menangani kasus Ebola tanpa campur tangan asing. Setidaknya terdapat tiga institusi yang menjadi penanggung jawab, yakni Nigerian Center for Disease Control, the Nigerian Field Epidemiology Training Program, dan Lagos State Ministry of Health. Pailey menyebutkan bahwa ketiga institusi tersebut secara cepat merespon penyebaran virus ini dengan melakukan karantina pada pasien yang diduga menderita, lalu menelusuri dengan detail jejak-jejak kontak dari pasien yang sudah dinyatakan positif terinfeksi. Selain itu, di ranah publik juga dilakukan kampanye besar-besaran sebagai upaya pencegahan.
Di penghujung tahun 2014, Nigeria dinyatakan terbebas dari Ebola. Akan tetapi, bukan pemerintah ataupun masyarakat setempat yang diapresiasi, melainkan institusi besar semacam WHO dan US Centers for Disease Control yang dianggap punya peran besar. Seorang Novelis dari Nigeria bernama Adichi tidak ragu mengatakan hal ini sebagai kebohongan. Dengan terbuka, kritikan ia tujukan secara langsung pada The Washington Post dan New York Times yang telah menyebarkan kebohongan di publik dunia.
Kabar Ebola tentu bukan kabar yang kita dengar puluhan tahun silam. Bahkan saya tidak yakin berita ini benar-benar ditutup. Dari kabar itu pula, mata kita seolah dibuka lebar-lebar untuk menyaksikan sebuah upaya dominasi ala kolonial yang terjadi hari ini, bukan di masa lalu. Pelajaran inilah yang kemudian kami bawa pulang ke Indonesia, untuk dijadikan bahan pelajaran bersama. Dari fenomena ini kita bisa belajar bahwa kolonialisme tidaklah selesai, tetapi muncul di ruang yang sering kali subtil. Sekilas, masalah penyebaran virus merupakan persoalan kesehatan semata yang hampir jauh dari kepentingan politik kolonial. Namun ternyata, dalam persoalan kesehatan terdapat kepentingan yang tidak ringan, kepentingan status quo dalam memelihara kuasanya melalui politik wacana. Menurut saya, di sinilah perjumpaan Indonesia dan Nigeria menemui urgensinya; sebagai negara yang sama-sama memiliki luka atas pengalaman menjadi negeri terjajah.
Membayangkan Kelas Menengah Nigeria
Pembahasan dan pembacaan yang dilakukan atas dua persoalan tersebut merupakan pembacaan menarik yang tentunya dipertahankan dalam catatan riset kedua ini. Selain itu, tim riset pertama juga mengemukakan asumsi terkait dengan dinamika masyarakat Nigeria. Tim pertama mengatakan bahwa Nigeria merupakan negara yang hampir tidak ada kelas menengahnya. Mengenai kelas menengah ini, ukurannya memang perlu diketahui secara lebih rigid melalui hitung-hitungan statistik. Akan tetapi, dari perjalanan riset yang dilakukan tim kedua, kelas menengah banyak ditemui, terutama di kalangan seniman dan terpelajar yang banyak menjadi narasumber penelitian. Dalam beberapa kesempatan, wawancara dilakukan di rumah tinggal maupun studio seniman. Dari situlah tim menemui gambaran mengenai kelas menengah yang tidak ditemui tim riset pertama. Beberapa seniman ditemui di apartemen sempitnya yang berada di tengah kota Lagos. Tim bahkan sempat tinggal selama kurang lebih tiga hari di apartemen salah satu seniman tari yang berada di tengah perkampungan warga.
Waktu itu kebetulan merupakan hari pertama tim menginjakkan kaki di Lagos. Dengan bekal referensi minim atas penginapan maka tawaran dari seorang seniman tari untuk menyewa kamar di apartemennya kami iyakan. Selama tiga hari pertama di Lagos, kami langsung merasakan serangan suara yang datang dari berbagai penjuru. Kami sempat mencicipi bagaimana rasanya menjadi kelas menengah di tengah kota Lagos. Akses menuju ke pusat kota, yang konon menjadi pusat seni dan budaya Nigeria, memang tidak jauh. Hanya perlu sekitar lima belas menit dengan menggunakan angkutan umum. Kami biasa menggunakan angkutan umum beroda tiga yang sering disebut dengan ‘bajaj’ di Jakarta jika jarak tidak terlalu jauh. Jika jarak agak jauh maka angkot pun menjadi pilihan yang menarik, karena mudah dan murah. Jika jarak lebih jauh lagi maka apa boleh buat, taksi menjadi pilihan terakhir, karena bagaimanapun juga secara fisik, kami terlihat seperti ‘orang asing’ di Nigeria.
Meski ada sisi ‘asing’ dari tubuh kami yang tidak bisa dihindari, dengan menempatkan tubuh kami di tengah masyarakat, kami membayangkan keberadaan kami sebagai kelas menengah. Bayangan kami, kondisi kelas menengah masyarakat Nigeria tidak jauh-jauh dari beberapa narasumber yang kami temui di Lagos, yang hidup di rumah ataupun apartemen biasa dan di tengah pemukiman padat penduduk, yang tiap harinya sangat akrab dengan suara berisik generator. Masyarakat kelas menengah yang setiap harinya juga harus berjuang mengelola keuangan supaya di akhir bulan bisa tetap bertahan di tengah harga barang dan makanan yang bisa dibilang tidak murah di satu sisi, tetapi tetap bisa berkomunikasi dengan teman dan saudara menggunakan smartphone di sisi lain.
Persoalan kelas sosial masyarakat Nigeria ini juga merupakan pekerjaan rumah dari tim riset BJ XIII. Sebagai PR, pengumpulan dan pengolahan data mengenai kelas sosial masyarakat ini akan terus berjalan meski masa penelitian lapangan berakhir, supaya ketika menyebut kelas menengah sudah tidak membayangkan lagi, tetapi juga menyajikan data.
Ruang Seni dan Persoalan Sosial
Mengenai keberadaan ruang seni yang tidak hanya berputar pada persoalan wisata serta seni yang tidak sebatas komoditas, menjadi salah satu fokus dalam pencarian tim kedua. Sebelumnya, tim pertama tidak banyak menemukan ruang seni yang dimaksud, praktik seni dengan spirit alternatif. Dengan perjalanan riset yang dilakukan selama satu minggu di Abuja dan Lagos, tim kedua maklum jika tim pertama belum mampu menjangkau ruang-ruang yang berupaya menjadi ruang alternatif. Barangkali karena acuan riset yang digunakan atau jaringan seni yang ditemui di lapangan, tim kedua banyak menemui seniman serta aktivis budaya yang bermain di ruang-ruang alternatif.
Yang perlu kita ingat ketika membicarakan ruang seni di sini, terbatas pada ruang-ruang yang kami temui, terutama di Lagos. Dan berbicara tentang Lagos, berarti berbicara tentang ruang kota yang pembangunannya seperti sengaja membiarkan jarak atau disparitas sosial dan ekonomi begitu menganga. Lagos terdiri dari Mainland dan Island. Sekilas sudah jelas bahwa bangunan megah yang ada di Island sengaja dipisahkan dari Mainland. Jembatan yang menjadi penghubung antar-pulau ini justru terasa memisahkan. Disparitas sosial ini juga sangat nampak dalam ranah seni. Galeri-galeri yang dikatakan komersil banyak terdapat di Island, kadang juga terdapat dalam hotel mewah ataupun sejajar dengan pertokoan dan butik elit. Sementara beberapa galeri di Mainland merupakan ruang pamer yang terlihat lebih sederhana dan tentu saja bukan di hotel.
Salah satu ruang seni yang berusaha keluar dari dominasi lingkaran pasar, dan memang tidak kebetulan terletak di Mainland ialah CCA, Center for Contemporary Art. Melalui penyebaran ilmu seni mutakhir dan eksplorasi praktik berkesenian seluas-luasnya, CCA mendukung muncul atau tumbuhnya praktik seni yang tidak bisa steril dari persoalan sosial dan politik. Selain CCA, terdapat Osh Gallery, sebuah galeri yang mendorong seniman bereksplorasi dengan medium yang tak terbatas. Galeri ini diinisiasi oleh Folakunle Oshun yang juga banyak belajar dari CCA. Sebagai inisiator sekaligus seniman, Fola mencita-citakan proses berkesenian yang bebas, terutama bebas dari tekanan pasar.
Peta seni Lagos kurang lebih nampak dari gambaran singkat di atas. Nampaknya, seni menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat atau persoalan sosial. Selain dari sisi infrastruktur, persoalan sosial juga banyak muncul sebagai tema karya ataupun rangkaian karya. Dari beberapa seniman yang kami temui, banyak di antaranya yang mengeksplorasi persoalan krisis energi yang terjadi di Nigeria. Krisis energi akut yang sehari-hari muncul melalui pemadaman listrik ini banyak dibahas dalam karya beberapa seniman. Selain itu, tema lingkungan juga banyak diminati. Terlalu sering bahkan. Sehingga muncul kecurigaan adanya pengulangan tema dan menjadi klise. Mengenai pengulangan ini, salah seorang seniman penting, Kainebi Osahenye, yang juga sering mengeksplorasi tema lingkungan berpendapat bahwa terdapat dua hal dari pengulangan ini; yang pertama ialah bahwa memang isu ini perlu untuk diulang karena kerusakan lingkungan memang di depan mata, kedua ia tidak mengingkari adanya pengulangan yang berujung pada klise.
Berbicara tentang persoalan sosial dan seni tentu tidak ada habisnya. Tema merupakan jembatan termudah dan paling eksplisit yang mampu menghubungkan seni dan persoalan sosial. Selebihnya, dibutuhkan pendekatan yang agak kaya dan ulasan yang lebih serius dalam mengolah persoalan ini, yang tentu tidak bisa dilakukan dalam catatan singkat dari perjalanan lanjutan ini.
Indonesia dan Nigeria dalam cerita Ankara
Berbicara tentang masyarakat dan ruangnya, tentu memiliki ribuan wajah, bergantung dari cara baca dan cara kita mendekatinya. Lagos sebagai ruang tentu memiliki banyak wajah, dan yang paling menonjol ialah kekayaan warnanya. Warna di sini bukan hadir sebagai metafor. Kekayaan warna yang dimiliki Lagos, salah satunya bisa dilihat dari bahan pakaian khasnya, yang oleh warga Nigeria disebut Ankara. Banyak yang menyebutkan bahwa Ankara ini merupakan “kain Afrika”. Beberapa orang bahkan dengan sengaja mengenakan pakaian berbahan Ankara untuk menunjukkan identitasnya sebagai warga Afrika. Di Nigeria, kain ini banyak digunakan oleh masyarakat sebagai bahan pakaian. Selain karena harganya yang terjangkau, kain ini dirasa cocok dengan iklim tropis, sebab konon 100% berbahan kapas.
Menariknya, Ankara yang dijadikan simbol identitas Afrika ini pada mulanya tidak diproduksi di Nigeria maupun Afrika. Ankara merupakan kain yang awalnya diproduksi oleh beberapa perusahaan kain di Belanda sebagai tiruan dari kain Batik Indonesia. Konon, perusahaan-perusahaan Belanda tersebut juga berniat memasarkan produknya di Indonesia. Sebagai ‘batik tiruan’ yang diproduksi secara massal, Ankara berupaya menggeser batik dengan cara memasarkan ‘kain semacam batik’. Harganya jauh lebih murah dibanding batik, di mana pada masa itu produksi batik hanya dikerjakan secara manual. Rupanya niat tersebut tidak berjalan mulus, karena motif Ankara dirasa tidak begitu cocok dengan selera orang Indonesia. Produsen yang sudah terlanjur memproduksi banyak kain, bagaimanapun juga, memerlukan ‘pasar’ baru. Akhir cerita, sampailah Ankara tersebar di beberapa wilayah di Afrika termasuk Nigeria.
Melalui sejarah Ankara ini, saya ingin mengatakan bahwa hubungan antar-negara dalam rezim pasar global seperti saat ini nampak menjadi sesuatu yang niscaya. Di sini, Indonesia dan Nigeria sama-sama menempati posisi sebagai pasar, tempat dibuangnya barang-barang produksi Eropa atau katakanlah ‘negara dunia pertama’. Kecurigaan pun tentu bisa dilanjutkan, “jangan-jangan tidak hanya barang yang disebarluaskan dengan logika demikian, tetapi ide, nilai ataupun hal-hal abstrak lain yang tidak kasat mata juga turut disebarkan”. Saya pikir, kecurigaan ini layak untuk diteruskan. Cerita tentang Ankara bisa kita gunakan sebagai cara atau alat bantu dalam menggali hubungan antara Indonesia dan Nigeria ketika berhadapan dengan kuasa global, yang tentu tidak hanya berada pada ranah produksi kain, tetapi juga minyak sawit atau bahkan ide dan logika.
Secara khusus, cerita Ankara ini bahkan menguatkan asumsi bahwa hubungan antara Indonesia dan Nigeria bukanlah sesuatu yang mengada-ada atau dibuat-buat. Selain hubungan formal yang bisa dilacak dalam catatan sejarah KAA, Indonesia dan Nigeria memiliki hubungan yang tidak langsung. Semangat perjumpaan yang digaungkan dalam Biennale seri Equator adalah perjumpaan yang menghasilkan ilmu pengetahuan. Menghasilkan pengetahuan, bagi saya, bukanlah persoalan main-main, yang sejauh proses ini belum mampu saya bayangkan langkahnya. Akan tetapi setidaknya, dari cerita tentang Ankara, kita mendapat bayangan bagaimana perjumpaan Indonesia dan Nigeria menjadi perjumpaan yang produkif untuk menggali pelajaran bersama dengan dosis yang disesuaikan. Dengan kata lain, meski bersama dan memiliki beberapa kesamaan konteks, persoalan di masing-masing negara tentu memiliki kebutuhan yang berbeda.
Lisistrata Lusandiana (Peneliti Yayasan Biennale Jogja)