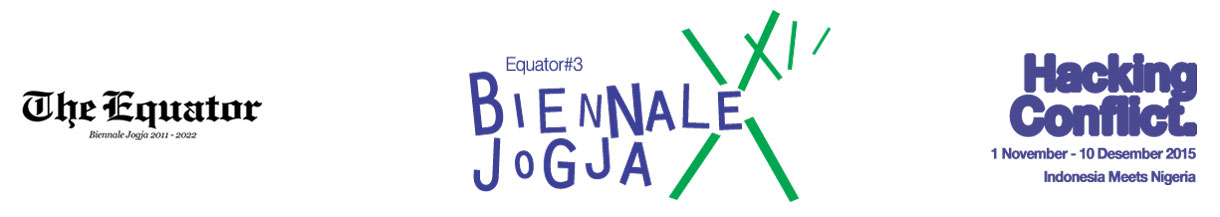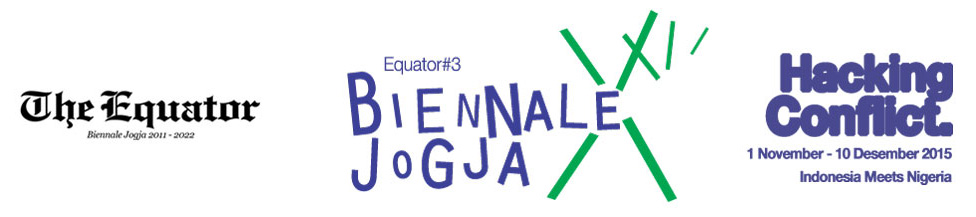Nigeria, negerinya Soyinka dan Achebe. Negeri yang belakangan ini, bagi beberapa media internasional, identik dengan aneka gangguan keamanan dan penyebaran virus ebola. Di Indonesia, orang kerap mengenang Nigeria sebagai negara asal kartel-kartel narkoba kelas kakap. Begitulah cerita tentang Nigeria disuguhkan. Orang sering lupa bahwa, seperti Indonesia, Nigeria juga negara berkembang yang tengah berbenah untuk bisa menjadi setara dengan negara-negara maju, bukan semak belukar seperti yang sering dibayangkan orang.
Kesan sinis dan ungkapan nyinyir sangat akrab diterima tim Yayasan Biennale Jogja beberapa saat sebelum berkunjung ke Nigeria. Tidak jarang kabar-kabar ngeri dibagikan untuk sekadar mengingatkan agar menangguhkan kunjungan. Berita dari media nasional dan internasional mengangkat tajuk yang sama setiap kali berbicara tentang Nigeria; Boko Haram dan ebola. Berita direproduksi, dikonsumsi khalayak, dan “berkembang” saat diomongkan sebagai gosip. Namun apa mau dikata, biduk sudah terlanjur mengarah ke laut lepas. Membatalkan kunjungan sama artinya dengan menunda pernikahan sesaat sebelum ijab qabul di depan calon mertua! Maka berangkatlah kami, tim Biennale Jogja, dengan beragam isu di kepala.
Saat pertama kali mendarat di bandara Abuja, Ibu Kota Nigeria, isu-isu miring yang banyak beredar–seperti kekhawatiran tentang virus ebola misalnya–tidak sepenuhnya benar. Virus ebola menjadi isu yang sangat seksi, terutama oleh kalangan media yang menjadikan Nigeria sebagai salah satu kawasan terdampak. Perlu diingat, Nigeria merupakan negara yang paling maju di daerah Afrika Barat sehingga antisipasi dan penanganan masalahnya jauh lebih baik dibanding negara lain di kawasan itu. Begitu juga dengan kekhawatiran pada kelompok Boko Haram yang bersembunyi di daerah Kano, wilayah Utara Nigeria. Berita tentang Boko Haram terlalu dibesar-besarkan untuk menciptakan ketakutan dan kesan buruk tentang Nigeria.
Dalam imaji kita, sebagaimana sering disuguhkan film-film Holywood, setiap pergolakan di kawasan Afrika diandaikan kacau balau; AK 47, baku tembak, pembunuhan, perkosaan, dan penculikan ada dimana-mana. Karena sudah terlanjur tertanam dalam benak, Afrika selalu dibayangkan kacau, tanpa kemajuan, dan dipenuhi orang bebal. Orang yang berkulit hitam dan berambut keriting kerap diasosiasikan dengan penjahat, tidak maju, berasal dari daerah konflik atau daerah endemik penyakit-penyakit ganas. Imaji seperti itulah yang layak dibuang ke tong sampah dan mulai mempelajari secara jernih bagaimana calon mitra kerja sama kita di Biennale Jogja nanti menjalani hidupnya serta melakukan “praktik artistiknya.”
Abuja dan Lagos
Abuja adalah kota yang relatif masih baru. Pembangunan infrastruktur kota masih banyak berlangsung. Kota yang gaya arsitekturnya sangat modern dan megah ini menjadi persinggahan awal kami. Beberapa tahun lalu Ibu Kota Nigeria dipindahkan dari Lagos ke Abuja. Itu karena Lagos dianggap sudah terlalu sumpek dan tidak lagi ideal sebagai tempat mengurusi pemerintahan. Begitu juga kantor perwakilan berbagai negara yang turut dipindahkan ke Abuja, termasuk KBRI. Abuja menjadi pusat pemerintahan, sedang Lagos dipertahankan sebagai pusat bisnis.
Di Abuja, kami menemui tiga bagian otoritas pemerintahan Nigeria yang mengurusi masalah seni dan budaya. Pertama-tama kami mengunjungi National Council for Arts and Culture, lalu dilanjutkan ke Federal Capital Territory for Tourism Department, dan terakhir ke National Gallery of Arts. Kunjungan ini tentu lebih formal dan cenderung membicarakan hal-hal yang sifatnya prosedural. Seperti umumnya terjadi di Indonesia, otoritas pemerintahan Nigeria yang kami temui juga mengerangkeng urusan seni dan budaya sebatas pada masalah turisme atau sesuatu yang bisa mendatangkan pemasukan bagi negara. Bentuk kerja sama yang dibayangkan selalu diandaikan bakal mendatangkan keuntungan finansial di kedua belah pihak atau sekadar harapan agar bisa jalan-jalan dengan menggunakan uang negara. Bukan pertukaran pengetahuan atau “investasi sumber daya manusia.”
Ketiga lembaga itu juga tidak melihat potensi lain yang muncul dari inisiatif perseorangan atau komunitas seni-budaya di negaranya–hal yang sangat sering kita temui di Indonesia. Dengan begitu, produk seni yang ditunjukkan melulu berbentuk kerajinan dan kesenian sejenis yang memungkinkan untuk “diperjual-belikan” atau menegaskan identitas/tradisi masyarakat lokal. Nampak eksotis memang, toh eksotisme menjadi jualan paling laris dimana-mana. Itulah mengapa, pemerintah di negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia atau Nigeria mendudukkan seni, budaya, dan pariwisata di atas panggung yang sama; supaya bisa dikunjungi, ditonton, dan ujung-ujungnya, duit.
Seperti Abuja, Lagos juga disesaki bangunan-bangunan megah. Bedanya Lagos lebih riuh. Dari pabrik-pabrik hingga pusat-pusat perbelanjaan terbesar di Nigeria ada di Lagos. Di kota inilah orang-orang dari berbagai suku di Nigeria berkumpul dan bekerja. Tingkat kemacetannya boleh dikata lebih dari Jakarta. Sebagai pusat perekonomian dan bekas jantung pemerintahan, Lagos jauh lebih dinamis dibanding Abuja. Di Lagos pula kami menemui berbagai komunitas maupun perseorangan yang bekerja di luar “pantauan” negara. Ada tiga komunitas dengan corak berbeda yang kami kunjungi di Lagos, yakni; Centre for Contemporary Art (CCA) Lagos, kantor redaksi majalah Position, dan African Art Foundation. Sedang pihak perorangan yang kami temui adalah Ndidi Dike, seorang seniman senior di Nigeria dan Victor Ehikhamenor, salah seorang seniman muda terpenting di Lagos.
Selain mengunjungi beragam komunitas dan seniman, kami berkunjung dan berdiskusi dengan Marc Andrew, direktur Goethe Institute untuk wilayah Nigeria. Darinya, kami memperoleh beragam pembacaan tentang seni kontemporer di Lagos dari sudut pandang orang luar yang telah lama bekerja dan membangun jaringan di Nigeria. Di hari yang sama kami menyempatkan diri untuk mengunjungi National Museum of Lagos dan Nigeria National Theatre, bangunan super megah yang terakhir kali digunakan untuk menggelar pertunjukan lebih dari sepuluh tahun lalu.
Ketimpangan Sosial-Ekonomi
Tahun 2012 lalu, pemerintah kota Lagos menerbitkan sebuah buku yang judulnya cukup menggelitik; “RRS: Landmarks of Crime-Fighting in a Megacity.” Buku itu sedikit memberi gambaran tentang Lagos di tahun-tahun yang lalu dan bagaimana masalah keamanan di kota–menurut klaim pemerintah kota Lagos dalam buku itu–dapat diatasi. Pemerintah kota Lagos khususnya, membuat kebijakan penting untuk mengatasi masalah kriminalitas. Kebijakan seperti itu nampaknya menjadi cetak biru penanganan keamanan di Nigeria. Tak heran bila kemudian masalah keamanan menjadi prioritas bagi pemerintah setempat untuk diselesaikan, baik di Lagos maupun Abuja.
Pengamanan di Abuja nampak lebih ketat, sebab kendali keamanan diambil alih tentara. Belum lama ini, Abuja diguncang teror bom kelompok Boko Haram sehingga ada pemberlakuan jam malam dan pemeriksaan setiap kendaraan yang hendak memasuki wilayah kota oleh tentara. Sedang di Lagos, urusan kota diserahkan kepada polisi dan kelompok polisi bantu yang di sebut LASTMA (Lagos State Traffic Management Agency). LASTMA ditugasi untuk mengurusi masalah lalu lintas. Dari seorang sumber kami mengetahui bahwa orang-orang yang direkrut sebagai Lastma adalah bekas pelaku kejahatan di Lagos. Merekrut mereka merupakan salah satu strategi untuk menekan tingkat kejahatan di kota Lagos. Namun, keberadaan LASTMA bukan tanpa masalah, sebab mereka jauh lebih galak dibanding polisi yang sebenarnya.
Masalah keamanan tentu menyita perhatian kami. Mengapa kota seperti Abuja dan Lagos rentan tindak kriminal sehingga harus mengerahkan banyak tenaga pengamanan? Siapa yang hendak dilindungi? Kami tergelitik untuk merunut pusaran masalahnya secara sederhana. Kejahatan di sebuah wilayah tentu bukan sesuatu yang alamiah, termasuk Abuja dan Lagos. Sejauh yang kami amati, kesenjangan ekonomi mungkin menjadi penyebab utama tingginya angka kejahatan. Belum lagi biaya hidup di kedua kota itu yang terbilang sangat mahal. Masalah elektrifikasi yang salah urus menyebabkan biaya produksi setiap barang menjadi sangat tinggi dan berimbas pada harga barang di pasaran. Di Nigeria, pemadaman listrik terjadi tidak kurang dari tiga kali sehari. Itulah mengapa setiap rumah, kantor, pabrik, atau tempat apapun yang membutuhkan listrik, ada generator yang berbahan bakar bensin. Sebagai negara yang sangat kaya akan minyak (dengan rerata produksi dua koma tujuh juta barel perhari atau tiga kali lipat dari produksi Indonesia) dan sumber daya lain, tentu sangat ganjil bila listrik menjadi barang langka.
Kompleksnya masalah di Nigeria memungkinkan kesenjangan ekonomi yang terlalu lebar. Orang-orang kaya Nigeria hidup di dalam kompleks-kompleks mewah yang sangat tertutup. Setiap kompleks dikelilingi tembok tinggi yang dilengkapi dengan kawat berduri di bagian atasnya. Di dalam kompleks, setiap rumah juga dikelilingi tembok tinggi. Begitu juga di hampir semua ruang publik yang sempat kami lihat, dikelilingi tembok dan penjagaan ketat. Pemandangan itu sedikit kontras dengan pemukiman warga berekonomi lemah. Mereka tinggal secara berdempetan, tanpa tembok tinggi maupun penjagaan. Setiap orang yang kami temui tidak merekomendasikan untuk masuk areal seperti itu dengan alasan keamanan. Boleh jadi aparat keamanan sekadar melindungi aset-aset orang kaya (dan atau wisatawan) dari gangguan orang yang merasa haknya tidak dipenuhi negara. Mereka lantas kita sebut sebagai “penjahat.”
Dengan gambaran situasi sosial macam itu tentu sangat sah bila kita membayangkan ada perlawanan dari kelas bawah pada kelas atas. Begitu juga perlawanan kelas menengah yang mungkin akan mengambil posisi untuk membela kalangan bawah. Namun kenyataannya, sejauh yang kami amati, tanda-tanda atau jejak perlawanan semacam parlemen jalanan tidak nampak. Lebih parahnya, dari orang-orang yang kami temui, tidak ada kelas menengah. Hanya ada kelas atas yang terlalu kaya dan kelas bawah yang terlalu miskin.
Lantas, mengapa jejak perlawanan terhadap pemerintah (dalam amatan kami) tidak ada? Ada dua asumsi yang mungkin kelak bisa dikembangkan atau diuji secara lebih objektif. Pertama, takut pada represi aparat keamanan khususnya tentara. Nigeria lama dikuasai rezim militer. Mereka baru lepas dari dari rezim militer pada 8 Juni 1998 setelah Sani Abacha meninggal karena serangan jantung. Pihak junta militer Nigeria memang menunjuk Jendral Abubakar sebagai pengganti Abacha. Tetapi, di tahun 2000, pemilu tetap dilakukan dan mendudukkan Olusegun Obasanjo di tampuk kepemimpinan. Perubahan iklim politik rupanya tidak sepenuhnya mengubah cara pandang atau “nyali” masyarakat Nigeria saat berhadapan dengan militer.
Bila dicermati, pola perubahan politik di Nigeria hampir mirip dengan yang terjadi di Indonesia. Bedanya, reformasi politik 1998 diraih setelah ada perlawanan langsung dari berbagai kelompok (mahasiswa, masyarakat, dan kalangan lain), sedangkan di Nigeria lebih karena pemimpin otoriternya meninggal dunia, bukan karena berhadap-hadapan langsung dengan militer. Peluang itulah dimanfaatkan masyarakat Nigeria untuk membalik keadaan.
Asumsi kedua, masyarakat dimabukkan di tempat-tempat ibadah dan ilusi tentang kesejahteraan. Asumsi ini sangat spekulatif karena berawal dari kesimpulan sebuah film dokumenter yang berjudul “Nollywood Babylon.” Film ini mengangkat fenomena Nollywood, sebutan untuk industri film populer di Nigeria. Dalam film itu sempat diceritakan tentang peran pemuka agama di rumah ibadah yang rajin memberi khutbah tentang kerja keras sebagai pangkal kesuksesan. Orang yang telah bekerja keras tetapi belum sukses dianggap terkena guna-guna sehingga perlu disembuhkan. Ketidaksuksesan dalam kasus ini ada lebih karena alasan mistis, bukan karena struktur sosial yang timpang atau negara yang salah urus. Karena itu, orang dianjurkan untuk menjalani hidupnya dengan baik; bekerja sebaik-baiknya tanpa banyak cingcong.
Begitu juga dengan ilusi tentang kesejahteraan yang disuguhkan dalam film-film Nollywood. Kesejahteraan, dalam hal ini kejayaan dan kekayaan, bisa dicapai manakala orang bekerja keras meski mulai dari bawah. Normatif dan nampak wajar. Namun, salah satunya lewat Nollywood-lah ilusi itu ditanamkan sehingga orang kerap menganggap dunia masih baik-baik saja dan lumrah untuk dijalani.
Awalnya, saya menganggap kesimpulan dalam film itu sebagai “gombal” semata atau terlalu dilebih-lebihkan. Namun, setelah melihat dan berdiskusi dengan seorang warga Lagos, saya menganggap kesimpulan itu sangat memungkinkan untuk didalami dan dibuktikan kebenarannya secara lebih objektif. Hal ini tentu menarik untuk dicermati lebih lanjut. Hanya saja, waktu yang terbatas tidak memungkinkan kami untuk mengeksplorasi lebih dalam lagi. Sehingga apa yang kami amati sangat terbatas dan kurang mendalam.
Praktik Seni Kontemporer di Lagos
Serabut masalah sosial-ekonomi di Lagos rupanya tidak menutup ruang kreatif bagi berbagai komunitas maupun individu. Lagos adalah ladang subur bagi pengembangan praktik seni kontemporer di Nigeria. Kesan itu kami dapat saat berkunjung ke salah satu ruang seni kontemporer di Lagos yang dinamai Centre of Contemporary Art (CCA). Di CCA, kami berdiskusi panjang dengan Jude Anogwih, seorang seniman yang mengeksplorasi berbagai medium dalam praktik artistiknya, mulai dari fotografi, video, hingga drawing. Selain sebagai seniman, Jude juga merupakan seorang kurator di CCA.
CCA bukan ruang yang asing dalam peta seni kontemporer internasional. Seniman-seniman yang belajar dan besar di CCA sangat sering diundang dalam pameran seni rupa lima tahunan, dOCUMENTA di Kassel, Jerman ataupun acara-acara besar lain. Bila partisipasi dalam pameran-pameran bergengsi dijadikan sebagai satu-satunya tolok ukur perkembangan seni rupa kontemporer di sebuah negara maka Nigeria telah jauh meninggalkan Indonesia. Hingga perhelatan dOCUMENTA yang terakhir kali diadakan tahun 2012 lalu, belum ada satu pun seniman Indonesia yang berpartisipasi di dalamnya. Tentu penialaian yang demikian sangat parsial sebab masih banyak kategori lain yang perlu dilihat.
Terlepas dari itu semua, ada beberapa hal yang menurut hemat saya sangat menarik di CCA dan menjadi cermin praktik seni rupa kontemporer di Nigeria. Selain ruang eksplorasi isu yang sangat kaya, mereka juga kuat dalam membedah maupun menarasikan sebuah karya seni. Boleh dikata, secara konseptual CCA sangat kuat. Itu nampak saat berdiskusi secara panjang lebar dengan Jude dan seniman-seniman yang sempat terlibat dalam sebuah project di CCA seperti Ndidi Dike dan Victor Ehikhamenor. Ndidi mengeksplorasi dan menggunakan beragam media dalam praktik artistiknya. Dalam sebuah project di CCA, Ndidi mengangkat tajuk jejek perbudakan di negerinya. Dia menelusuri secara historis dan genealogis praktik perbudakan di masa lalu; bagaimana orang Nigeria ditangkap, dikumpulkan, dipasung, dikemas, hingga dikirim ke berbagai kawasan seperti Eropa dan Amerika. Untuk mendukung project-nya, Ndidi melakukan penelitian panjang tentang praktik perbudakan di Afrika selama masa kolonial berlangsung.
Kedalaman dalam mengeksplorasi isu juga ditunjukkan Victor Ehikhamenor. Victor adalah seniman serba bisa di Lagos. Selain menekuni drawing, painting, dan fotografi, Victor juga menjadi kolumnis di Washington Post, kontributor beberapa media terkemuka di USA dan Eropa baik untuk tulisan fiksi maupun non-fiksi. Dia sempat tinggal di USA sebelum akhirnya kembali dan menetap di Nigeria. Dalam praktik artistiknya, Victor mengeksplorasi tema-tema sosial, ekonomi, dan politik. Seniman ini sangat penting dalam peta seni kontemporer di Lagos. Okey Ndibe, seorang kolumnis The Sun, menggambarkan Victor sebagai seorang patriot yang rela meninggalkan segala “kemapanannya” di USA dan kembali ke Lagos atas permintaan Dele Olojede–seorang jurnalis terbesar dalam sejarah Nigeria dan sempat memenangkan hadiah Pulitzer–untuk mengurusi surat kabar Next.
Dalam hal eksplorasi isu, Jude juga punya kecenderungan Ndidi dan Victor. Hanya saja, karya Jude jauh lebih rumit dan sangat konseptual. Untuk memahami karyanya, orang perlu mendengar paparan Jude secara langsung. Dia tidak peduli pada orang yang akan melihat karyanya. Begitupun dengan gagasan yang hendak ia sampaikan. Mau sepakat atau tidak, Jude sama sekali tidak peduli. Menurutnya, apa yang dia sampaikan adalah cara bacanya terhadap sebuah persoalan. Lantaran terlalu konseptual, muncul kesan–setidaknya bagi saya secara pribadi–jika karyanya terlalu ditekan gagasan. Gampangannya, pemikirannya serumit karyanya.
Tulisan sederhana ini tentu belum mencerminkan keseluruhan pengalaman kami selama mengunjungi Nigeria. Begitupun dengan apa yang kami temui dan lihat di sana, belum cukup untuk memberi kesimpulan umum perihal praktik seni kontemporernya. Ini hanya menjadi pemantik awal bagi kita semua untuk sedikit melihat kehidupan masyarakat dan praktik seni kontemporer Nigeria. Setidaknya ada satu hal yang perlu direnungkan; Nigeria bukan semak belukar! Mereka bergerak secara progresif dan sangat penting untuk dijadikan mitra kerja sama.
–Arham Rahman
*gambar: Pemandangan kota Lagos di area Yaba. Foto diambil dari kantor CCA Lagos, Nigeria.