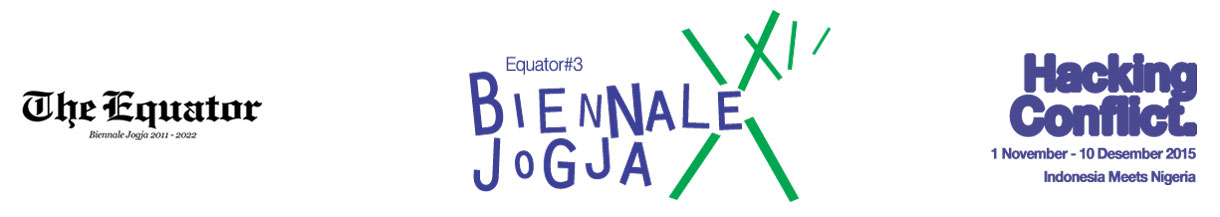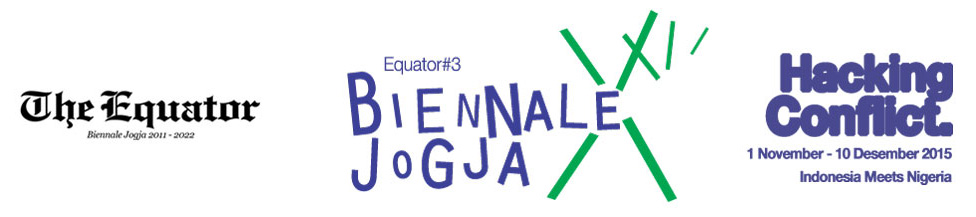Langit yang Berwarna dan Teman Kecil yang Tersingkir
1982. Ketika itu saya masih kelas 2 SD, tinggal di kota kecil yang nyaman. Keluarga saya berasal dari kalangan pedagang sehingga memilih lokasi tempat tinggal strategis dekat pasar, kawasan pusat pertokoan dan ruang-ruang transaksi yang umumnya ditempati oleh komunitas Tionghoa dan komunitas kecil Arab. Walau sudah tinggal lebih dari 3 generasi tetapi ada hal-hal yang mewarnai interaksi kami sebagai kawan sepermainan yang harmonis dan menyenangkan. Seakan langit penuh dengan warna menghiasi masa kecil kami setiap hari. Suatu malam rumah kami terus menerus bergetar, suara langit-langit berderit semakin keras dan semua lampu gantung bergoyang teratur namun menakutkan karena bumi ternyata berguncang Saya tidak bisa tidur semalaman. Ayah beserta orang rumah tampak berbicara serius. Saya kurang paham apa yang sedang terjadi, tapi sepertinya bumi tidak lagi nyaman untuk dipijaki. Pagi hari ketika membuka jendela, saya baru tersadar langit tidak lagi berwarna biru tetapi gelap kelabu kemerahan seperti sedang terbakar. Orang berlarian dengan lampu senter di tangan karena siang bukannya semakin benderang tapi semakin menggelap. Jalanan menebal tertutup hujan abu, setiap langkah meninggalkan jejak membuat saya tergetar ketika menyadari seluruh permukaan kota berubah warna menjadi abu-abu tertutup butiran debu. Pengeras suara masjid tidak lagi mengumandangkan suara adzan tapi berisi peringatan-peringatan. Volume radio di meja kerja ayah saya diputar 2 tingkat lebih keras dari biasanya agar kami sekeluarga mendapatkan informasi akurat dan terkini, apa yang sedang terjadi, untuk segera menentukan apa yang harus kami lakukan. Saya semakin kalut, inikah kiamat akhir dari seluruh kehidupan di bumi yang sering disebutkan oleh guru ngaji? Bergegas saya naik ke puncak genteng ingin melihat langit dan bumi yang tampak semrawut hari itu. Di kejauhan terlihat awan bergulung-gulung seperti cendawan raksasa, terdengar dentuman suara menggelegar yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Kilatan petir dan pijar api membuat saya tergetar antara kagum dan ngeri. Galunggung meletus! Di kemudian hari saya baru tahu bahwa letusan Galunggung yang ketiga kalinya ini- terhitung sejak tahun 1822- termasuk salah satu yang paling besar dalam sejarah manusia modern.
Selama 9 bulan saya harus berhadapan dengan segala persoalan akibat bencana ini. Sekolah ditutup, setiap keluar rumah harus memakai masker, transaksi ekonomi terhenti, kegiatan pasar terganggu, raut panik tampak dimana-mana khawatir kondisi sanak famili yang tinggal jauh di desa dan mobilisasi ribuan pengungsi menjadi berita sehari-hari. Setelah letusan mereda, curahan lahar dan tumpukan pasir telah mengubah peta wilayah, akibat sungai yang terputus dan lapisan lahar serta pasir yang mengubur desa-desa di sekitarnya. Hampir setiap ada kesempatan saya selalu kembali naik ke atas genteng, namun kali ini sepertinya saya sedang kurang beruntung, permukaan lantai tempat saya berpijak yang hanya berukuran kurang dari 15 cm tertutup pasir licin. Saya tergelincir dan jatuh dari ketinggian 4 meter, pingsan dan kehilangan kemampuan berbicara untuk beberapa saat. Galunggung bukan hanya membuat kota saya mati suri, tapi saya benar-benar KO oleh ‘pukulannya’. Alam dengan mudah dapat memukul kehidupan manusia dengan sangat keras. Walau bagi bumi, letusan gunung berapi hanyalah sebuah bisikan kecil yang keluar dari ‘mulutnya’.
Setelah beranjak dewasa, sekitar tahun 1998-1999-dalam situasi kehancuran ekonomi Indonesia akibat krisis moneter- rumah keluarga kami telah pindah lokasi tepat di depan sebuah gereja, tempat teman-teman kecil saya yang sudah beranjak dewasa beribadah setiap Minggu dengan penuh rasa khawatir terutama ketika terjadi konflik antar agama dan rasial yang berujung pada kekerasan hingga pengeboman gereja-gereja di beberapa lokasi di Indonesia. Memori keceriaan masa kecil yang masih saya ingat dari wajah mereka berganti dengan pandangan kosong dan raut ketidakpastian penuh ketegangan. Bagai peta yang berubah tersingkir kekuatan letusan, apabila gejolak politik terus bergerak tak terkendali, teman-teman sejak masih kecil saya ini pun akan mudah disingkirkan dari negara ini.
Lempeng Bumi yang Bergerak dan Ideologi yang Bertumbukan
Seiring beranjak dewasa, sepertinya pemandangan langit yang memerah baik karena bencana alam atau gerakan sosial terus mewarnai kehidupan saya di negara ini. Seperti pada aksi pembakaran dan penjarahan selama kerusuhan Mei – yang membuat beberapa teman Tionghoa masa kecil saya pindah ke luar negeri- telah memerahkan langit Jakarta dan melumpuhkan ibukota. Belum lagi setelah mengetahui letak geografis bumi Indonesia tempat saya berpijak. Ternyata ratusan kilometer dibawahnya kerap terjadi tumbukan lempeng-lempeng raksasa tektonik purba yang terus menerus bergerak. Semenjak waktu mulai berdetak, tumbukan ini telah membangun monster yang berupa barisan gunung berapi, bagaikan permainan Roulette siap meledak kapan saja. Dalam posisi-posisi tertentu lempeng di tengah samudra bisa bergesar secara ekstrim memicu gempa bumi berskala tinggi di dasar laut dan memicu gelombang mega tsunami mematikan. Seperti gempa Aceh dengan kekuatan 9,2 SR merupakan terbesar ketiga yang pernah tercatat di seismograf dan memiliki durasi terlama sepanjang sejarah, yaitu sekitar 8,3 sampai 10 menit. Gempa tersebut mengakibatkan seluruh planet bumi bergeser 1 sentimeter dan menciptakan beberapa gempa lainnya sampai ke wilayah Alaska. Episentrumnya berada di antara Simeulue dan daratan Sumatera, telah memicu terjadinya gelombang tsunami yang puncak tertingginya mencapai 30 meter ini menewaskan lebih dari 230.000 orang di 14 negara dan menenggelamkan banyak pemukiman tepi pantai. Ini merupakan salah satu bencana alam paling mematikan sepanjang sejarah. Indonesia adalah negara yang terkena dampak paling besar, diikuti Sri Lanka, India dan Thailand. Fakta yang membuat saya merasa bahwa sebenarnya peradaban itu ternyata sangatlah rentan.
Siang tahun 2000, lalu lintas di Jakarta Pusat tampak lebih lengang dari biasanya. Angin yang berhembus pelan seakan tak kuasa menyapu awan polusi yang menebal menaungi langit ibukota. Sepeda motor yang saya kendarai memasuki kawasan Jalan Kuningan/HR. Rasuna Said lalu menanjak dengan kecepatan sedang sehingga sudut pandang dari ketinggian jalan layang membuat mata saya mampu menyapu garis horizon kota Jakarta yang tampak artistik dengan kontrasnya latar belakang pencakar langit dan rumah-rumah beratap genteng. Pemandangan ini membuat saya terkenang kembali kebiasaan sewaktu kecil, menaiki atap rumah untuk melihat seluruh sudut kota. Namun kali ini mata saya berhenti berkedip, kecepatan sepeda motor melambat namun denyut jantung saya semakin cepat. Kembali terlihat semburat kemerahan di langit diselingi asap halus. Semakin mendekat ke arah sumber cahaya semakin mengerikan, lalu lintas terhenti, wajah pengendara pucat pasi, pohon-pohon hijau sepanjang jalan menjadi tinggal ranting karena seluruh daunnya rontok ke jalan. Di tengah kekalutan saya melihat sosok-sosok manusia digotong dengan badan bersimbah darah dan baju mereka terkoyak kekuatan dahsyat. Tercium bau terbakar seperti mesiu. Untuk pertama kalinya saya melihat bagaimana dampak sebuah bom yang meledak. Orang lari berhamburan karena takut bom susulan, saya memacu sepeda motor dengan pandangan kosong. Sampai rumah baru saya ketahui kalau sebuah bom mobil telah membuat dua orang tewas dan 21 orang terluka. Peledakan di kedutaan Filipina ini disinyalir terkait aksi balas dendam, karena pemerintah Filipina melakukan penyerangan terhadap kelompok garis keras Islam di Moro. Aksi mereka dicurigai sebagai pengeboman pertama dari awal gelombang teror bom yang meledak sebanyak 28 pengeboman berlangsung dari tahun 2000-2009 di Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut sebanyak 322 orang tewas. Bagi pelakunya, barangkali tindakan ini adalah sebuah jalan suci seperti ‘vibrasi’ dan intervensi terhadap ideologi yang sudah dianggap mati.
Perpisahan dengan Negara dan Perjumpaan dengan Seni
Pada saat tulisan ini dibuat saya sedang mengalami kegelisahan hebat terkait status saya sebagai bangsa dan warga negara Republik Indonesia. Saya tidak ragu tentang gagasan kebangsaan dan demokrasi, namun ide untuk mendeklarasikan sebuah negara tanpa komitmen jelas dari aparaturnya dan konsekuensi setengah-setengah dari bangsanya membuat ide luhur nasionalisme berubah menjadi perayaan rutin tahunan membosankan dan ideologi hafalan yang usang. Secara perlahan serpihan-serpihan rekonstruksi sejarah yang dijejalkan selama saya lahir dan tumbuh di era Orde Baru menguap tersapu perubahan. Namun setelah era reformasi ternyata tidak banyak perubahan yang berarti, semakin hari baik negara ataupun dunia seni cenderung menjauh dari apa yang saya bayangkan sebelumnya. Saya merasa waktu perpisahan antara saya dan negara semakin mendekat, kegelisahan ini semakin memuncak dalam dua tahun terakhir tatkala saya mengerjakan karya baru terkait peristiwa politik yang terjadi di tahun 1965-1966, pada saat terjadi benturan ideologi paling kejam sepanjang sejarah Indonesia yang dipengaruhi tarik menarik dua kekuatan besar di dunia saat itu, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Situasi yang mendorong bangsa Indonesia bergeser kearah lain. Tragisnya rakyat kembali menjadi korban, setengah juta jiwa melayang. Ideologi kembali menjadi pembenaran atas pemusnahan suatu golongan. Menyedihkan selama 32 tahun berikutnya kita diajarkan untuk menjadi pembenci sejati. Lalu sejarah baru dibangun namun si pelaku tidak menyadari bahwa sejarah yang tidak mungkin direproduksi tersebut kembali ingin dipertontonkan kepada publik. Monumen-monumen berselera buruk dengan bahan beton dan perunggu yang menjulang tinggi ke langit didirikan dengan megah di ruang publik. Namun apa yang terjadi setelah sang penguasa tersungkur? Monumen menjadi kehilangan makna, ada secara fisik namun sudah tidak dianggap berfungsi, bahkan secara estetis sulit untuk dinikmati karena rakyat melihat sejarah yang terdistorsi. Monumen Mandala (mengenang perebutan Irian Barat) di Makasar semakin sepi karena warga lebih senang mengunjungi pantai Losari. Ternyata sejarah pun sangatlah labil, terus bergeser dan berubah seiring perkembangan sejarah itu sendiri.
Perjumpaan saya dengan kesenian menjadi penting. Setidaknya, saya merasa cara pandang sebagai seniman terhadap persoalan mampu membangkitkan imajinasi radikal tanpa batas sehingga kerap merefleksikan gambaran dunia dengan apa adanya. Saat ini saya mengamati dua arus besar dunia seni Indonesia. Seni pasar dan intelektual. Seni pasar sama sekali tidak menarik minat saya karena sejak kecil saya tumbuh dekat pasar, di mana omong kosong, jual beli dan negosiasi menjadi pemandangan sehari-hari lengkap dengan drama kaya mendadak dan simbol-simbol kesuksesan yang dipertontonkan dalam keseharian. Situasi seni yang saya jalani saat ini telah menciptakan perjumpaan-perjumpaan yang lebih eksplosif dari hanya sekedar ruang ‘steril’ galeri. Karena ada kecenderungan infrastruktur seni di Indonesia saat ini tumbuh seperti di Barat, memuseumkan, membendakan. Padahal ketika memasuki museum seni kontemporer, saya merasa sering dikerdilkan ketika berada di dalamnya. Pembacaan geopolitik yang selama ini saya pelajari ternyata semakin melebar sepanjang garis peta politik di permukaan bumi. Tarik menarik dan benturan ideologi terus terjadi sementara ancaman gunung berapi dan gempa bumi terjadi setiap hari (saat ini setidaknya terdapat 76 gunung berapi yang aktif di Indonesia), ditambah dengan potensi ‘letupan’ gerakan yang terus bergerilya di Timur bumi pertiwi. Rakyat Papua memanggul busur, panah dan senjata memperjuangkan kemerdekaan atas pendudukan Indonesia. Konflik dan ketegangan mewarnai kekayaan alam mereka yang terus dieksploitasi dengan brutal. Negara kembali melakukan kesalahan fatal dengan menerjunkan militer ke Tanah Papua, ceritanya tentu akan berbeda apabila lebih banyak mengirimkan seniman untuk bekerja disana.
Tempat Paling Mematikan di Bumi dan Langit yang Berwarna Pelangi
Dengan getir saya harus mengakui bahwa ternyata kawasan yang saya tinggali merupakan salah satu tempat paling mematikan di bumi. Karena dampak dari tumbukan ideologi dan bergesernya lempeng tektonik telah mengakibatkan begitu banyak tragedi kemanusiaan dan luka sejarah kelam. Ring of Fire, garis kerentanan yang membentang di sekitar lingkar Pasifik, selain menjanjikan sumber daya alam dan potensi ekonomi yang strategis, kawasan ini penuh gejolak baik secara geografis maupun politis yang terbentang dari masa perang dunia ke 2, perang dingin hingga era globalisasi saat ini. Di garis Asia Timur saja terdapat berbagai potensi konflik yang setiap saat mudah tersulut dan meledak. Ketegangan perbatasan wilayah di Laut Cina Selatan melibatkan perdebatan lebih dari 8 negara, konflik bangsa bersaudara antara Korea Utara dan Korea Selatan, segregasi yang kian melebar antara pekerja migran dengan warga setempat di ruang-ruang publik Taiwan, raksasa Cina yang telah membuat semua mata dunia melirik bukan hanya pada gemerlap ekonominya namun kebijakan politiknya yang agresif dan provokatif. Sementara diam-diam reaktor nuklir Fukushima bocor mencemari Samudera Pasifik. Semuanya terasa rumit seperti dulu waktu saya melihat seluruh kota yang tertutup abu. Untuk memulai langkah sepertinya saya harus kembali menggunakan faktor penting dalam peradaban yang sering dilupakan, yakni kekuatan kebudayaan. Setiap teriakan menginginkan perubahan semakin keras sehingga menjadi tidak lagi terdengar dengan jelas. Saya ingat cerita seorang teman yang percaya kekuatan sebuah ‘bisikan’, masuk ke dalam telinga secara perlahan lalu diterima oleh hati tanpa paksaan untuk membuat sebuah perubahan.
Bisa jadi ini semua hanyalah utopia saya saja yang berambisi mengintervensi garis ‘Cincin Api’. Ditengah kegalauan membuat karya baru untuk Jogja Biennale kali ini justru saya merasakan bahwa ‘operating system’ geopolitik Equator tidak ‘user friendly’ karena membuat saya sulit untuk memahami relasi Indonesia-Nigeria yang saya percaya bukan hanya sekedar saling menawarkan Indomie. Sambil terus bekerja saya bermimpi suatu hari tidak lagi melihat semburat merah yang penuh misteri diatas langit tetapi warna pelangi yang indah dan mendamaikan hati.
Penulis: Irwan Ahmett (Seniman BJXIII Hacking Conflict)