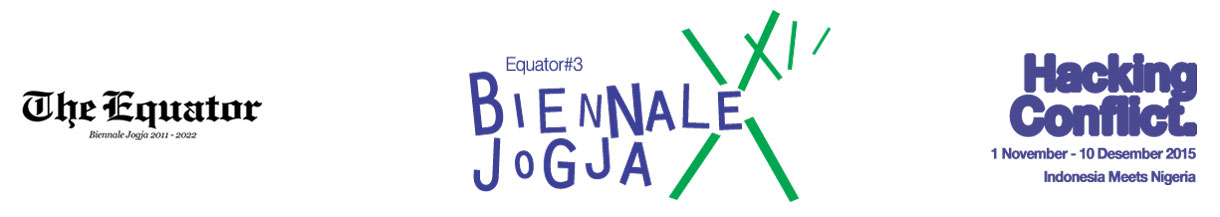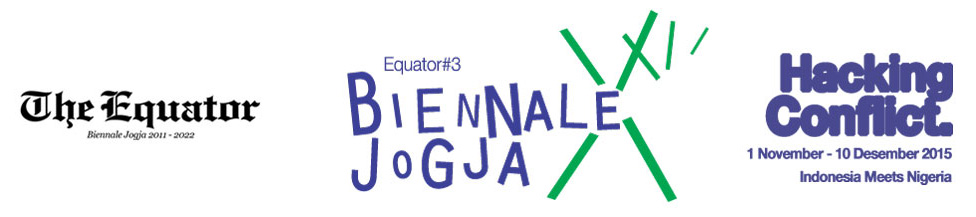Pada bulan Juli 2014 lalu, dalam sebuah perjalanan di seputaran benua Eropa, saya mampir ke Frankfurt sebelum terbang kembali ke Indonesia. Frankfurt selalu menjadi kota ideal untuk saya sejenak berhenti, terutama karena saya punya beberapa teman baik di sana, yang berhubungan pula dengan kesenian. Dua teman saya bekerja untuk institusi yang cukup menarik, yang satu adalah Museum Modern Art Frankfurt, dan satu lagi adalah Museum Kebudayaan Dunia. Kebetulan ketika saya bertandang ke sana, dua institusi ini sedang menggelar pameran seni yang merujuk pada Afrika dan konteks kebudayaannya yang lebih luas.
Pameran pertama yang saya kunjungi adalah The Devine Comedy: Heaven, Hell and Purgatory Revisited by Contemporary African Artists di Museum Modern Art Frankfurt. Tak kurang dari 50 seniman Afrika, baik yang hibrid maupun mereka yang lahir dan besar di Afrika, terlibat dalam salah satu pameran terbesar yang berfokus Afrika dalam dua dekade terakhir ini. Pameran ini melibatkan pula sebuah struktur dramatika dalam teater, yang membuat alur pameran menjadi cukup hidup, karena terbagi dalam tiga babak, dengan fokus pada relasi dua tokoh dalam drama karya Dante Alighieri yang digunakan sebagai judul pameran: The Devine Comedy. Kurator pameran, Simon Njami (kurator Afro-Eropa berbasis di Paris), mengundang para seniman untuk menerjemahkan gagasan inferno melalui karya-karya mereka. Pendekatan tema yang cukup spesifik ini membuat pameran ini tidak terlalu memberi kesan sebagai pameran survey untuk memperkenalkan seniman Afrika kontemporer, tetapi mempelajari lebih dalam gagasan seniman dalam satu tema khusus. Meski demikian, saya tetap merasa tema yang ditawarkan terlalu kering dan romantis untuk membicarakan konteks Afrika kontemporer, yang tentu saja melingkupi beragam dimensi sosial politik yang berkelindan mulai dari pasca-kolonialisme, globalisasi budaya, kreolisasi, dan sebagainya. Sebagian karya yang dipamerkan terutama beririsan dengan gagasan atas agama dan mitologi, atau citra visual dari dewa dan figur-figur dalam narasi besar di berbagai suku di Afrika, dengan konteks politik yang menurut saya cenderung superfisial. Meski demikian, dalam hal bentuk dan kecenderungan estetik, Simon Njami berhasil menjajarkan berbagai medium mulai dari lukisan, instalasi, fotografi, video instalasi, beberapa dalam skala yang cukup massif, dalam desain pameran yang mudah dinikmati. Pameran ini memajang karya dari beberapa nama besar tradisi seni kontemporer Afrika yang sekarang banyak menghiasi berbagai biennale, pameran museum dan art fair internasional seperti Ghada Amer (Mesir), Kader Attia (Prancis), Julie Mehretu (Etiopia), Wangechi Mutu (Kenya), Aida Muluneh (Etiopia) dan sebagainya.
Hari berikutnya, saya mengunjungi pameran di Museum Kebudayaan Dunia, untuk bertemu teman saya Dr. Clementine Deliss, direktur museum tersebut. Pameran yang sedang diadakan di sana, “Foreign Exchange” memang tidak secara langsung berfokus pada Afrika, tetapi ada beberapa seniman Afrika yang diundang untuk menciptakan satu karya yang merupakan hasil bacaan dan terjemahannya atas berbagai arsip dan koleksi museum yang sebagian besar merupakan artifak etnografi. Beberapa seniman meneliti foto-foto koleksi museum yang berhubungan dengan “cara memandang”; bagaimana lensa kamera yang diarahkan pada masyarakat adat di pedalaman, oleh para peneliti atau etnografer masa lalu, merupakan representasi kekerasan kolonialisme yang ampuh dengan menggunakan kamera sebagai senjata. Dr Deliss sendiri merupakan salah satu pakar penting dalam wilayah kajian seni kontemporer Afrika, terutama ketika ia menyelenggarakan Afrika 95, sebuah festival besar di London yang untuk pertama kalinya membicarakan Afrika dalam perspektif sosial politik kontemporer.
Pengalaman menonton dua pameran dalam waktu bersamaan, dan juga membaca sebuah ulasan atas pameran Afrika lainnya di Eropa pada periode tersebut, saya merasa perlu mempertanyakan lebih jauh bagaimana modus-modus pameran bercorak atau yang mengusung nama Afrika ini berlangsung di berbagai belahan dunia dalam kurun waktu setidaknya dua dekade lebih ini. Pertemuan saya dengan beragam pelaku seni dari benua Afrika, termasuk mereka yang telah banyak menjadi kurator internasional berkedudukan di Eropa atau Amerika , membawa saya pada pembacaan-pembacaan kritis untuk merespon fenomena ini.
Tahun 1989, kurator Jean Hubert Martin dari Center Pompidou Paris, menyelenggarakan pameran penting berjudul Magiciens de le Terre, yang pada akhirnya memberi perubahan besar pada lanskap seni kontemporer dunia, terutama karena pameran ini memberi ruang yang cukup signifikan pada seniman dari Negara-negara Asia dan Afrika yang pada waktu itu lebih sering tampak sebagai “liyan” (others). Dalam sejarah seni kontemporer, pameran ini menghasilkan apa yang disebut sebagai “global turn”, juga merujuk dari peristiwa bersejarah runtuhnya tembok Berlin pada tahun yang sama, pasca peristiwa Tiannamen, dan sebagainya. Pada tahun-tahun selanjutnya, semakin banyak pameran diselenggarakan dengan mengikutsertakan seniman-seniman dari Negara Afrika, dan beberapa di antaranya merupakan pameran skala besar (blockbuster exhibitions) seperti Africa Explore (1991) di New York dengan Susan Vogel sebagai kurator dan pameran Africa Remix (2004), dengan arahan artistik Simon Njami, yang berawal di Dusseldorf Jerman, lalu mampir ke London, Johannesburg dan Tokyo pada tahun-tahun berikutnya. Meski pameran-pameran skala besar semacam ini memberikan kontribusi atas makin tampilnya, atau meningkatnya visibilitas seni kontemporer Afrika, akan tetapi sebagian besar kritikus dan sejarawan juga mengenangnya sebagai upaya menampilkan Afrika sebagai sebuah wilayah yang eksotis. Sebagian besar peristiwa seni semacam ini diinisiasi dan dikuratori oleh institusi dari luar Afrika sendiri, sehingga tidak sepenuhnya bisa menyuarakan perspektif orang dalam. Pada periode yang sama, kurator-kurator Afrika terkemuka seperti Okwui Enwezor atau Olu Olguibe, lebih banyak bekerja dengan seniman-seniman Afrika diaspora, yang memang tersebar di seantero Amerika dan Eropa, atau mereka yang telah dikenal dan mapan seperti William Kentridge atau Yonke Shonibar, misalnya.
Dalam ranah kuratorial, benua Afrika juga menunjukkan kemunculan figur-figur kurator internasional yang disegani, seperti Okwui Enwezor, N Gone Fall, Olabisi Silva, dan beberapa nama lain. Sebagian besar dari mereka memang mengenyam pendidikan formal di Eropa atau Amerika, baik belajar Ilmu Politik, Susastra dan bidang ilmu sosial lain. Okwui Enwezor misalnya, baru semester belajar di Universitas Nigeria, memutuskan untuk pergi ke Amerika, dan belajar politik di Jersey City State College. Ia banyak mempelajari sastra dan puisi sebelum akhirnya berada di lingkup pergaulan seni rupa kontemporer. Pameran awalnya yang mengundang perhatian dunia adalah In/Sight: African Photographers, 1940 to Present, yang menampilkan karya dari 30 fotografer Afrika di Guggenheim Museum di New York pada tahun 1996. Pameran ini merupakan penanda kuat untuk mempresentasikan “cara lihat baru” (a new way of seeing, merujuk pada John Berger) atas Afrika. Pameran ini juga membuka pada publik riset panjang yang dilakukan oleh Okwui Enwezor terhadap arsip citra visual berkaitan dengan Afrika dan representasinya secara umum. Setelah pameran itu, ia juga merancang pameran foto terpenting dalam isu poskolonialisme dan rasialisme, Rise and Fall of the Apartheid: The Bureaucracy of Everyday Life di International Center of Photography, New York.
Generasi kurator pasca Okwui Enwezor sendiri kemudian banyak mengritik kecenderungan kurator senior yang lebih sering mempromosikan seniman Afrika diaspora ketimbang mencoba untuk bekerja dan memahami situasi Afrika kontemporer dari ranah Afrika sendiri. Perkembangan seni rupa Afrika pada pertengahan 1990an dan sesudahnya memang cukup pesat dengan makin terbukanya wilayah ini pada arena global. Pameran-pameran Afrika berlangsung di berbagai belahan dunia, mulai London, New York hingga Tokyo, sementara seniman mereka terus menjadi bagian dari pergerakan dinamis seni rupa kontemporer dengan keikutsertaan mereka di berbagai pameran di museum dan biennale/triennale internasional.
Fenomena menarik terbaru adalah kemenangan pavilion nasional Angola pada Venice Biennale 2013. Angola merebut tempat kehormatan, mendapat Golden Lion yang sangat bergengsi, ketika mempresentasikan Edgor Chagas dengan karyanya Luanda, Encyclopedia City. Kemenangan Angola ini mematahkan dominasi Negara-negara dunia pertama dalam sejarah Venice Biennale seperti Jerman, Perancis, Swiss, Inggris, dan sebagainya. Paviliun Angola mempresentasikan tidak saja satu kecenderungan estetik yang cukup radikal, tetapi juga membawa diskusi tentang fenomena pertumbuhan kota dan ruang publik di Afrika, yang dipresentasikan dalam sebuah respons yang menarik atas kelas borjuis Eropa melalui pemilihan ruang pameran yang serupa vila kelas atas.
Menanggapi situasi eksotisisme atas seni Afrika yang terus berlanjut, N Gone Fall, salah satu generasi kurator Afrika pasca 1990an, menyebutkan: “Apakah semua pameran ini menyebutkan kata Afrika dalam judul pamerannya untuk meyakinkan penonton bahwa mereka sedang menonton sesuatu yang betul-betul berbeda dan spesial? Hampir semua pameran ini mengandung konten yang sangat lemah, kalau tidak bisa dibilang kosong, bahkan nyaris mirip dengan pameran nasional Afrika yang diselenggarakan tahun 1960an dan berkelana keliling dunia. Seolah-olah motivasi satu-satunya untuk membuat pameran ini adalah untuk merayakan budaya Afrika secara internasional. Tetapi, apakah seni itu hanya semata tentang perayaan? Apakah seniman-seniman Afrika itu cuma rombongan hiburan yang tidak punya pemikiran dan hal-hal untuk dikatakan?”
N Gone Fall saya kira menyebut poin penting untuk digarisbawahi: bahwa melibatkan seniman dari sebuah wilayah kebudayaan bukan saja menjadi laku untuk merayakan keberagaman, tetapi lebih merupakan upaya untuk mendiskusikan gagasan-gagasan yang signifikan dan kritis sehingga ada rintisan untuk menciptakan dunia yang lebih adil. Saya sendiri melihat bahwa ada banyak seniman yang menciptakan karya menarik dan kritis, yang isunya tidak saja bisa dibawa untuk berbicara tentang Afrika, tetapi merefleksikan lebih jauh apa yang terjadi secara universal di berbagai belahan dunia. Karya-karya monumental Kader Attia dan William Kentridge adalah inspirasi yang sangat berharga untuk mendiskusikan gagasan eksploitasi dan kolonialisme, dan penting pula bagi kita untuk belajar bagaimana melihat sejarah dari perspektif yang kalah. Pada karya-karya seniman generasi awal seperti mereka, narasi-narasi besar pasca perang, kisah perbudakan dan genoside merupakan isu yang digali sebagai bagian dari upaya memformulasikan gagasan nasionalisme dan kebangsaan. Ini juga bisa dijumpai sesungguhnya pada gerakan kebudayaan Asia pada periode yang sama (sekitar akhir 1950an dan 1960an), misalnya pada kasus upaya besar-besaran dari Presiden Soekarno untuk menjadikan seni dan budaya sebagai senjata diplomasi, dan keinginannya untuk membangun hubungan dengan Negara-negara non imperialis, termasuk di dalamnya Negara Asia Afrika.
Generasi seniman muda seperti Otobong Ngkana, kelompok seniman Invisible Borders, Kemang Wa Lehulere, Lynette Yiadom Boakye, dan sebagainya mewakili satu generasi baru yang membicarakan Afrika dengan perspektif baru dan pendekatan yang segar, yang membagi bahasa-bahasa visual atau persoalan yang barangkali sama dengan seniman muda di tempat-tempat lain. Generasi muda ini juga terbuka pada platform seni yang baru, di mana mereka bertemu dan bekerja dengan kelompok aktivis, akademisi ataupun inisiatif komunitas, untuk membawa seni menjadi bagian dari ruang baru untuk bersuara.
Oleh: Alia Swastika
*gambar: Kemang Lawahere, karya yang dipamerkan di Berlin Biennale 8, Dahlem Museum, 2014.