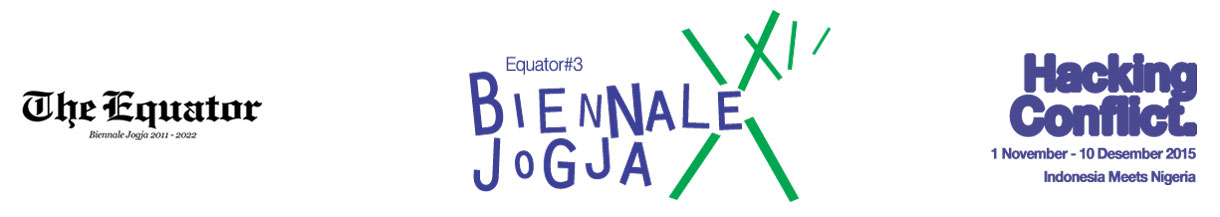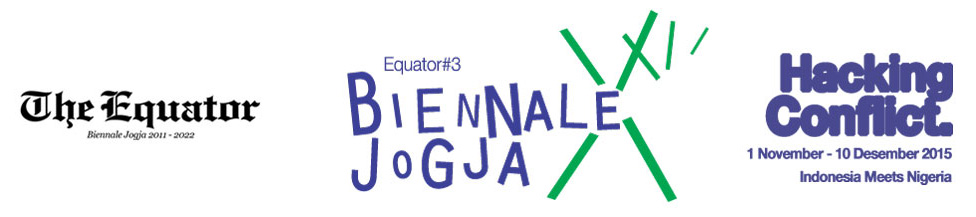Oleh Arie Setyaningrum Pamungkas*
Saya memilih judul pembuka ‘Perlukah Menghadirkan Sang Liyan?’ sebagai sebuah pertanyaan retoris yang akan saya jabarkan dengan mengaitkan dua momentum yang berlangsung pada 2015. Pertama adalah peringatan ke 60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) pada pertengahan April 2015 dan kedua, penyelenggaraan Jogja Biennale Equator#3 pada akhir tahun 2015. Kedua momentum ini menempatkan konteks singgungan (tangible context) khususnya antara Indonesia dan Afrika. Lantas apa pentingnya mengaitkan peringatan KAA ke 60 dengan penyelenggaraan Jogja Biennale Equator#3? Apakah semangat KAA masih cukup relevan untuk menempatkan konteks kesejarahan negara-negara pascakolonial ini secara tematik ke dalam kegiatan atau aktivitas Jogja Biennale Equator? Mari kita telaah konteks singgungan ini dengan menempatkan gagasan keberadaan ‘Sang Liyan’ (Otherness) yang secara esensial merupakan spirit (ruh penyemangat) dalam penyelenggaraan keduanya.
Rekontekstualiasasi KAA: Redefinisi Konteks Pascakolonial di Era Pasar Bebas
Dalam edisi Newsletter The Equator edisi 5 Mei 2014, Sayfa Auliya Achidsti secara kritis mencermati penyelenggaraan KAA yang hanya merupakan nostalgia masa lalu dan menyisakan beban tugas diplomasi dan kerjasama yang masih belum strategis di antara negara-negara Asia-Afrika khususnya dalam menghadapi kompetisi di dalam sistem pasar bebas. Meskipun dalam penyelenggaraan peringatan ke 60 tahun KAA pada bulan April 2015 ini pemerintah Indonesia menawarkan suatu skema kemitraan, khususnya dalam peningkatan strategi pembangunan ekonomi antarnegara-negara peserta KAA (NAASP –New Asian-African Strategic Partnership), sesungguhnya nuansa romantisme masa lalu sebagai ikatan simbolis masih terasa kental. Hal ini nampak pada upaya untuk meletakkan posisi sejarah politik dekolonisasi negara-negara peserta KAA sebagai landasan moral etis bagi eksplorasi sumber daya ekonomi baru antar-negara peserta KAA dalam menghadapi kekuatan pasar dunia. Suatu landasan moral etis yang nampaknya masih dibayang-bayangi logika melawan dominasi kolonialisme ‘Barat’, tetapi sesungguhnya menyembunyikan potensi yang rapuh, khususnya ketika eksplorasi pada sumber daya manusia dan alam diarahkan semata-mata untuk kepentingan ‘market-driven’, yakni tetap mengapropriasi logika neo-kapitalisme yang dijalankan di era pasar bebas. Dalam konteks ini, penyelenggaraan KAA lebih diutamakan pada bagaimana mengoptimalkan peran masing-masing pemerintah untuk memenuhi tuntutan kompetisi pasar bebas dunia. Padahal dalam kenyataannya, 60 tahun setelah deklarasi Bandung itu banyak terjadi perubahan pada peta geopolitik, geososial, geoekonomi dan lanskap kultural pada setiap negara bangsa peserta KAA.
Pertama, rekontesktualisasi penyelenggaraan KAA belum mengkritisi peranan aktor dan agensi yang selama 60 tahun hampir luput dari pembahasan politik dan pemberdayaan sosial di negara-negara berkembang, yakni para aktor dan agensi korporasi khususnya korporasi global. Dalam konteks ini, pemerintah di negara-negara peserta KAA masih berposisi sebagai agen yang pasif dan hanya menempatkan agenda pertumbuhan ekonomi ketimbang implikasi sosial, kultural dan ekologis dari eksploitasi sumber daya alam secara massif yang ditujukan untuk mengejar angka pertumbuhan ekonomi. Pemerintah di masing-masing negara peserta KAA belum memiliki komitmen untuk melihat sejauh mana tanggung jawab korporasi global terkait keterlibatan mereka di dalam penanaman modal yang berimplikasi pada lingkungan ekologis, sosial, dan budaya. Hal ini nyaris luput dari agenda pembahasan penyelengaraan ke 60 tahun KAA, padahal peta geopolitik dunia saat ini sudah tidak lagi dibayangi oleh kekuatan blok-blok ideologi nation-state (blok sekutu-blok sosialisme/komunisme) sebagaimana 60 tahun yang lalu. Dalam konteks ini, redefinisi semangat KAA yang menekankan pada aspek dekolonialisasi sudah seharusnya menempatkan aspek kebudayaan bangsa-bangsa pascakolonial, bukan semata pada tuntutan mengejar keuntungan kompetisi pasar bebas dalam ukuran investasi penanaman modal asing dan pendapatan domestik suatu negara yang semu, sebab kerangka politik developmentalisme ini tidak sepenuhnya menjangkau partisipasi lokal dan kreativitas yang berbasis pada keseimbangan sumber daya dan lingkungan ekologis. Laporan Bank Dunia mengenai FDI (Foreign Direct Investment) pada awal tahun 2000 menunjukkan bahwa penanaman modal asing di negara-negara Afrika lebih didasari atas seleksi kekayaan sumber daya alam (industri minyak dan mineral misalnya), seperti contohnya yang berkembang di Nigeria, Afrika Selatan, dan Ghana ketimbang pengembangan industri berbasis padat karya seperti pertanian dan industri kreatif berbasis rumah tangga. Sementara itu, dalam dua dekade terakhir ini, peranan FDI di beberapa negara Afrika mulai memasuki babak baru ketika investor dari negara-negara pascakolonial yang mulai menjadi pemain dalam kekuatan ekonomi dunia, seperti Cina, Malaysia, dan Uni Emirat Arab yang juga ikut melirik potensi investasi di beberapa wilayah Afrika. Meski demikian, lagi-lagi banyak negara di Afrika (kecuali Afrika Selatan) seakan-akan masih nampak sebagai agen yang pasif–karakter FDI selain pada eksploitasi sumber daya alam juga ditujukan untuk menjadikan kawasan Afrika sebagai target pasar baru. Dengan kata lain, investasi itu dijalankan dengan mempertimbangkan pertumbuhan demografi di Afrika sebagai pasar yang besar, prospek konsumen baru bagi berbagai produk di pasar bebas.
Berbeda dengan sejarah penanaman modal Barat di Afrika yang erat kaitannya dengan sejarah kolonialisme dimana eksploitasi alam dan manusia dijalankan secara represif, investasi Cina di Afrika justru dilatarbelakangi oleh semangat Gerakan Non-Blok. Pemerintah Cina hanya memfasilitasi investor-investor Cina yang ingin menanamkan modal di Afrika tanpa membebani pemerintahan di negara-negara Afrika dengan persyaratan ideologis di dalam proses diplomasinya–sesuatu yang coba ditiru oleh pemerintah Indonesia melalui penjajakan NAASP. Ironisnya, dalam penjajakan kerjasama ekonomi dengan negara-negara Afrika, pemerintah Indonesia justru menggunakan platform yang hampir sama dengan model FDI ala negara-negara Barat, yakni investasi pada eksplorasi pada sumber daya mineral, bukan pada alternatif pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
Investasi Cina, khususnya pada pengembangan industri agribisnis di Afrika sepertinya menjadi semacam model bagi banyak negara-negara pascakolonial lainnya selain tetap berfokus pada eksplorasi sumber daya alam dan mineral. Kemitraan negara-negara Afrika dalam investasi dengan Cina juga dibarengi oleh pembangunan infrastruktur melalui peningkatan pinjaman luar negeri, contohnya pada 2005 bantuan lunak pemerintah Cina berjumlah 800 juta USD dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 10 milyar USD (Ayodele dan Sotola, 2014:5). Meski demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa kepentingan strategis Cina melalui investasi di negara-negara Afrika memang lebih banyak dilatarbelakangi oleh motif serupa, yakni memperoleh sumber daya alam dalam bentuk raw material (terutama minyak bumi) dengan harga yang murah (ibid:6).
Dalam dua dasawarsa terakhir, implikasi penanaman modal asing oleh negara-negara pascakolonial (non-Western) di Afrika bukan hanya mempengaruhi bagaimana relasi politik pemerintah di negara-negara tersebut, melainkan juga mengubah reproduksi sosial dan lanskap kultural di Afrika seperti pola-pola konsumsi mereka. Pembahasan mengenai strategi ketahanan pangan yang berbasis pada tradisi lokal misalnya, justru luput dari agenda kemitraan negara-negara peserta peringatan KAA ke 60 di tahun 2015 ini.
Kedua, strategi kebudayaan dan upaya untuk mengembangkan kerjasama budaya dalam peringatan KAA ke 60 lebih dimaknai sebagai pelengkap (komplementer) saja, bukan sebagai sesuatu yang secara esensial menjadi eksplorasi ‘baru’ bagi reproduksi sosial yang bersifat mutual di antara negara-negara peserta KAA. Dalam konteks ini, kebudayaan yang bersifat komplementer lebih menjadi atribut pelengkap tujuan atau motivasi kerjasama ekonomi yang bias ‘market-driven’ tadi. Di titik ini, pergeseran ideologi nation-state seperti nasionalisme sudah mulai usang dan mendapat tantangan baru dari tumbuhnya berbagai bentuk ideologi yang bersifat transnasional, seperti misalnya paham-paham radikalisme berbasis keagamaan.
Tragedi dan konflik berdarah yang akhir-akhir ini berlangsung di beberapa negara Afrika sepertinya masih belum menjadi perhatian diplomasi pemerintah Indonesia. Padahal, dalam era globalisasi, pertarungan ideologis kini justru dimotivasi oleh isu-isu ketimpangan sosial dan upaya segelintir elit untuk terus berkuasa dengan menggunakan wacana perlawanan yang berbasis pada ketidakadilan sosial. Dalam konteks inilah seakan-akan ada benang yang terputus di antara negara-negara Asia-Afrika, dimana dalam imaji kita masih didominasi oleh wacana yang justru bersumber dari sejarah kolonialisme. Dengan kata lain, kita di Indonesia hampir buta atau kurang mengenal sejarah budaya dan perkembangan sosial masyarakat di Afrika yang juga majemuk. Semangat KAA pada masa kini sudah seharusnya ditempatkan pada esensi awalnya, yakni mengupayakan kemandirian bangsa-bangsa di ‘Dunia Ketiga’, bukan sekadar ‘survive’ di dalam era kompetisi pasar bebas, melainkan juga pada upaya untuk berbagi pengetahuan mengenai resiko sosial, politik dan ekologis yang harus dihadapi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika dalam menjalani perubahan pola relasi dominasi kekuasaan di dunia dan cara-cara mengatasinya.
Menengok Afrika: Sang Liyan yang Tercecer dan Penyelenggaraan Jogja Biennale Equator#3
Sebagaimana yang telah saya kemukakan sebelumnya, fokus pada strategi kebudayaan merupakan hal yang tercecer dalam penyelenggaraan peringatan KAA ke 60 di Bandung pada bulan April 2015 ini. Jika oleh beberapa pihak terkait peringatan itu dianggap bukan sekadar momentum nostalgia, melainkan juga menawarkan agenda kerjasama politik dan ekonomi melalui platform baru, sesungguhnya tak ada yang benar-benar baru di sana. Relasi dominasi pengetahuan sebagaimana yang menjadi ‘mode of production’ (cara-cara berproduksi) dari masa kolonial nampak tetap berlanjut. Kita di Indonesia nyaris buta dengan perkembangan budaya dan reproduksi sosial di Afrika. Berita dan wacana mengenai Afrika yang kita konsumsi melalui media hanya merupakan reproduksi dari apa yang menjadi kepentingan media arus utama di dunia. Dengan kata lain, kita memandang Afrika dengan stigma tertentu. Baik mengenai eksotisme Afrika, maupun posisi mereka yang minor di dalam peta ekonomi dan politik global. Padahal, persoalan kemanusian dan keseharian yang dijalani di seluruh dunia ini terpengaruh oleh modernitas. Suku-suku di pedalaman Afrika pun ikut terpengaruh pada perubahan reproduksi sosial secara global. Apa yang mereka makan bisa jadi sama atau hampir serupa dengan yang kita makan sehari-hari. Begitu pula hal-hal lain semisal dalam pencapaian cita-cita setiap individunya.
Upaya dekolonialisasi melalui kemandirian bangsa-bangsa Asia dan Afrika sebagaimana yang menjadi landasan moralitas etis KAA di Bandung, enampuluh tahun yang silam, merupakan upaya untuk menghadirkan keberadaan ‘Sang Liyan’ sebagai tali pengikat atas dasar kesamaan nasib dan kini membutuhkan rekontekstualisasi. Meski demikian, kita tidak lagi bisa semata-mata memandang ‘Barat’ sepenuhnya sebagai agen penerus bentuk-bentuk kolonialisme baru, sebab aktor atau agen yang terlibat di dalam peta ekonomi dan politik dunia tidak lagi mengenal batasan geopolitik, entah teritori ataupun ideologi nasionalisme.
Di sisi lain, keberadaan ‘sang liyan’ sebagai suatu citra pembeda tetap dibutuhkan di dalam memformulasikan strategi kebudayaan, karena itulah yang menghadirkan konteks sejarah yang mengacu pada penanda tertentu yang bersifat monumental dan narasi yang mewakili ekspresi kemanusiaan dan perubahan lingkungannya. Tetapi, apakah kita cukup memiliki pengetahuan tentang Afrika? Sebagai modal awal kita perlu menjelajahi kebudayaannya.
Seburuk apapun sejarah kolonialisme yang pernah berlangsung di benua Asia dan Afrika, setidaknya jejak pengetahuan yang ditinggalkannya memberi kita peta awal perihal bagaimana kita mulai untuk saling ‘mengenal’ satu sama lain. Hampir tak terbantahkan bahwa pengetahuan, termasuk mengenai keragaman budaya dan ekspresi seni di negara-negara koloni juga menjadi kekayaan yang hingga kini masih terdokumentasikan dengan baik di negara-negara bekas penjajah, khususnya di Eropa. Meskipun tentu saja, catatan dan dokumentasi itu juga memiliki bias kepentingan kolonial yang berlangsung pada konteks di masa itu. Meski demikian, setidaknya kita bisa berangkat dari konteks serupa, yakni bagaimana bangsa kita pernah mengalami kolonialisme dan bagaimana sejarah kolonialisme itu kini mempengaruhi berbagai bentuk ekspresi kemanusiaan kita.
Berangkat dari konteks ini pula, saya melihat penyelenggaraan Jogja Biennale Equator#3 perlu untuk mengidentifikasi tema-tema dan mendesiminasi pengetahuan mengenai sejarah budaya serta keberadaan Afrika bagi masyarakat Indonesia di dalam penyelenggaraannya nanti. Berikut ini setidaknya ada tiga tema besar berkenaan dengan rekontekstualisasi semangat KAA dalam penyelenggaraan Jogja Biennale Equator #3 yang bisa saya tawarkan sebagai bagian dari kurikulum kegiatannya. Pertama, mengenai tema keragaman tradisi dan bagaimana tradisi memiliki arti (nilai) penting bagi masyarakatnya kini serta bagaimana pelembagaan tradisi berlangsung, khususnya yang berpengaruh pada sejarah dan praktek seni rupa modern di Afrika serta kesamaan-kesamaan apa yang juga dialami di dalam konteks Indonesia. Hal ini menjadi penting dikarenakan seni rupa merupakan medium berkesenian yang sangat dekat dengan pelembagaan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara-bangsa. Kedua, mengenai tema gerakan sosial dan politik yang mempengaruhi ekspresi berkesenian sehingga memberi corak pada berbagai ‘genre dan style’ seni rupa Afrika modern kini dan relasinya dengan sejarah globalisasi di Afrika dan Asia khususnya. Ketiga, tema mengenai pertemuan yang melintasi batas teritori dan nasionalisme, semisal bagaimana pengaruh kolonialisme di dalam perkembangan wacana atau praktek seni rupa termasuk yang dijalankan oleh komunitas diaspora dan bagaimana praktek atau wacana seni rupa modern menjadi ruang alternatif baru dan bahkan medium aktivisme dalam mengekspresikan komplesitas kemanusiaan, khususnya di wilayah yang kini masih berjuang untuk mandiri dari dominasi kekuatan ekonomi dan politik dunia.
***
Sumber Bacaan
Achidsti, Sayfa Aulia, 2014. Indonesia-Afrika Bukan Hanya Romantisme Sejarah, dalam ‘The Equator Edisi 5 Mei 2014’. Newsletter Jogja Biennale Equator: Yogyakarta.
Ayodele, Thompson dan Sotola, Olusegun, 2014. ‘China in Afrika: An Evaluation of Chinese Investment’, IPPA (Innitiative for Public Policy Analysis) – Working paper: Laghos, Nigeria
Bogaerts, Els dan Raben, Remco, 2012. ‘Beyond Empire and Nation: The Decolonization of Asian and African Societies 1920s-1960s’. KITLV Press: Leiden.
Kemetrian Luar Negeri Indonesia, 2012. New Asian-African Strategic Partnership: Senior Official Meeting. Diakses secara online melalui alamat http://www.kemlu.go.id/Documents/NAASP/Hyperlink%202.pdf. Diakses pada 8 April 2015.
_____
* Arie Setyaningrum Pamungkas adalah staf pengajar di Departemen Sosiologi, UGM, aktivis budaya dan pengamat seni rupa.
Gambar: diambil dari www.liputan6.com