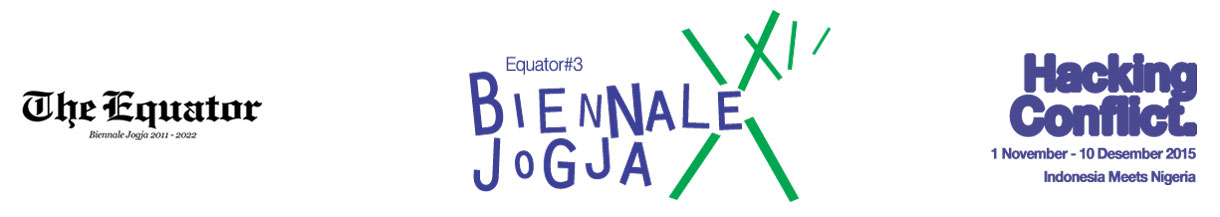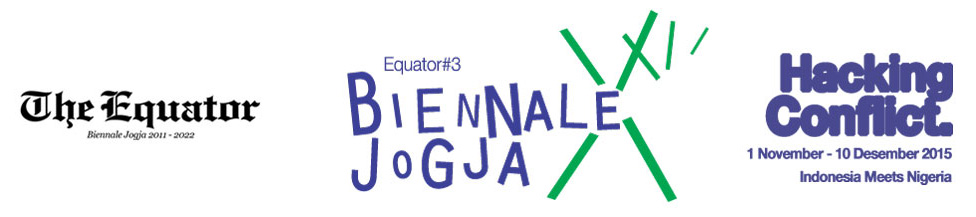“1000 kali seniman tak berpolitik, 1000 kali pula politik mencampuri seni dan seniman”
– Amir Pasaribu
Kutipan dari komposer musik legendaris Indonesia itu saya temukan dari kliping koran tua Harian Rakjat edisi 13 April 1957. Kutipan itu berumur 57 tahun jika diukur dari masa saat Glenn Fredly, Bimbim Slank, dkk “mengorganisasi” musisi untuk menjadi relawan politik riil Indonesia di Pemilu Indonesia ke-12. Seniman-seniman itu secara terbuka mendukung kandidat presiden Joko Widodo dan kandidat wakil presiden Jusuf Kalla.
Peristiwa panggung musik politik 5 Juli 2014 di Gelora Bung Karno Jakarta itu saya baca sebagai kembalinya spirit Amir Pasaribu dalam bermusik yang tak alergi dengan keterlibatan politik langsung dan terbuka. Politik bukan iblis yang mesti dihindari, melainkan dirawat bersama dalam kepemimpinan rakyat.
Dan pada pemilu ke-12 ini muncul keterlibatan lain yang berbeda dengan dua model keterlibatan sebelumnya, yakni keterlibatan yang cair dan tanpa bayaran. Keterlibatan yang bersifat sukarela ini bersifat ad hoc, sementara, tanpa ada iming-iming uang, kecuali panggilan untuk menjadi peserta dan bukan penonton politik.
Dalam sejarah pemilu, jumlah keterlibatan relawan seni, terutama dimotori musisi yang memiliki lapisan pengikut yang luas, adalah terbesar dan tiada tanding setelah Pemilu 1955. Mereka tak diikat oleh organisasi yang bersifat partisan, melainkan jaringan teknologi komunikasi. Walau bukan pendukung partai politik tertentu, mereka hadir menyuarakan apa yang disebut Amir Pasaribu sebagai cara “memikirkan nasib kemadjuan bangsanja dalam pemikiran semua segi hidupnja”.
Sukwan/wati seni itu terlibat dalam kompetisi yang sengit lewat jalur telinga dan mata. Di lajur kompetisi telinga, beraneka bunyi-bunyian kreatif ditanam dan ditautkan di mesin penyimpan maya seperti soundcloud. Dari semua genre ada: dari rock hingga dangdut.
Sementara di lajur mata, pelbagai poster, komik, meme/mim diproduksi, di laman web, dan disebarkan secara masif lewat media sosial. Adapun partisipasi kreatif sukwan/wati di lajur campuran antara mata-telinga (audio-visual) terdokumentasi dengan baik di laman youtube.
Munculnya seniman di politik riil itu tentu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Sejarah panjang seni di Indonesia, terutama seni rupa, memberikan konfirmasi bagaimana pergulatan politik dan seni dalam berkarya dan bagaimana seni dan politik hidup berdampingan menyuarakan aspirasi dukungan maupun protes terhadap kekuasaan.
Esai ini menjelajahi wajah seni dan politik, terutama sekali yang terjadi di Yogyakarta. Kota yang berkali-kali diterjang chaos, berkali-kali pula menyeimbangkannya. Mulai dari Perang Diponegoro, agresi militer Belanda setelah 19 hari Republik Indonesia diproklamasikan, pawai “sejuta massa” pada masa genting 1998, hingga warga kota ini bergegas bangkit dari reruntuhan guncangan bumi 27 Mei 2006. Kota Yogyakarta menjadi “Kota Revolusi” tatkala pemerintahan Soekarno-Hatta pada 4 Januari 1946 memilih memindahkan ibukota Republik Indonesia ke Yogyakarta. Di masa inilah Yogyakarta nyata menjadi pusat peradaban yang lebih kompleks. Jalan Malioboro berubah menjadi ekologi simbolik baru bagi kota Yogyakarta, yaitu menjadi arena persebaran makna dan gagasan serta citra baru pada masa revolusi di lingkungan kota Yogyakarta.
Yogyakarta sendiri sebenarnya sudah cukup siap untuk dijadikan, tidak hanya pusat kebudayaan Jawa, melainkan menjadi tempat di mana revolusi dan perlawanan atas kolonialisme bisa berlangsung dengan sengit, tidak hanya di medan pertempuran senjata, tetapi juga di medan kebudayaan. Seni rupa adalah salah satu palagan revolusi dan politik itu.
Seni yang Terlibat: Genealogi Persekutuan Politik Praktis dan Seni Rupa
1955 adalah tahun sibuk untuk sebuah negara-bangsa yang baru satu dekade merdeka. Dimulai dari kesuksesan Indonesia menjadi tuan rumah bagi perhelatan akbar yang melibatkan negara-negara Asia dan Afrika. Konferensi Asia Afrika di Bandung itu, bukan saja melahirkan pernyataan politik radikal atas relasi bangsa-bangsa yang terprentah dan diprentah – meminjam istilah Tirto Adhi Soerjo tahun 1907 – tapi juga sikap sinis dan nyinyir dalam negeri. Terutama lawan (kawan?) politik Sukarno semacam pengikut Sjahrir dan Hatta. Dua nama itu bukan saja absen dalam KAA, tapi juga koran-koran yang diterbitkan kelompok “soska” ini menyambut dingin konferensi yang ditutup tepat ketika hari pertama umat Islam menjalankan ibadah di bulan Ramadhan.
Kesuksesan penyelenggaraan KAA itu menerbitkan wuwungan optimisme bahwa Indonesia pasti bisa menyelenggarakan pemilu yang demokratis; suatu percobaan politik demokratis pertama yang sangat menentukan. Di Pemilu inilah kita menemukan satu fase bagaimana seni diuji di lapangan politik praktis di “masa damai”. Di masa liberalisme politik 50-an, perupa bukanlah penonton, tapi terlibat aktif di dalamnya.
Perupa-perupa yang turut membidani lahirnya Persatuan Ahli Gambar Indonesia (Persagi), Seniman Indonesia Muda (SIM), dan Pelukis Rakjat di Yogyakarta, misalnya, menjadi salah satu tulang punggung kemenangan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Kota Yogyakarta. Pemilu 1955 adalah pintu masuk bagi perupa Soedjojono dan Affandi untuk masuk dalam politik praktis. Keduanya adalah dua dan 10 wakil PKI yang berasal dari seniman dan budayawan yang lolos menjadi anggota DPR. (Harian Rakjat, 17 September 1955)
Kehadiran seniman-seniman ini di arena politik praktis bukan tiba-tiba. Tempaan revolusi fisik membajakan keyakinan mereka bahwa seni dan politik bukan sesuatu yang bermusuhan. Mazhab realisme kerakyatan dalam seni rupa yang diusung pentolan SIM Soedjodjono dan pentolan Pelukis Rakjat Hendra Gunawan membawa pada sebuah simpul bahwa seni adalah keluarga politik, di mana seniman adalah subjek penentu jalannya revolusi. Meminjam kata-kata Soedjojono: “Namakanlah saya bukan seniman; saya lebih baik jadi manusia daripada ‘seniman’ zonder politik, daripada ‘seniman’ zonder rasa tanggungjawab atas nasib manusia yang ada kebetulan di sudut dunia ini, yang orang katakan bangsa Indonesia. Saya turut revolusi. Saya tidak turut saja, tetapi juga turut menetapkan revolusi itu harus kemana.” (Soedjojono, 2013)
Seni yang terlibat di arena politik riil, bisa kita lihat dari keterlibatan seniman-seniman yang menopang revolusi dalam pelbagai front. Terutama seksi propaganda kemerdekaan. Narasi sejarah lahirnya poster “Ajo Bung!” menjadi tonggak klasik keterlibatan itu. “Seni yang terlibat” adalah seni yang memiliki garis lurus yang tegas antara karya dan laku. Bukan “seni yang terlibat” bila karyanya saja yang politis, tapi kehidupan praktis sehari-hari seniman justru apolitis.
Nyaris sepanjang dekade revolusi, seni rupa bertendens yang dipundaki perupa-perupa avant garde dari Yogyakarta dipandang sebagai antitesis dari gaya lukis Mooi Indie yang sangat terkenal sebelum kemerdekaan dengan seniman-seniman garda depannya seperti Raden Saleh, Abdullah Sr. (ayah Basuki Abdullah). Abdullah, misalnya, selalu menggambarkan alam Hindia Belanda yang serba indah. Gunung-gunung biru yang melatarbelakangi sawah dengan padi menguning, rumpun bambu dan pohon nyiur di pinggirnya. Jika ada tiang telepon atau rel kereta api atau gardu-gardu pekerja berdiri di pinggir segera dihilangkan.
Apa seni rupa baru antitesis Mooi Indie itu? Soedjojono memberikan penegasan: “Seni loekis jang tidak mempropagandakan kebagoesan, akan tetapi mempropagandakan kebenaran pada tiap-tiap orang…. Kebagoesan jang disebabkan oleh warna-warna tjantik dan garis-garis jang berkembang-kembang (sierlijk) sadja sebagai sebagai lagak radja djin bangsawan, belum tentoe kebagoesan jang benar, sebab biasanja kebagoesan jang demikian hanja hendak menoetoepi kekosongan batinnja sadja… Peloekis-peloekis kita jang terbanjak hanja verfbedienden dari toeris-toeris jang datang makan angin kesini sadja. Dan poeblik misih maoe dihipnotis oleh kebagoesan bombasme, bluf dan lagak radja djin bangsawan sadja…” (Soedjojono, 1946)
Lebih lanjut Soedjojono menolak apa yang disebut “romantisch priangan” yang merupakan peristilahan yang lain dari Mooi Indie dan sekaligus menunjuk kawasan di mana gaya melukis ini sangat kuat: “Kita haroes tidak bisa hormat kepada seorang seniman peloekis jang enak-enak sadja menggambar lembah-lembah dan goenoeng tinggi mentjapai awan dan mimpi sorga doenia berkata: ,,O, romantisch Priangan”, tetapi ta’ maoe mendengarkan dibelakang dekat dia pak tani mengeloeh, merintih, menangis, sebab kakinja kena patjoel, berdarah, loeka parah. Gambarnja tadi barangkali bagoes, tetapi hati kemanoesiaannja ta’ ada, barangkali tergantoeng diawan soedah habis dipatoek elang atau dihantam petir melajang.” (Soedjojono, Ibid.)
Ketika J Hopman menulis sebuah esei di majalah Uitzicht pada 1948, Soedjojono menanggapinya sangat sengit dan keras. Hopman menulis bahwa seni lukis Indonesia itu tidak ada. Kalaupun ada ia membebek saja dengan seni di Barat. Menurut Soedjojono, Hopman mengalami kesalahan besar. Realisme yang dikembangkan oleh mazhab Yogya (baca Indonesia) tidak boleh dikatakan sebagai kepunyaan Barat belaka. Realisme adalah kepunyaan tiap-tiap manusia. “Kalau da Vinci, Durrer, Cazanne, kebetulan orang-orang Barat, ini bukan soal. Tiap-tiap anak Tuhan, meski dia di Betlehem (Kristus), meski di Mekkah (Muhammad), meski di Tiongkok (Laotz, Confusius, Li Tai Po), meski di India (Buddha), meskipun di Mesir (Ichnaton), di Amerika (Louis Amstrong, negro) atau di Eropa (Socrates, berlage, Cazanne) tidak berhak mengepak dan memonopoli teori-teori mereka kalau memang teori-teori tadi suatu kebenaran yang nyata dan baik untuk dunia.” (Soedjojono, Ibid.)
Kita bisa memahami reaksi sengit Soedjojono. Tak hanya karena masa itu adalah masa konfrontasi bersenjata dengan Belanda, tapi juga pencarian yang keras kekhasan seni lukis modern Indonesia zonder gaya Mooi Indie (baca: Belanda) yang dicekokannya kepada seniman Indonesia. Karena itulah, Soedjojono berpandangan, saatnya seniman-seniman Indonesia mencari arahnya sendiri atau dalam kalimat Soedjojono: “kami sudah tahu bagaimana dan ke mana kami akan bawa seni lukis kami”.
Dan Soedjojono, Hendra, Affandi, dan sederet pelukis-pelukis Yogyakarta yang tergabung dalam sanggar SIM dan Pelukis Rakjat membawa seni lukis mereka ke tendensi sosial yang kuat. Tendensi sosial itu bukan hanya berada dalam konsepsi, tapi juga cara hidup dan metode cara bagaimana lukisan itu diciptakan.
Untuk membuat sketsa dan melukis, para seniman yang tergabung dalam Pelukis Rakjat dan SIM kerap pergi keluar sendiri atau tergabung dalam kelompok-kelompok kecil dan mendapatkan diri mereka di ladang-ladang, di pinggir kali, di kota, di salah satu sudut jalan atau di pasar. Kerap juga mereka melakukan perjalanan ke pantai-pantai yang jauh atau daerah bergunung yang jauh dari kota untuk menangkap senyatanya kehidupan Rakyat.
Dari usaha itu kemudian kita mengetahui siapa “Rakyat” menurut Soedjojono dan Hendra, misalnya. Bagi Soedjojono yang berpandangan marxis, rakyat adalah kelompok sosial kelas bawah yang tertindas, seperti tergambar dalam lukisan berjudul Potret seorang Tetangga, Mengungsi, dan Sekko. Dengan realisme yang menjadi jiwa di lukisan-lukisan itu, Soedjojono menandaskan bahwa ia bisa menggambarkan dengan jelas “realitet nasi” yang dimengerti oleh rakyat yang oleh generasi baru Lekra di era tahun 1960-an, realisme sosial Soedjojono itu dinaikkan statusnya menjadi realisme revolusioner dan progresif. (Burhan, 2002)
Sementara bagi Hendra, rakyat adalah wanita-wanita yang memundaki muatan berat yang diikatkan pada punggung-punggung mereka yang membongkok, penjaja makanan di pinggir jalan serta para pelanggan mereka, pada wanita dan kanak-kanak. Para wanita yang dibebani yang berjalan dengan susah payah sepanjang jalan-jalan Jawa Tengah ke dan dari pasar telah menjadi lambang yang ada di mana-mana dari kemelaratan dan kemerosotan pada banyak lukisan Pelukis Rakjat. (Holt, 2000)
Dari deretan fakta itu, bukan suatu keheranan bila perupa-perupa macam Soedjojono, Hendra Gunawan, Affandi, hingga Basuki Resobowo berada dalam satu ayunan politik praktis dan berada di pusaran pemilu 1955. Keterlibatan penuh itu menandaskan bahwa dalam sejarah seni rupa kita, seniman dan politik bukanlah air dan minyak yang saling bertolakan. Setidaknya, partai macam PKI adalah partai yang paling yakin bahwa kehadiran seniman dalam politik menyegarkan masa depan politik yang tak melulu berbicara kekuasaan dengan segala negosiasi pragmatisnya. Inilah satu-satunya partai yang menempatkan budayawan dan perupa paling banyak dalam susunan sebagai calon legislatornya ketimbang partai-partai lain. Bahkan dibandingkan partai yang selalu mendaku diri sebagai partai intelektuil macam PSI yang dipimpin Sjahrir.
Belajar Nakal (Lagi): Keluar dari Ketertiban “Politik Keluarga”
Rupanya, usia “kemenangan” seni yang terlibat itu hanya bertahan satu dekade jika kita menghitung tonggaknya dari Pemilu 1955. Sepanjang 1955 hingga 1965 kejayaan seni sebagai ujung tombak propaganda politik dengan barisan panjang jargon yang diciptakan untuk mengomunikasikannya terjungkat dalam sebuah katasrofa yang mengerikan.
Gestapu, Gestok, atau apa pun sebutan malam jahanam 1 Oktober 1965 itu bukan saja menjadi tapal kejatuhan Sukarno, kehancuran PKI, dan para pemanggul ideologi kiri revolusioner, tapi juga mengubur mazhab “seni kerakyatan”. Seni propaganda yang sifatnya kolektif selama satu dekade menguasai wacana perupaan berganti wajah dengan seni propaganda yang lain. Sebut saja “seni individuil” dengan stabilitas pembangunan menjadi pengikatnya. Berkesenian boleh, tapi tak diperkenankan menyerempet ke dalam politik praktis dan mengusik stabilitas pembangunan.
Proyek-proyek pembangunan patung monumental yang sudah berlangsung di era Sukarno tetap dilanjutkan, namun mengikuti tatanan wacana baru; pemurnian Pancasila yang dijaga tentara. Patung tentara dibikin. Bukan saja patung Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya dibangun dengan gagah, semangat yang sama juga disebarluaskan di semua pelosok desa di seluruh Indonesia. Artefak keseragaman seni propaganda ala Garuda Pancasila ini masih bisa kita telisik dari pencarian Nanang R Hidayat di Museum Garuda, Yogyakarta (Hidayat, 2008). Si Tuan Besar yang tergambar dalam novel George Orwell 1984 bersembunyi di belakang kepakan sayap terbuka garuda untuk mengawasi seluruh keluarga di Indonesia. Keluarga? Ya, sasaran utamanya adalah kontrol pada keluarga. Maka dari itu, gapura “Garuda” di 80 ribu kampung sejak era 80-an selalu bersanding dengan “prasasti” 10 Program PKK dan patung KB (Shiraishi, 1997; Suryakusuma, 2013). Sementara itu sekitar 2 juta pegawai negeri dan aparatus birokrasi sejak 4 Juli 1978 diwajibkan ikut penataran hasil Sidang Umum MPR 1978 menyangkut Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) serta Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).
Situasi politik seperti itu yang menyuburkan lagi berkembangnya seni abstrak yang pernah hilang sebelum katasrofa berdarah 1965 meletus. Situasi semacam itu pula yang melahirkan “fenomena baru” kelahiran museum atau ruang seni yang bersandar pada individu seperti Museum Affandi.
Tepat di situasi yang “tenang”, “stabil”, dan “keluarga” sudah “dilindungi” ini pula lahir letupan-letupan kecil dalam kelambu tidur seni rupa Indonesia. Sebut saja Gerakan Seni Rupa Baru tahun 1974 yang dikenal juga dengan “Desember Hitam” di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Isu pameran yang diinisiasi mahasiswa-mahasiswa dari Sekolah Tinggi Seni Rupa ASRI Yogyakarta, Sekolah Tinggi Seni Indonesia ITB, dan LPKJ Jakarta itu awalnya merupakan respons keras dari penjurian “lomba” seni lukis yang “itu-itu saja” dan “biasa-biasa saja”. Isu “Desember Hitam” menjadi besar lantaran yang menampik seni eksperimental adalah mereka yang memegang kekuasaan kesenian dan yang punya hak memegang kendali. Harapan pernyataan “Desember Hitam”, sebagaimana termaktub dalam lima butir, adalah diberi ruang bagi munculnya kreativitas-kreativitas baru. Sebab mereka melihat bahwa yang menghambat perkembangan seni lukis Indonesia selama ini adalah “konsep-konsep usang, yang masih dianut establishment, pengusaha-pengusaha seni budaya dan seniman-seniman yang sudah mapan.” Karena itu “Desember Hitam” datang ingin menegur dengan mempurnawirawankan kaum establish seni rupa. (Supangkat, 1979)
Tiga tahun berselang, apa yang terjadi di Jakarta itu merembet ke Yogyakarta; kota yang pernah jadi ruang penangkaran “seni yang terlibat” dan “seni bertendens” yang terkubur tahun 1965. Pameran Pipa pada 1 Spetember 1977 adalah nota protes telanjang terhadap prinsip kesenian dalam pola yang mapan. Mereka menamakannya “pameran proses” karena yang dipamerkan serba tak siap. Ke-17 mahasiswa ASRI yang terlibat merasa bosan dengan bentuk yang sudah siap.
Kita tahu bahwa pada periode ini pencarian bentuk-bentuk seni rupa yang dianggap secara paling tepat mewakili representasi indentitas keindonesiaan secara budaya maupun politik sudah demikian “stabil”, “teratur”, “tertata”. Gaung perdebatan di masa sebelumnya yang mempertanyakan apakah “seni lukis Indonesia ada”, segera diikuti oleh pencarian keras kepala para pelukis yang ingin menempatkan corak tertentu dalam seni lukis di Indonesia sebagai salah satu gaya dan corak visual utama dan gaya seni lukis dekoratiflah yang cukup subur berkembang di Yogyakarta. Representasi gaya ini bahkan berhasil memunculkan langgam khas yang dianggap sebagai salah satu puncaknya, populer dengan istilah “dekora magis”. Pengkanonan seni lukis di lingkungan akademis inilah yang telah memicu munculnya semangat pembangkangan kelompok “Pipa”. (Wiyanto, 1979)
Memasuki tahun 1980-an atau masa konsolidasi kekuasaan sedang mengalami massifikasi dengan penyeragaman ideologi negara, letupan-letupan seni rupa hanya bekerja di ranah melakukan kritik dalam lingkup seni rupa itu sendiri. Perayaan seni dan politik berlangsung secara sporadis di luar kampus; namun lebih dominan bergerak dalam lingkup kampus. Efek menihilkan politik dalam kampus lewat program agung “NKK/BKK” tahun 1978 sampai di titik ini sukses. Pembangkangan-pembangkangan ekspresi berkesenian, biarpun muncul, sedapat mungkin dilokalisasi dalam kampus. Jika pun sampai keluar, biarlah Angkatan Darat yang “mengurusnya”.
Moelyono yang merupakan “alumni” dari Pipa ’77 dan ’79 mencoba melebarkan eksperimen berkeseniannya ke luar kampus dengan membawa bendera “seni rupa penyadaran”. Ia mencoba sekuat yang bisa dilakukan untuk menyatakan bahwa “seni yang terlibat” adalah menyatunya seniman dan masyarakat dalam sebuah kerja bersama. Apa yang dilakukan Moelyono sedikit demi sedikit mengeluarkan seni rupa dari dinding kampus ke lingkup pedesaan. Walau atas nama kerja individu dan bukan kolektif, sikap berkesenian Moelyono itu bisa kita catat sebagai sebuah pernyataan penting bahwa mesti berani mengatakan “tidak” pada kehidupan berkesenian yang terpingit dan dijepit kekuasaan “keluarga baik-baik”.
Dalam konteks hampir sama dengan kemunculan GSRB ’74 pula kita memosisikan parade protes Binal Jogja ’94. Peristiwa seni yang dikelola antara lain Dadang Christanto dengan salah satu bintangnya paling bersinar Heri Dono, merupakan kritik keras ekspresi seni dua dimensi yang “direstui” dalam acara dua tahunan peristiwa seni rupa di Yogyakarta. Praktik seni instalasi yang masih “dalam proses” saat pameran Pipa ’77 dan ’79 termatangkan dengan hadirnya perayaan protes Binal ’94 yang sekaligus mengaburkan medium seni konvensional dan menjadi jalan masuk bagi lahirnya medium baru jelang alaf baru tiba.
Kembalinya Seni Pamflet: Dua Jalan di Tembok Kota
Seni rupa kerakyatan memang tak pernah kehabisan peminat di Yogyakarta. Bukan saja karena di kota ini pertama kali genre seni ini diproklamasikan dan diekspresikan sedemikian keras kepalanya S. Soedjojono dkk sejak medio dasawarsa 1930-an, melainkan juga imajinasi tentang seni berbasis publik diujicobakan berkali-kali dengan beragam artikulasinya di masa ketika seni kontemporer menguasai jagat berkesenian Yogyakarta. Mulai dari “kiri-tengah” seperti yang dipraksiskan Samuel Indratma dengan proyek Jogja Mural Forum (JMF) yang mengusungi jargon politik dengan riang gembira: “revolusi kulonuwun” hingga “kiri-dalam/progresif” seperti yang dipraksiskan Lembaga Budaya Kerakyatan Taring Padi dengan tangan terkepal meninju langit yang bersemangat “revolusi belum selesai” sebagaimana dipraktikkan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) puluhan tahun sebelumnya.
Imaji tentang posisi gerak seni Taring Padi yang bersandar pada kerja Lekra itu sudah tercium sejak pertama kali dideklarasikan pada 2 Desember 1998 di LBH Yogyakarta oleh Yustoni Volunteero dkk, sejak dalam proses menamai manifesto politik berkeseniannya dengan “Mukadimah” dan judul selebaran propaganda tentang siapa musuh yang harus ditonjok: “Lima Iblis Budaya”.
Dalam genealogi sejarah seni rupa kritis pasca Orde Baru, tak bisa dibantah bahwa Taring Padi adalah “pewaris sah” imajinasi seni rupa seniman Lembaga seni Rupa (Lesrupa/Lekra) yang terakhir kalinya mengadakan sidang pleno pada Juli 1965 dan semua program-program seni kerakyatannya sungsang oleh prahara “Gestok”.
Taring Padi dalam posisi ini tak boleh dicibir sebagai “cah nakal” ISI lantaran kemunculan mereka dengan posisi tegas dan imajinasi sejarah yang juga tak kalah tegasnya. Heidi Arbuckle (2010) dalam kajian antropologisnya dengan sangat baik membantu kita melihat detail-detail sikap berkesenian Taring Padi pada tiga tahun awal berdirinya. Bahkan hingga pada amatan kehidupan sehari-hari aktivisnya: “di bekas kampus ASRI, Gampingan, Yogyakarta… mereka berbagi tugas-tugas harian seperti memasak, mencuci, dan merawat kebun sayur swadaya”.
Menurut Doktor lulusan Universitas Melbourne Australia ini dalam pengorganisasian seninya, Taring Padi tak sementereng Lekra, dan bahkan jika dibandingkan dengan Sanggar Bumi Tarung sekalipun. Ini disebabkan karena Taring Padi sama sekali tak memiliki akses atau patron negara dan partai seperti yang dimiliki pendahulunya. Untuk mempraktikkan produksi seni ber”komitmen sosial”, Taring Padi hanya mengandalkan jejaring budaya kiri-progresif yang terpecah-pecah.
Kepada jaringan nirnegara dan partai politik itulah Taring Padi mendesakkan praksis berkeseniannya yang berangkat pada “kesadaran populer” dan pentingnya “berpihak kepada rakyat” (bandingkan dengan kata “rakyat” yang dipakai Taring Padi, sementara Apotik Komik dan JMF yang justru lebih “nyaman dan baik-baik saja” memakai kata “publik”).
Taring Padi sangat sadar bahwa “seni untuk rakyat” adalah gabungan yang konsisten antara karya yang politis dan tindakan yang politis. Yang diutamakan dari teori progresif anutan Taring Padi ini adalah implikasi politik, bukan implikasi estetiknya.
Lantaran itu kita menemukan teknik memproduksi karya Taring Padi sebangun dengan sikap-sikap itu. Selain mengabaikan penonjolan individu, kebanyakan karya rupa Taring Padi berupa baliho atau spanduk, poster cukil-kayu, figur-figur wayang, dan selebaran populer Terompet Rakyat yang terbit berkesinambungan di mana kerja-kerja itu lebih menonjolkan kerja kolektivitas dan propaganda yang “berimplikasi politik”.
Turba atau “turun ke bawah” kemudian menjadi kata kunci berkarya. Turba yang ditafsir Taring Padi adalah menggelar aksi-aksi bersama. Bukan hanya bersama organisasi mahasiswa dalam kasus pembakaran patung Soeharto 1998 dan aksi keranda kematian bagi Soeharto-Habibie-Wiranto 1999; berbaur dengan kelompok musik marjinal dalam aksi “Proklamasi Kemanusiaan”, bareng LSM internasional dalam Konferensi Asia Pasifik; melainkan juga menggelar Festival Memedi Sawah di areal persawahan petani Delanggu dan aksi protes penggunaan pestisida petani Magelang dan Boyolali atau yang paling mutakhir bergabung dengan rakyat Gunung Kidul memprotes penambangan pasir besi.
Dalam aksi-aksi itu, poster dan baliho Taring Padi menjadi demikian menonjol. Tak hanya besarnya ukuran, massalnya produksi, tapi juga kata-kata sarkas yang meninju. Bahkan, salah satu karya para perupa Taring Padi yang saya kira bisa menjadi ikon seni rupa adalah baliho berukuran raksasa petani berdiri berjajar-jajar yang menjadi latar pertemuan Konferensi Asia Pasifik pada 1999. Usai pagelaran kelompok anti imperialisme dari pelbagai ornop itu, karya ini dipotong-potong dan dibagikan kepada peserta asing yang mengikuti konferensi itu. Ritus upacara “pelenyapan karya politis untuk tindakan politis” atas karya itu sikap luar biasa, dan bahkan tak setara jika dibandingkan dengan perupa Tisna Sanjaya misalnya yang pada penutupan tahun 2009 membakar karyanya sendiri untuk dilarung di pantai Klungkung Bali.
Memang, ada pergeseran prinsip kemudian saat Taring Padi mengarungi politik liberal sejak Bapak Soeharto tumbang. Mulanya, Taring Padi meneguhkan pendirian bahwa mereka menentang secara muka-muka dengan galeri-galeri komersil seperti Cemeti Art House dan kelompok Apotik Komik. Taring Padi juga berpendirian bahwa karya-karya “asli” mereka seperti baliho dan wayang sama sekali tak boleh dijual. Yang boleh dijual—itu pun secara loakan dan bukan distro mapan dan resik—hanyalah karya yang mudah direproduksi seperti cukil berbentuk poster, stiker, pin, kaos, dan semua-mua yang bersifat cinderamata.
Tapi politik liberalisme yang membuai membuat Taring Padi melonggarkan prinsip-prinsip yang dibuatnya. Para pendirinya (sudah) boleh berpameran di galeri-galeri yang dikutuknya. Juga (sudah) si setan imperialisme yang berzirah Ford Foundation boleh menjadi sponsor buku sejarah lengkap yang memuat perjalanan panjang berkesenian Taring Padi.
Pada saat posisi Taring Padi bergeser, posisi seni yang dipundaki Jogja Mural Forum dan Apotik Komik mendapat tempat di dinding-dinding kota. Makin membesarnya pewacanaan street art memiliki persinggungan dengan semangat yang dibangun JMF; bukan saja merebut ruang publik (baca: tembok kota), namun juga membangun simpul-simpul komunitas yang memiliki komitmen yang sama lewat anugerah media sosial pemberian abad 21.
Sebagaimana di era liberalisme pertama (50-an), sejak 2014 hubungan seni(man) dan politik melentur dan bahkan berada dalam satu meja jamuan makan dengan tertawa sebebasnya. Hubungannya tak lagi semerunduk di era ketika politik “keluarga baik-baik berkuasa” atau menjaga “jarak” sebelum lonceng perhelatan Pemilu 2014 dibunyikan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Penulis: Muhidin M Dahlan (Peneliti BJXIII Hacking Conflict!)
Gambar ilustrasi: “Poster Boeng”. Sumber: Affandi (1907-1990), Maestro Seni Lukis Indonesia.