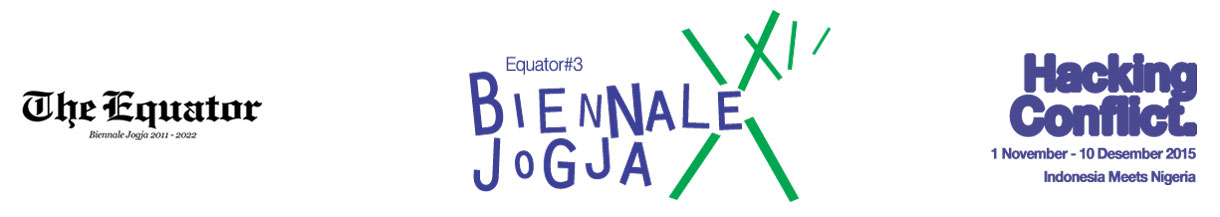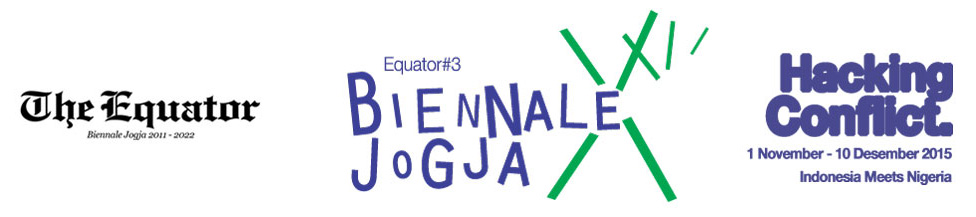Selama Perang Asia Pasifik (1937-1945) pemerintah Jepang menjalankan beragam taktik guna memobilisasi manusia dan sumber daya material bagi kampanye militer dalam skala yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Jepang. Organisasi-organisasi kedaerahan, asosiasi profesi, dan unit-unit baru yang memungkinkan mobilisasi bantuan dan keterlibatan warga dalam perang didirikan. Seni juga dilibatkan dalam proyek ini. Organisasi-organisasi seni di Jepang, yang merupakan alat penting dalam memenuhi kepentingan seniman dan menghidupkan dunia seni, kini menjadi alat penting dalam melayani proyek negara, dan pada saat yang sama organisasi-organisasi seni baru yang bersifat patriotik juga tumbuh menjawab keadaan darurat negara yang diciptakan oleh militer.
Situasi yang sama juga terjadi di negara-negara yang dikuasi Jepang. Di Indonesia, kedatangan Jepang berlangsung relatif damai dan disambut orang Indonesia dengan suka cita, karena ada anggapan umum bahwa Jepang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda.
Segera setelah berhasil menguasai Sumatera dan Jawa pada bulan Februari dan Maret 1942, Jepang meluncurkan proyek propagandanya yang pertama (Tiga A: Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia) dan membentuk Departemen Propaganda (Sendenbu). Organisasi-organisasi propaganda lebih khusus yang bergerak melalui radio, film, surat kabar, dan seni menyusul dibentuk, beberapa di antaranya adalah Jawa Hōsō Kanrikoru (Biro Pengawas Siaran Jawa), Jawa Shinbunkai (Perusahaan Surat Kabar Jawa), Nihon Eigasha Nichi’ei (Perusahaan Film Jepang), dan Jawa Engeki Kyōkai (Perserikatan Usaha Sandiwara Jawa). Dua organisasi lain dengan skala mobilisasi yang lebih luas dibentuk pada 1943: PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) dan Keimin Bunka Shidōsho (Institut Pemandu Pendidikan dan Budaya Rakyat, atau disebut juga Pusat Kebudayaan).
Para ahli, penulis, dan seniman terkemuka Indonesia terlibat di dalam organisasi-organisasi tersebut, misalnya Affandi, Sudjojono, Agus Djajasoentara, Oto Djajasoeminta, Barli, Hendra Gunawan, Emiria Soenasa, Basuki Abdullah, Oetojo, dan Armijn Pane (dokumen Jawa Gunseikanbu [Departemen Pemerintahan Militer Jepang di Jawa] menyebut 26 nama seniman terkemuka yang terlibat dalam proyek perang Jepang di Jawa). Mereka ini bekerja bersama lebih dari 100 orang ahli dan profesional terkemuka dari Jepang yang dikirim untuk tinggal dan bekerja di Indonesia, misalnyaTakashi Kono (desainer grafis), Rintaro Takeda (sastrawan), Seizen Minami (pelukis), Saseo Ono (karikaturis), Sōichi Ōya (penulis, wartawan), Eitarō Hinatsu (sutradara film), Miyamoto Saburo (pelukis), dan Ryōhei Koiso (pelukis).
Ada beberapa alasan mengapa seniman-seniman terkemuka ini terlibat dalam proyek propaganda perang Jepang. Di Indonesia, keberhasilan Jepang bernegosiasi dengan Sukarno, dan kemudian melibatkan Sukarno serta tokoh politik kunci Indonesia lainnya dalam organisasi-organisasi propaganda Jepang, tampaknya merupakan salah satu alasan bergabungnya para seniman dalam proyek perang Jepang.
Paksaan dan ancaman bukannya sama sekali tidak digunakan. Contohnya, Di Jepang dua tokoh surealis Jepang Takiguchi Shūzō and Fukuzawa Ichirō ditangkap pemerintah pada 1941 dengan tuduhan terlibat komunisme. Tekanan terhadap organisasi yang mereka pimpin, Bijutsu Bunka Kyōkai (Perkumpulan Seni Rupa dan Budaya), baru mereda ketika para anggotanya menyatakan akan mengubah panduan artistik mereka dan akan bertindak lebih aktif dalam program-program kerjasama dengan pemerintah.
Studi Sakouchi Yūji tentang material seni pada masa perang yang dimuat di jurnal Kindai gasetsu (No. 13, Februari 2004) juga memberikan penjelasan baru soal keterlibatan para seniman pada proyek perang. Masa paling berat bagi para seniman di Jepang adalah pada 1941, yaitu ketika material seni sedemikian terbatas, disebabkan oleh sanksi ekonomi atas Jepang dijatuhkan Amerika Serikat dan sekutunya. Sejak 1941, para pelukis cat minyak atau yōga (lukisan gaya Barat) hanya bisa mendapatkan kanvas dan cat minyak berkualitas rendah, sementara pelukis gaya tradisional Jepang atau Nihonga juga menderita lantaran keterbatasan pasokan kain sutra, emas dan pigmen mineral. Dalam situasi tidak menentu ini, keterlibatan dalam proyek perang menjadi salah satu alat paling menjanjikan bagi para seniman untuk bisa mendapatkan meterial seni. Dalam upayanya mendapatkan pasokan material seni dari pemerintah, para seniman terlibat dalam tawar-menawar kolektif, menunjukkan dukungan mereka pada perang melalui penyelenggaraan pameran-pameran patriotis dan menyumbangkan karya seni kepada intitusi-institusi militer.
Di Indonesia, Jepang menyediakan cat minyak, kanvas, studio, dan bahkan model secara cuma-cuma bagi seniman Indonesia yang bergabung dengan proyek Jepang. Kursus-kursus melukis bersama guru-guru Jepang dan pelukis terkemuka Indonesia diselenggarakan di berbagai kota. Begitu juga pameran, lomba, dan pemberian penghargaan. Semua keistimewaan dan kemewahan itu, yang selama masa pendudukan Belanda hanya bisa dinikmati oleh seniman dan kelompok teratas dalam masyarakat, kini bisa diperoleh cuma-cuma. Tidak mengherankan bahwa selama periode singkat pendudukan Jepang, terjadi ledakan jumlah seniman di Indonesia.
Dari para seniman Jepang, seniman Indonesia juga mempelajari banyak gaya dan teknik baru dalam membuat karya seni. Saseo Ono umpamanya, memperkenalkan mural kepada seniman-seniman Indonesia. Pada bulan Maret 1942, tiga hari setelah mendarat di Jawa, dia membuat mural “Bersatulah Bangsa Asia” di Serang, Banten. Saseo juga mendorong seniman-seniman Indonesia untuk belajar membuat sketsa cepat di luar ruangan, memperkenalkan teknik animasi stop motion (misalnya dalam film berita tentang propaganda menabung, 1943) dan juga teknik pembuatan film boneka (Pak Kromo, 1943). Contoh lainnya adalah Takashi Kono. Selain menjadi pengarah desain untuk sejumlah media massa di Indonesia, dia juga memperkenalkan teknik kolase dan montase pada desain dan fotografi kepada seniman-seniman Indonesia.
Di luar alasan-alasan itu, cukup banyak pula profesional dan seniman yang bergabung dengan proyek perang Jepang secara sukarela, yaitu kelompok yang percaya kepada cita-cita perang: menyatukan dan memodernkan Asia adalah tugas mulia Jepang yang harus dicapai. Tidak jarang mereka membiayai sendiri perjalanan mereka ke negara-negara dudukan Jepang, dan memilih menetap bahkan ketika Jepang telah menyerah. Contohnya Mabuchi Itsuo dan Eitarō Hinatsu.
Mabuchi adalah salah satu figur penting dalam propaganda perang Jepang. Dia anggota pasukan intelejen Jepang di China. Sejak 1937 dia mengendalikan propaganda sipil dan militer Jepang di China, dan sejak 1938 dia juga bekerja sebagai penulis dan wartawan. Pada akhir perang dia dikirim ke Indonesia untuk membantu merancang aktivitas propaganda. Ketika Jepang menyerah, Mabuchi memilih menetap di Indonesia dan bekerja bersama tentara Indonesia dalam perang melawan pasukan Sekutu. Eitarō Hinatsu juga memilih menetap di Indonesia setelah Jepang menyerah. Dia tetap berkarya sebagai sutradara film dan drama, dan menggunakan nama Indonesia Dr. Huyung. Dia menetap di Yogyakarta, mendirikan Cine Drama Institut pada 1948 dan Stichting Hiburan Mataram pada 1949.
Beragamnya alasan keterlibatan seniman pada proyek perang menunjukkan kerumitan hubungan seni dan propaganda, berbeda dengan pemahaman Barat yang cenderung menyederhanakan, melihat negatif hubungan propaganda dan seni, dan cenderung melihatnya sebagai mesin yang bergerak satu arah: yang pertama mengendalikan yang kedua, propaganda perang menguasai seni sepenuhnya.
Pemahaman negatif atas hubungan seni dan propaganda yang sebenarnya baru terbentuk sejak dimulainya Perang Dunia II itu—yang terutama dibentuk oleh militer Amerika Serikat—gagal melihat kerumitan, tegangan, dan pasang-surut hubungan seni dan propaganda Jepang. Meskipun militer Amerika Serikat menyadari kemampuan luar biasa Jepang dalam memobilisasi warganya dan warga negara-negara yang didudukinya (khususnya mereka mengagumi sedikitnya penggunaan teror dan paksaan), tetapi mereka tidak berhasil memahami jiwa dan cara kerja propaganda Jepang. Kajian-kajian Amerika atas propaganda Jepang pada awal 1940-an terpusat pada stereotip sifat masyarakat Jepang dan kebudayaan Timur sebagai masyarakat bermental budak yang sepenuhnya mengabdikan hidupnya kepada raja. Dalam konteks sejarah Jepang, besarnya pengaruh Kekaisaran Shōwa (dimulai sejak 1926) memang perlu diperhatikan. Begitu juga besarnya pengaruh para pemimpin nasionalis pada 1940-an di Indonesia. Akan tetapi hal itu tidak perlu dibesar-besarkan dan mesti diletakkan pada konteksnya. Propaganda Jepang bisa bekerja secara efektif bukan saja karena ia bisa menyampaikan pesan yang tepat kepada masyarakat, melainkan juga seringkali propaganda itu berasal dari masyarakat (dalam teori propaganda Jepang, sifat ini disebut minshin haaku, propaganda yang bisa merengkuh hati dan jiwa masyarakat).
Di Jepang, pada masa perang, proposal dan saran untuk meningkatkan mutu produk propaganda datang dari segala penjuru negeri, dan dari segala jenis organisasi. Agen-agen periklanan dan rumah produksi swasta menghujani pemerintah dan militer dengan proposal untuk membantu mereka membuat propaganda yang lebih baik dan menaikkan tingkat mobilisasi massa. Tanpa mengesampingkan adanya gerakan-gerakan bawah tanah perlawanan terhadap Jepang di Indonesia, inisiatif propaganda yang berasal dari masyarakat juga merebak di seluruh penjuru negeri.
Seni dan propaganda pada masa pendudukan Jepang di Indonesia bisa dikatakan berada dalam hubungan yang saling membutuhkan. Jepang melihat para seniman sebagai sarana untuk memobilisasi dukungan rakyat Indonesia bagi tujuan perangnya, sehingga kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan mereka harus dibuat agar mereka tetap dalam barisan pendukung. Sementara bagi para seniman Indonesia, organisasi-organisasi propaganda Jepang merupakan sarana untuk menyebarkan dan mengintensifkan ide-ide nasionalis dan kemerdekaan kepada masyarakat, mendapatkan akses material, fasilitas, dan pengatahuan seni baru, serta menyadarkan mereka pada kekuatan seni dan kolektivitas dalam dunia politik—suatu kesadaran yang kelak menjadi lakon utama dalam babak sejarah seni di Indonesia selama dua dasawarsa berikutnya.
Penulis: Antariksa, peneliti pada KUNCI Cultural Studies Center, Yogyakarta. Karya terbarunya Art Collectivism in the Japanese-Occupied Indonesia akan terbit tahun depan (Fukuoka: Kyushu University Press, musim panas 2016).
Gambar ilustrasi: Saburo Miyamoto, Surprise Attack of Naval Paratroops at Manado, 1943, cat minyak di atas kanvas, 189 x 297 cm (National Museum of Modern Art, Tokyo).