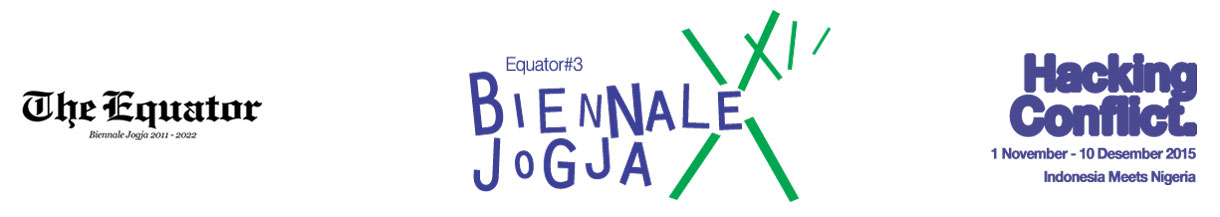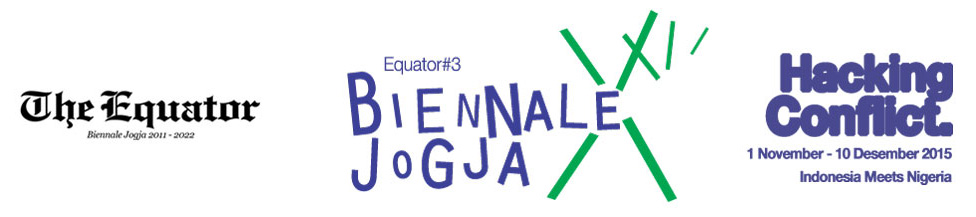Saat ini, ratusan biennale yang tersebar di seluruh dunia menunjukkan bahwa format berpameran ini telah menjadi suatu aspirasi global, melampaui imajinasi serta pemahaman awal mengenai potensi dan jangkauannya. Di bawah tekanan globalisasi, biennale saat ini menghadapi suatu paradoks klasik: ketika ada dalam jumlah yang begitu banyak, bagaimana suatu biennale membedakan dirinya dari kebanyakan biennale yang lain? Bagaimana ia mengelak dari resiko keserba-samaan, dengan menawarkan sesuatu yang tak terduga meski masih tetap menggunakan format yang sama? Bagaimana ia tidak menjadi ‘unik, seperti yang lain’?
Bagi para pesimis, ancaman penyeragaman yang dibawa oleh globalisasi adalah alasan utama untuk berpendapat bahwa format biennale telah menjadi kuno dan tidak relevan. Terlebih lagi, saat ini visi dan ambisi yang melatar-belakangi penyelenggaraan sebuah biennale bisa dibilang tidak terlalu jauh berbeda dari aktifitas kultural lain, seperti kompetisi olahraga misalnya, atau pertukaran diplomatik: sebagai contoh, adanya keterlibatan dari partisipan internasional demi penyeimbangan status geopolitik, atau penggabungan sentimen ‘kebanggaan lokal’ dengan taktik branding negara untuk menggaet perhatian investor demi mengembangkan perekonomian berbasis turisme. Menimbang perspektif ini, tak heran jika pertanyaan tentang harus-tidaknya kita ‘berbiennale’ sekarang ini menjadi sumber perdebatan yang hangat.
Di sisi lain, para pembela biennale berpendapat bahwa format ini tetap relevan jika dianggap sebagai sebuah situs eksperimentasi yang berpotensi melampaui kekakuan tradisi dan kaidah berpameran yang dimiliki oleh museum atau galeri. Pendapat optimis seperti ini, tentunya, datang dari latar belakang Eurosentris dan tidak sepenuhnya tepat untuk kenyataan dunia kesenian di Indonesia, dimana kita tidak memiliki tradisi atau peraturan baku dalam praktik berpameran baik di museum maupun di galeri. Meski demikian, semangat biennale yang dilandasi spekulasi dalam merespon konteks sosio-politik dan kultural yang terus bergeser dan penjalinan jaringan dalam skala mikro dan makro, tetap menjadi daya tarik untuk biennale-biennale yang datang dari wilayah yang tadinya dianggap sebagai ‘pinggir’ pusat kesenian dunia. Jika idealisme kesenian ini terdengar utopis, contoh konkrit atas bagaimana suatu festival seni dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat luas terlihat pada perubahan infrastruktur lokal yang dapat disebabkan oleh penyelenggaraan pameran berulang, seperti, misalnya, yang terjadi dengan kasus Manifesta, Trienal Echigo-Tsumari, dan Trienal Setouchi.
Terlepas dari kritik tajam dan skeptisisme populer terhadapnya, biennale sebagai suatu format berpameran terus berkembang secara luas dan membuat pertanyaan ‘apakah kita harus menyelenggarakan biennale’ tampak seakan tak berdaya. Jika – untuk bermacam alasan – format biennale tetap menjadi pilihan populer untuk kebanyakan masyarakat seni dunia, maka pertanyaan yang lebih tepat untuk diajukan sebenarnya tidak lagi menyangkut harus atau tidaknya format biennale tetap digunakan, tapi ‘bagaimana’ kita menggunakannya untuk mengajukan suatu hipotesa tentang realita kontemporer tanpa mengulang-ulang ‘rumus’ penyelenggaraan biennale, dan menjadikan acara kesenian ini suatu hal yang homogen.
Elena Filipovic membaca gejala keseragaman biennale sebagai suatu ‘global white cube’, dimana biennale-biennale yang ada terus mereplika strategi permuseuman modern di Barat dalam hal berpameran.[1] Ini bermasalah, mengingat betapa seringnya praktik biennale kontemporer menyuarakan perbedaan mereka dari ideologi ‘white cube’ museum yang dianggap tidak lagi cocok untuk mengartikulasikan ide-ide mendesak tentang kekinian. ‘Kubus putih’ itu dianggap sebagai perwakilan sempurna atas modernisme Barat: tidak adanya jendela sehingga kehidupan yang sedang berlangsung di luar tidak masuk–dan mengganggu–suasana di dalam ruangan; cahaya buatan yang dapat diatur sedemikan rupa sehingga selalu terlihat seperti siang hari; suara yang diredam untuk mengamplifikasi suasana kontemplatif. Di dalam museum, pengunjung ditempatkan dalam dunia yang berbeda dari dunia ‘sebenarnya’ di luar sana, dimana mereka dapat melambung ke keadaan transendental yang berjarak dari lingkungan keseharian yang konon banal, tidak inspiratif, tidak artistik. Dalam ruang ini, semua fitur dan elemen dari karya menjadi menonjol, tanpa harus berlomba dengan kebisingan dunia luar untuk menarik perhatian pengunjung.
Hari ini, ‘white cube’ telah menjadi metafora untuk suatu pendekatan yang khas terhadap kesenian dan bagaimana ia harus dipresentasikan. Dibangun agar netral, tidak bersuara dan tidak terlihat, ruang ini justru menjadi semakin dominan. Seperti banyak komentator lain, Filipovic menulis bahwa praktik biennale yang ada sekarang berangkat dari hasrat yang sama untuk melawan tradisi ‘white cube’. Namun, menurut observasi Filipovic, kebanyakan biennale yang ada justru mengulang hal-hal yang ingin mereka tentang, baik dari segi penggunaan ruang yang terbelenggu oleh kisi-kisi kaku, hingga hilangnya kekhasan pada judul dan tema yang diberikan, yang hanya memberi gambaran universal dan generik tentang dunia saat ini. Mencari jalan keluar dari problema ini menjadi semakin sulit karena biennale telah menjadi institusi kesenian dengan budayanya sendiri, membentuk anggapan umum tentang bagaimana suatu biennale harus terlihat: kumpulan karya-karya spektakuler yang dipadatkan di satu ruang, dengan partisi-partisi putih di antara karya-karya itu.[2]
Jika Filipovic meletakkan praktik biennale sekarang sebagai suatu hasrat untuk melawan ideologi ‘modernist white cube’, Caroline A. Jones berpendapat bahwa biennale yang kita miliki sekarang sebenarnya terlahir dari nafas yang diberikan oleh eksposisi internasional dan ‘festival dunia’ dari Eropa di abad 19 (contoh: pameran Crystal Palace di London di tahun 1851 dan terbentuknya Biennale Venesia di tahun 1895).[3] Persamaan antara model-model pameran ini dengan biennale di abad 20 dan 21 terlihat pada ambisi geopolitik, kedekatannya dengan turisme, serta pengaruh acara-acara kesenian ini pada infrastruktur lokal dan rute perdagangan seni internasional. Meski demikian, Jones tetap mengakui adanya pergeseran penting yang dibuat oleh biennale kontemporer dari model yang disahihkan oleh eksposisi internasional dan festival dunia Eropa yang terdahulu.
Bagaimanapun juga, ‘festival dunia’ berakar pada superioritas bangsa penjajah: adanya kelompok bangsa yang mampu melakukan ekspedisi ke daerah eksotis dan melihat artefak dari budaya ‘lain’ ini menurut kacamata mereka, dan memindahkan artefak tersebut dari konteks asli ke konteks artifisial untuk menghadirkan semacam tontonan yang alih-alih merayakan ragam kebudayaan di dunia. Praktik ini membuat bangsa yang bersangkutan terlihat unggul, dan kota dimana festival ini diselenggarakan semakin sarat gengsi karena terkesan ‘mendunia’. Karena perspektif kolonialisme ini, biennale yang didirikan oleh tempat-tempat di luar wilayah yang disebut ‘Barat’ terbilang tidak memiliki banyak persamaan dengan tradisi Biennale Venesia (BV) maupun ‘festival dunia’ tadi.
Ini menandakan bahwa secara historis, praktik biennale ‘pinggiran’ tidak sepenuhnya terjelaskan oleh tradisi tersebut. Mengikuti Ranjit Hoskote, Oliver Marchart menulis tentang ‘Biennials of Resistance’ – biennale atau festival seni besar yang menantang legitimasi tradisi Biennale Venesia mengenai status kesenian baik yang berasal dari Barat maupun Non-Barat – dimana Biennale Sao Paulo, Trienal India, Biennale Havana, Biennale Asia-Pacific, Biennale Gwangju dan Biennale Johannesburg (ketika masih ada) disebut sebagai contoh. Hoskote membayangkan kemunculan suatu tipe biennale yang baru, yang mencerminkan keresahan yang dimiliki daerah-daerah Selatan dunia (the global South), dan menunjukkan sebuah sejarah tentang biennale yang bertolak belakang dari tradisi dan tolok ukur yang ditetapkan oleh BV. Marchart menambahkan bahwa yang menjadikan kelompok biennale ini penting adalah bagaimana mereka melebur pusat kuasa BV untuk melegitimasi strategi yang digunakan oleh sebuah biennale sebagai suatu medium kesenian.[4]
Dari kelompok ini, Marchart meletakkan Biennale Havana yang ketiga di tahun 1989 (BH3) pada posisi tersendiri, terutama untuk terobosan model kuratorial biennale yang kemudian banyak ditiru oleh biennale-biennale selanjutnya. Ia berpendapat bahwa BH3 adalah biennale pertama yang meski dibuat oleh negara non-Barat dan melibatkan kesenian dari ‘Dunia Ketiga’, tidak membatasi kerangka kuratorialnya pada persoalan represi penjajahan. Ini menandakan bahwa selain bertolak belakang dari tradisi BV, biennale ini juga berbeda dari Biennale Sao Paulo yang menekankan ideologi pasca-kolonialsme. Strategi kuratorial penting lainnya adalah bagaimana Gerardo Mosquera, kurator biennale tersebut, tidak hanya mengundang seniman dari wilayah yang disebut ‘pinggir’, tapi juga seniman dari komunitas diaspora yang tinggal di daerah-daerah pusat dunia. Di sini, ada perluasan konsep mengenai ‘Dunia Ketiga’, dimana istilah ini memberikan gambaran yang lebih kompleks tentang sebuah dunia yang sedang dibentuk oleh proses migrasi dan mobilisasi global.
Kecerdasan politik dan sosio-kultural ini adalah, catat Marchart, hal yang tidak dimiliki oleh pameran lain pada masanya. BH3 mengupas modernisme sebagai suatu hal yang bersifat plural, dan menolak stereotip tentang kesenian dari wilayah ini yang berputar pada “kekaryaan tradisional dan estetik simbolik-relijius”.[5] Selain itu, BH3 juga berpengaruh besar karena membuka potensi-potensi baru tentang partisipasi, dimana acara tersebut adalah sebuah “organisme yang terdiri dari bermacam pameran, kegiatan, pertemuan, publikasi, program outreach”.[6] Langkah untuk mendematerialisasi pameran – dimana biennale tersebut tidak lagi berfungsi sebagai sebuah tontonan akbar, tapi sebuah upaya untuk menyelidiki suatu masalah khusus tentang kekinian dan mengajukan hipotesa mengenainya – menjadi model yang sering digunakan oleh biennale-biennale hingga saat ini. Dengan ini, Marchart menyimpulkan bahwa sejarah biennale yang menolak tradisi BV harus ditelusuri ke model yang ditawarkan oleh, antara lain, BH3.
Silsilah biennale yang kita kenal saat ini, yang penuh dengan cabang dan tidak bisa secara langsung dihubungkan kembali kepada tradisi pameran berulang di Eropa menjelang akhir abad 19, menunjukkan biennale sebagai suatu produk kultural yang terbentuk dari perubahan bermacam kondisi geo-politik dan sosio-ekonomik. Biennale, sebagai suatu produk kultural, sudah seharusnya menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi persoalan terselubung yang sedang dihadapi masyarakat sebagai suatu kelompok: ia harus lihai dalam membaca realita masa kini, sehingga dapat menyusup lebih dalam dari perspektif arus utama untuk mengenali apa yang sebelumnya tidak terlihat. Meski memiliki relevansi secara global, sebuah biennale tetap mengartikulasikan permasalahan yang secara khusus dialami suatu tempat di tingkat lokal, dan maka dari itu tidak bisa sekadar mengikuti angan-angan tentang suatu standar universal yang dianggap dapat melintasi ruang dan waktu.
Bagaimana menegosiasi ilusi tentang ‘standar universal’ tersebut? Tentunya tidak ada jawaban tunggal atas teka-teki ini, tapi semata menjelma lokasi-lokasi yang tidak umum digunakan sebagai ruang pamer, atau melibatkan karya-karya yang lebih bombastis dari biasanya, juga bukan cara yang sesungguhnya tepat. Melainkan, jika sebuah biennale tidak ingin hanya mengulang rumus ‘berbiennale’ yang telah sudah ada, yang dibutuhkan adalah ketulusan dalam mengusut hubungan yang rumit dan berbelit antara karya, audiens, dan situs, serta menyusun komposit ini menjadi suatu proposisi intelektual yang dapat disampaikan melalui kerangka kuratorial. Ini tidak hanya memaksa adanya kemitraan yang lebih intens antara kumpulan agen dalam dunia kesenian dengan agen-agen dalam praktik kebudayaan yang lebih luas. Terlebih dari itu, – dan terkait dengan paradigma ‘outcome-based’ yang sering digembar-gemborkan saat ini – ini menuntut adanya keberanian dalam mengambil resiko untuk membuahkan hasil yang tidak sepenuhnya pasti maupun komplit: sesuai dengan sifat proposisi yang ia ajukan mengenai realita yang dihadapinya. Pada akhirnya, meski ini tidak menjamin popularitas sebuah pameran, tapi setidaknya ada sebuah celah yang terbuka untuk memposisikan sebuah biennale sebagai kesempatan untuk berspekulasi dan tidak hanya mereplika ‘standar’ tertentu, sebagaimana yang dijanjikan oleh semangatnya.
Oleh: Mitha Budhyarto (dosen dan kurator)
Gambar ilustrasi diambil dari www.biennaleforu,.org
_____________
[1] Elena Filipovic, “The Global White Cube”, The Biennial Reader, Irina Filipovic et al (eds.), Bergen: Bergen Kunsthalle, 2010, hal. 322-345.
[2] Ibid.
[3] Caroline A. Jones, “Biennial Culture: A Longer History”, Filipovic, I., ibid, hal. 66-87.
[4] Oliver Marchart, “The Globalization of Art and the “Biennials of Resistance”: A History of Biennials from the Periphery”, CuMMA – Studies in Curating, Managing and Mediating Art, CuMMA Papers #7, https://cummastudies.files.wordpress.com/2013/08/cumma-papers-7.pdf (diakses 16 April 2015).
[5] Mosquera dikutip di Marchart, ibid.
[6] Ibid.