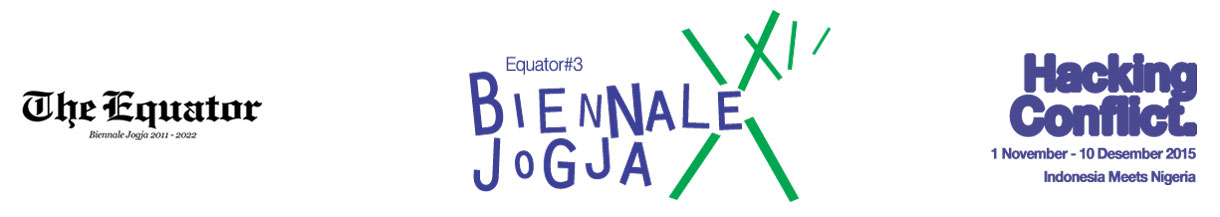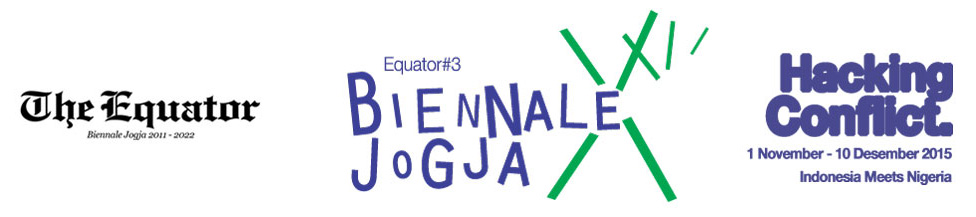“Kekacauan adalah teman sejati demokrasi” — William Blake.
Nukilan di atas saya ucapkan saat mempresentasikan rancangan kasar (draft) tema kuratorial saya untuk program Pameran Utama Biennale Jogja XIII di sebuah diskusi tertutup yang diselenggarakan oleh Yayasan Biennale Yogyakarta pada tanggal 23 Desember 2014. Nukilan tersebut saya lontarkan setelah memaparkan teori agonisme untuk memberikan gambaran sederhana atas rumusan tema yang masih berantakan. Beberapa saat setelah menukil kalimat itu, saya sadar telah keliru.
Meski begitu, saya tak buru-buru membetulkannya. Bagi orang yang mempelajari karya-karya William Blake secara mendalam, pasti tahu bahwa nukilan di atas keliru. Tulisan yang benar adalah “opposition is true friendship” atau oposisi adalah pertemanan yang sejati. Kesalahan ini terjadi karena tiga hal: saya lupa teks aslinya, penerjemahan yang keliru, dan grogi karena di tengah presentasi diburu oleh ibu direktur untuk segera masuk ke sistem kuratorial.
Meskipun nukilannya keliru, para hadirin bisa memahami konsep tema yang saya ajukan dan memicu munculnya diskusi yang sangat inspiratif. Setidaknya, pemahaman saya atas teori agonisme pada tema yang sedang saya kembangkan tidak salah, bahkan saya mempraktekannya meski secara tidak sadar.
Lantas apa itu agonisme dan setan apa pula yang menautkannya dengan wacana hubungan antara Indonesia dan Nigeria?
Perjalanan saya bersama Lisistrata Lusandiana (peneliti Yayasan Biennale Jogja) di Nigeria selama 30 hari lalu (5 November – 5 Desember 2014) bertujuan untuk memeriksa lebih dalam hasil riset pertama dari kunjungan sebelumnya oleh Yustina Neni (Direktur Yayasan Biennale Yogyakarta), Rain Rosidi (Direktur Artistik) dan Arham Rahman (Redaktur Newsletter The Equator). Selain itu, saya juga tertarik untuk melihat lebih jauh tentang intervensi artistik di Nigeria. Kami pun berbagi tugas. Saya akan meneliti tentang dinamika seni dan budaya, sedangkan Lisis mempelajari wajah atau karakter sosial, budaya, ekonomi dan politik Nigeria secara luas yang kemudian saya elaborasi untuk menentukan tema.
Tim BJ XIII memutuskan untuk membangun sebuah tema yang tidak sekadar mencari persamaan antara Indonesia dan Nigeria, tetapi juga mencari narasi-narasi yang sedang dialami atau sedang dibicarakan oleh kedua negara tersebut. Untuk itu, hal utama yang kami lakukan dalam penelitian itu adalah mencoba merasakan dan mengalami secara langsung dinamika kehidupan di Nigeria. Ada 4 daerah yang kami kunjungi, yaitu Abuja -ibukota pemerintahan,
Lagos -kota terbesar, Abeokuta, sebuah kota kecil tempat kelahiran Fela Kuti dan Wole Soyinka yang tak jauh dari Lagos dan selama 2 hari sempat numpang di rumah seorang seniman yang juga kepala adat di sebuah desa kecil di Osogbo. Namun, kami menghabiskan lebih banyak waktu di Lagos karena geliat seni kontemporernya yang lebih dinamis. Melalui rekomendasi yang kami dapatkan, daftar tersebut mengantarkan kami ke hal-hal yang lebih luas sehingga membuat kami menjadi cukup sibuk selama sebulan. Kami mengunjungi semuanya secara langsung tanpa asisten. Kami mencoba makan apa yang mereka makan, mengendarai berbagai macam angkutan umum, bernegosiasi harga, berpindah-pindah tempat tinggal dan ngobrol dengan siapapun mulai dari tokoh budaya, seniman, aktivis, sopir bus, anak kecil, pengusaha, musisi, pegawai hotel, penjual makanan kaki lima hingga tentara.
Dalam perjalanan itu, ada dua kata yang sering kami temui, yaitu republic dan yang cukup mengejutkan adalah kata intervention, karena sebelumnya saya memang ingin meneliti soal itu di Nigeria. Kata republic digunakan baik oleh musisi-aktivis Fela Kuti (Kalakuta Republic, rumah kolektifnya yang sekarang menjadi museum), maupun nama penerbit buku alternatif Cassava Republic, toko hp Cellular Republic hingga rumah makan cepat saji Chicken Republic. Sedang kata intervention sering digunakan oleh seniman, budayawan, sastrawan dan penulis dalam karya-karyanya.
Kami lalu sepakat untuk menjadikan 2 kata tersebut sebagai acuan observasi. Melalui serangkaian pembacaan literatur dan wawancara, kami juga akhirnya memutuskan untuk menelusuri hal-hal yang mendasari mengapa dua kata tersebut demikian “populer” di sana lewat pengalaman tinggal dan berinteraksi dengan masyarakat.
Indonesia dan Nigeria adalah negara bekas jajahan yang baru benar-benar lepas dari rezim otoriter di akhir tahun 90-an. Bila berakhirnya rezim otoriter di Indonesia disebabkan oleh pelengseran rezim Orde Baru pada tahun 1998 melalui serangkaian aksi massa (protes masyarakat) maka di Nigeria situasinya lebih unik. Rezim otoriter Nigeria yang dikendalikan oleh kalangan militer justru diakhiri oleh pihak militer itu sendiri. Pergantian rezim tersebut pertama-tama dimotivasi oleh meninggalnya pemimpin tertinggi Nigeria saat itu, Jendral Sani Abacha, karena serangan jantung di tahun 1998. Seorang perwira militer yang juga merupakan Menteri Pertahanan Nigeria di era Abacha, Mayor Jendral Abdulsalami Abubakar, mengambil alih kekuasaan dan mengakhiri rezim militer dengan menggelar Pemilu.
Pasca-keruntuhan otoritarianisme tersebut, negara dan rakyat sama-sama melakukan eksperimen atas sistem demokrasi. Mereka mencari rumusan demokrasi yang ideal dan otonom menurut pemahaman atau kehendaknya masing-masing. Hal ini menciptakan sebuah kesenjangan infrastrukur sosial dan budaya. Situasi ini menjadi semakin kacau dengan adanya pemahaman sebagai bangsa besar (terdiri atas berbagai macam suku, tradisi dan bahasa) yang memiliki sumber daya alam melimpah sehingga berusaha untuk mengejar ketertinggalan dan harapan menjadi negara adidaya yang demokratis.
Dalam praktiknya, kebebasan individu untuk menyatakan pendapat–bagi sebuah bangsa yang terdiri dari beragam suku dan bahasa–adalah ladang subur untuk memanen oposisi. Kebebasan dan kesatuan dalam keberagaman, ibarat bensin dan air yang jika tidak diolah secara cerdik, akan menjadi “racun mematikan” bagi sebuah keselarasan hidup. Konflik-konflik yang muncul seringkali dilihat sebagai momok menakutkan yang harus diberantas atau bahkan dihindari. Tanpa disadari, hal ini justru menciptakan masyarakat yang moralistik dan melupakan keberagamannya–tepatnya (sebut saja) sebuah masyarakat yang simetris, kalimat bernada ironi dari desain kaos DGTMB (Daging Tumbuh). Dari sinilah saya kemudian tertarik dengan teori agonisme. Dalam teori ini, konflik harus selalu dilihat secara positif. Perlu dipinang dan dipahami dalam kehadirannya yang mutlak. Sebagai hal penting yang musti dikelola sehingga menciptakan sebuah keharmonisan yang tak terduga. Meski agonisme merupakan sebuah teori politik, saya ingin melihatnya secara luas, yaitu berdasar pada sendi-sendi kehidupan yang dialami oleh masyarakat saat ini. Demokrasi tak melulu berada pada tataran politik, tetapi perlu dipahami sebagai cara hidup bersama dalam berbagai macam perbedaan dan karut-marut infrastruktur ekonomi, sosial dan teknologi.
Pada ranah teknologi, kesenjangan dalam hal pendistribusian dan sifatnya yang asimetris, mendorong lahirnya inovasi baru yang penuh intrik; sebuah inovasi palsu dengan nilai yang unik. Inovasi-inovasi ini tidak diciptakan oleh pencarian atas hal-hal yang belum ada, tetapi lahir dari keterbatasan dan kesalah-kaprahan. Dalam sebuah kerja bersama atau kolaborasi—sistem kerja yang sedang digemari karena menawarkan semangat kebersamaan—kesalahpahaman terhadap sebuah gagasan justru seringkali menghasilkan karya yang secara artistik tidak terduga. Ia memiliki nilai kebaruan karena sifatnya yang unik. Peluang atau celah muncul karena adanya bentuk yang tidak terstruktur dengan rapi. Proses penciptaan kemudian dikerjakan berdasarkan peretasan yang penuh improvisasi. Karena itu, dibutuhkan strategi yang taktis tapi spekulatif untuk meretas konflik menjadi pola asimetris yang simetrik (atau harmoni dalam chaos). Hal ini patut dicoba dengan membedah dan menghadirkan biji-biji pahit konflik dan kekacauan melalui kerja seni-budaya yang imajinatif, terbuka dan dinamis untuk kemudian dinikmati, dipikirkan dan diretas bersama-sama.
Pada Program Pameran Utama Biennale Jogja XIII nanti saya akan mengundang para pelaku seni, budaya dan berbagai bidang terkait lainnya untuk berkolaborasi bersama saya, menciptakan sebuah platform kerja berupa ruang aktivitas, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Ruang ini terdiri atas ruang pajang, studio kerja, kelas belajar, panggung tontonan dan pusat informasi yang simulatif. Melalui ruang tersebut, di bulan November yang cuacanya biasanya tak menentu itu, kami mengajak masyarakat untuk bermain, belajar dan bekerja secara bersama-sama untuk bereksperimen dengan konflik.
RANCANGAN KERJA
Pada intinya, pameran ini dirancang sebagai sebuah penciptaan karya kolaboratif yang sinergis dalam lingkup seni kontemporer secara luas (bukan hanya seni rupa). Disini kurator juga akan duduk bersama partisipan sebagai kolaborator dalam proses penciptaan. Kurator dan partisipan (seniman) dibayangkan sebagai sebuah kolektif seniman yang mengembangkan gagasan dan menciptakan karya seni bersama-sama dan terbuka melalui sebuah forum. Forum ini ditujukan untuk menciptakan sebuah proyek seni bersama sehingga karya-karya yang dihasilkan saling bertautan satu sama lain. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan seorang partisipan membuat karya sendiri, namun gagasan diperoleh atau dikembangkan melalui forum dan terbuka bagi partisipan lain untuk terlibat. Forum diselenggarakan secara online dan offline mulai minggu kedua di bulan Maret hingga Desember 2015.
Pameran ini (bisa disebut juga sebagai sebuah proyek seni kolektif) dirancang untuk menciptakan ruang-ruang konflik, permasalahan, yang mengintervensi publik secara artistik untuk berpartisipasi aktif sehingga membentuk opini-opini publik. Dengan ini, karya seni membuka peluang atas inisiatif, aspirasi dan distribusi wacana yang luas.
Secara fisik, ruang (situs) utama pameran disusun atas object-object yang membentuk sebuah struktur bangunan, sebuah site-specific installation. Bangunan ini memiliki ruang pajang, ruang pertunjukan, ruang kerja dan pusat informasi yang artistik dan instalatif, meliputi pemajangan karya seni, artefak dua dimensional dan tiga dimensional, kelas belajar, panggung, studio kerja, biro informasi dan toko. Ruang utama ini juga berfungsi sebagai pusat atau poros penyebaran karya-karya yang dilakukan dan diedarkan di ruang-ruang lainnya (satelit). Selain itu juga dibutuhkan sebuah ‘alat’ atau interaksi berupa permainan-permainan atau simulasi bagi pengunjung untuk terlibat aktif. Biro informasi berfungsi karya komunikasi yang menjadi panduan atas karya-karya yang ditampilkan baik yang berada di ruang utama dan di ruang publik (termasuk galeri seni atau ruang komunitas).
Program pameran ini juga akan mengirim seniman Indonesia untuk melakukan residensi selama 1 bulan di Nigeria pada bulan Juni dan mendatangkan seniman Nigeria ke Indonesia pada pertengahan bulan September hingga pertengahan bulan November. Program residensi ini lebih ditujukan untuk melakukan riset dan proses pengembangan kerja yang telah digagas dan didiskusikan sebelumnya di forum.
Wok the Rock