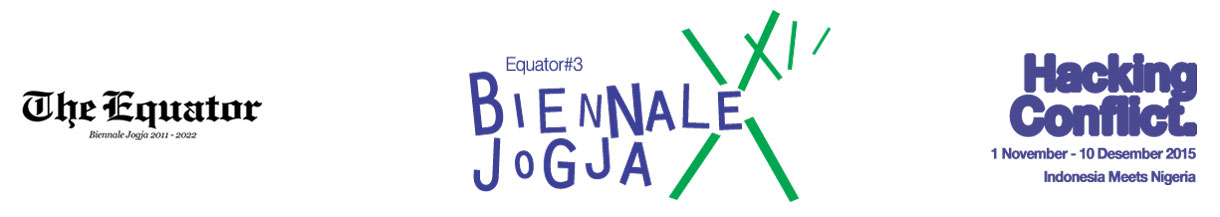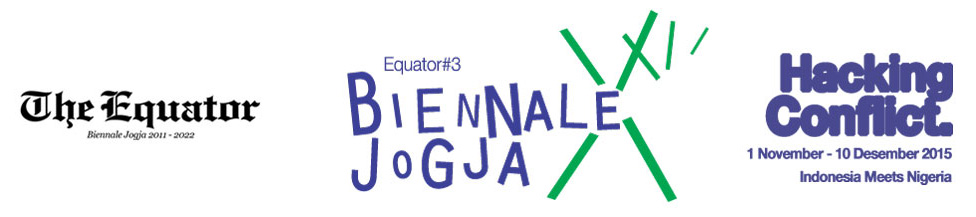PAGUYUBAN SIDJI
“Mateni Sing Mukti, Mukti Sing Mateni”
Isu sampah dan penanggulangannya menjadi isu mayor dalam masyarakat terkini dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat mulai dari yang sifatnya ekonomi seperti Bank Sampah, hingga “menyulap” sampah menjadi kerajinan kreatif.
Gagasan yang ditawarkan oleh Paguyuban Sidji adalah meretas masalah sampah di DAS dan irigasi di Sriharjo, Imogiri, Bantul. Sampah yang menumpuk dan merusak persawahan warga, bukan hanya disebabkan sampah yang mengalir dari kota (hulu), melainkan juga kebiasaan warga yang membuang sampah sesukanya di “spot-spot favorit”. Sampah itu, dalam peribahasa Jawa adalah “mateni sing mukti, mukti sing mateni”.
Proyek yang akan dikerjakan adalah pembuatan instalasi seni dari sampah-sampah sekitar dan dipasang di “spot-spot favorit” sepanjang daerah aliran sungai (DAS). Semua proses pembuatan instalasi sampah ini melibatkan pemuda. Proyek yang diharapkan tentu lebih dari sekadar pemasangan instalasi yang dalam biennale se-belum2nya sudah kerap dilakukan kelompok seniman lain.
Perlu ada tindakan seni yang memberi rasa kaget. Muncul usulan; selain (1) edukasi membuang sampah yang “benar; (2) pembuatan seni yang tepat guna; juga (3) bekerjasama dengan dinas kebersihan (truk kuning) yang dikawal arak-arakan motor pemuda desa di Sriharjo membawa sampah yang sudah dikumpulkan untuk dibawa kembali ke kota dan dijadikan instalasi. Retasan ini menjadi serangan balik mengagetkan kepada warga kota/hulu bahwa sampah yang dibuang “takut-takut” mematikan kehidupan mereka yang di hilir.
ANAK WAYANG INDONESIA
“Kampung Semanak”
Konflik apa yang ingin diretas AWI ini di kampung Mergangsan Kidul? Lihat saja dulu kegiatan artistik apa yang mereka tawarkan. Pertama, karnaval anak keliling kampung. Kedua, “mimbar bebyass” sebagai panggung pertunjukan yang organik dalam kampung, seperti poskamling, balai RT, halaman TK, halaman masjid, dan beberapa titik penting lainnya. Ketiga, pameran foto sejarah kampung dan pembuatan banner-banner perdamaian.
Sebagai komunitas organik yang lahir dari Mergangsan Kidul, kiprah AWI cukup panjang membangun kampung ini menjadi “kampung bahagia” yang memperlakukan keberbedaan dengan cara-cara bersahaja. Cerita sukses ini barangkali bisa menjadi inspirasi bagi kampung yang lain. Karena itulah, Mergangsan bisa dijadikan halte untuk sebuah sarasehan Biennale ihwal “Kampung Bahagia” dengan menghadirkan komunitas-komunitas yang konsens dengan sisi-melik kampung maupun perangkat desa lain dan pemerintah yang terkait.
SANGGAR SENI RNB & KOMUNITAS TITIK LENYAP
“Berguru pada Batu”
Kelompok ini hendak meretas soal eksploitasi alam lewat penambangan bukit berbatu di Desa Bedoyo, Ponjong, Gunungkidul. Alih-alih melakukan perlawanan secara frontal, sebagaimana terjadi di kawasan-kawasan lain saat terjadi konfrontasi penambangan, RnB & Titik Lenyap menawarkan gagasan seni perlawanan “kulonuwun” yang memiliki dampak ekonomi berkelanjutan seperti membuat motif “batik tambang” dan membuka ceruk pasar keluar daerah. Karena itu, komunitas ini menggaet dinas terkait Kabupaten Gunungkidul.
Menggambar bukit yang sudah “tak produktif” dengan mural raksasa, pembuatan “monumen harapan”, pementasan pertunjukan teater kampung adalah hal lain yang dilakukan untuk kerja penyadaran. Kelompok ini juga melakukan penajaman artistik dengan menjadikan bukit mural sebagai ruang/panggung budaya baru untuk aktivitas kesenian. Kerjasama dilakukan juga dengan pihak lain untuk membuat branding “batik tambang” agar memiliki napas ekonomi panjang untuk kesejahteraan warga sekitar.
Arsitektur UKDW +
“Ingatan dan Air”
Isu air di perkotaan digarap sekelompok mahasiswa arsitektur UKDW yang berkolaborasi dengan beberapa dosennya. Mereka merancang sebuah penanda utama dalam bentuk karya arsitektural berbahan bambu untuk mengumpulkan ingatan masyarakat tentang situs-situs air bersih di perkampungan pinggir kali Code. Selain karya utama itu, beberapa aktivitas juga dirancang untuk mempertemukan kembali pola keseharian masyakat hari ini dengan tempat-tempat penanda air itu. Kelompok ini juga akan didukung oleh komunitas seniman dan warga kampung di lokasi acara itu.
TERAS PRINT STUDIO dan Kulon Progo Printmaking
“Menyukil Sejarah”
TPS bekerjasama dengan Kulonprogo Printmaking meretas soal relasi yang buram pendidikan seni yang dipahami masyarakat seni di kota dengan masyarakat di daerah-daerah pinggiran yang notabene (calon) sumber kreatif. Fenomena itu dilihat komunitas ini dari kurang dikenalnya seni rupa–selain pertunjukan tradisi–yang dibuktikan ketiadaan ruang yang representatif yang dibangun pemerintah kabupaten.
Untuk itulah TPS bekerjasama dengan kelompok seni Jatimulyo, Pengasih, dan seniman grafis berkolaborasi meretas kesenjangan kesadaran itu. Memilih seni grafis cukil pada hardboard, TPS menggerakkan masyarakat melakukan pencungkilan bersama yang diberi tajuk “Menyungkil Sejarah” (sebelumnya bertema “Mencungkil Biennale”). TPS melakukan riset komunitas; menggelar cukil bersama dengan komunitas tentang apa yang digelisahkan. Hasilnya karya-karya kolektif-kolegial itu dipamerkan di ruang pameran Biennale, sementara salinannya dipamerkan di ruang publik di Kulonprogo.
Proyek ini bisa disebut pula menghidupkan kultur cukil kayu yang pernah menjadi primadona di era seni rakyat masih menjadi panglima. Tema retasan yang dipilih juga menarik, yakni dunia pendidikan. Menjadi menarik adalah workshop cukil kayu yang bersifat kolaboratif dengan melibatkan “guru-seni” di seantero Kulonprogo. Sebab peran guru dalam transformasi pengetahuan dan kultur cukup signifikan. Posisi mereka sebagai “pemegang pengetahuan” masih terpacak kuat di benak warga yang tinggal di kampung atau di kota-kota kecil kabupaten. Pengalaman sang guru itulah yang diharapkan bisa dikomunikasi-bagikan kepada siswanya secara turun-temurun lewat subpelajaran “mulok”.
ANANG SAPTOTO DAN ARSITEKTUR UTY
(Universitas Teknologi Yogyakarta)
“Sejarah dan Retropeksi Pembangunan Perumahan Gunung Sempu Yogyakarta)
Membaca ulang dari awal-mula bagaimana perumahan menjadi pola baru hadirnya hunian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perumahan yang dianggap “liyan” dari kampung justru berasal dari gagasan “sederhana” menghidupkan kawasan tandus dan berkapur di tahun 70-an. Komunitas ini menampilkan kisah awal lewat tuturan dan dokumentasi konsepsi dasar mengapa hunian perumahan dibangun dalam sebuah proyek. Selain pameran foto, video, dokumentasi, komunitas yang konsens pada arsitektur ini juga menampilkan maket masa depan Gunung Sempu sebagai perumahan lama dengan wajah baru. Ini adalah siasat meretas kondisi alam yang berkapur menjadi ruang artistik dan layak huni.
Selain perumahan untuk yang hidup di sebelah barat, Sempu juga dikenal juga sebagai kuburan Tionghoa yang dikreasi sebagai “perumahan sunyi” yang artistic mengikuti kontur tanah pegunungan. “Yang Hidup, Yang Mati” di Sempu adalah bentang-alam (landscape), sekaligus menjadi bentang-pikir (mindscape) bagaimana sebuah hunian dirancang.
Perstiwa seni ini dirancang juag melalui eksekusi artistik tertentu hingga mendapatkan kesadaran baru bahwa perumahan kita terima sebagai satu kesatuan historik bagaimana sejarah hunian dalam masyarakat bersifat dinamik. Pertanyaan-pertanyaan ini menggelitik untuk diketengahkan, seperti apakah perumahan melahirkan cipta-karsa baru, menghadirkan pola berkomunikasi yang khas, dan menawarkan solusi bagi tesis bahwa di masa depan mayoritas masyarakat hidup di kota dan bukan di desa.
MOANSNAKE28 & Art as Therapy
“Kampung Kita, Kearifan Kota”
“Seni sebagai terapi” adalah cara meretas “kampung rombeng” semacam Bausasran yang ditawarkan komunitas ini. Kampung yang tak terurus dengan segala turunan identifikasi negatifnya menjadi tantangan yang tak mudah bagi kegiatan berkesenian untuk mengurainya. Apalagi kompleksitas negatif yang lain terkait dengan hubungan yang “dingin” antarasrama yang melingkupinya, seperti asrama mahasiswa Jambi, Palembang, dan Papua. Menyatukan variabel-variabel sosial yang sakit itulah komunitas ini bekerja. Ajakan berkesenian, terutama dengan mural dan pemanfaatan ruang-ruang yang ada dengan memobilisasi warga membangun “urban gardening” dan perpustakaan warga luar ruang diharapkan bisa mengeluarkan stempel kampung Bausasran dari segala cibiran minor.
Proyek seni ini menantang untuk dilihat dari kompleksitas masalah yang dihadapi di mana diperlukan kesabaran mengurainya. Menggabungkan antara praktik seni mural dan urban gardening serta melibatkan “kaum pendatang” dari Indonesia Timur menjadi poin penting untuk menjawab cerita panjang tentang stereotip terkini pasca peristiwa Cebongan. Persoalan kualitas hidup warga menuntut kelompok ini mampu mengurai masalah lingkungan urban yang indah, sehat, cerdas, dan kosmopolit (INSECERKOS).
KELOMPOK TIGA
“Agraria Menapak Tilas”
Agraria Menapak Tilas adalah sebuah karya seni rupa instalasi dengan wujud sawah yang membentuk telapak kaki manusia. Merespon ruang kosong dan terbuka di tengah-tengah perkotaan menjadi lahan produktif. Dalam karya ini, Proses pembuatan karya adalah point terpenting atau inti dari karya. Mulai dari pembangunan pondasi sebagai bidang sawah, pembibitan, tanam perawatan panen sampai pengaplikasian hasil panen. Di antara waktu yang luang, dihadirkan beberapa kegiatan seperti workshop seni grafis juga pertunjukan seni wayang suket. Selain itu, interaksi pengunjung dalam kegiatan juga menjadi bagian terpenting pada karya.