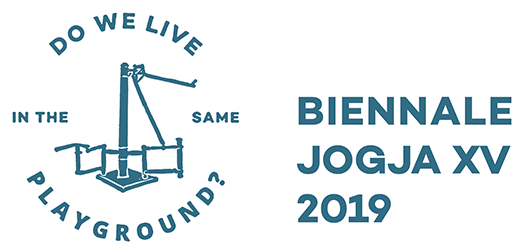Penwadee Manont
Keluarga bisa dibilang menjadi pengaruh terbesar yang membuat Pooh, panggilan akrabnya, mengenal dan begitu fokus terhadap isu sosial serta politik dalam praktek kerjanya. Ayahnya adalah seorang politisi dan sempat menjadi anggota parlemen di Thailand, sangat aktif dalam pergerakan dan melihat permasalahan sosial yang terjadi. Sehingga, hal ini membuat kehidupan Pooh sangat dekat dengan isu-isu politik. Mengenyam pendidikan di dua negara sekaligus, Amerika dan Thailand, Pooh memulai studinya di bidang desain grafis. Kemudian ia melanjutkan pendidikan magisternya di Thailand, Environmental Management, School of Social and Environmental Development, National Institute of Development Administration.
Pooh sudah lama menaruh perhatian terhadap dunia seni, sehingga setelah ia mengenyam pendidikan di bidang desain grafis, ia memutuskan untuk beralih ke pengelolaan seni, lebih khususnya sebagai asisten kurator di 304 Alternative Art Space di tahun 2001. Kemudian karir Pooh dalam bidang kuratorial ia kembangkan melalui pengalamannya bekerja sebagai tim kurator di The Jim Thompson Art Center selama kurang lebih lima tahun ia berada disana. Karirnya yang bergeser dan menyentuh ranah seni, menurut Pooh ditandai dengan salah satu momen di mana ia berkesempatan mengikuti sebuah lokakarya kuratorial di pertengahan tahun 90-an. Baginya, momen mengikuti lokakarya tersebut sangatlah penting, terlebih saat ia juga berkesempatan bertemu dengan Gridthiya Gaweewong dan Klaomas Yipintsoi. Setelah lokakarya tersebut ia semakin yakin untuk mengembangkan dan memfokuskan pekerjaannya dalam ranah kuratorial.
Suami Pooh yang bekerja sebagai sutradara, membuat Pooh juga banyak bekerja dalam dunia perfilman. Saat ini pun, dia aktif bekerja sebagai direktur pelaksana dari SEAFIC (Southeast Asia Fiction FIlm Lab). Sebelumnya pun dia juga sempat menjadi produser dalam beberapa pembuatan film pendek, salah satu diantaranya berjudul The Whole Nine Yard dan Cool BKK, yang dibuat oleh Lek Manont.
Berbicara mengenai perjalanan karirnya yang bisa dibilang sudah cukup panjang, hampir dua puluh tahun lebih lamanya, saat muncul pertanyaan peristiwa penting apa yang paling diingat sepanjang ia bekerja sebagai kurator? Peristiwa pertama adalah saat ia terlibat menjadi salah satu pengurus sebuah gerakan bernama ANT’s Power di tahun 2014. Di tahun tersebut, Bangkok, tempat di mana ia berada mengalami sebuah krisis politik saat Yingluck perdana menteri yang terpilih di tahun 2011, menyalahgunakan kekuasaannya. Salah satunya dengan membentuk RUU amnesti untuk mempermudah kembalinya Thaksin Shinawatra. Peristiwa ini membuat Pooh merasa harus melakukan sesuatu, permasalahan ini harus dibicarakan.
Setelah terjadinya krisis politik, terjadi sebuah proses transisi di masyarakat Thailand. Pameran Condemn To Be Free, menjadi bentuk kerja lain yang dia rasa penting dalam perjalanan karirnya. Kepekaan Pooh dalam melihat situasi politik yang terjadi, dia mencoba merefleksikannya lebih dekat lagi dalam membaca posisi tiap-tiap individu. Ada yang secara jelas mengambil posisi oposisi tapi juga ada yang berusaha netral — yang mana bagi Pooh, perihal ini penting untuk dibongkar melalui bentuk kolaborasi. Bentuk kolaborasi yang melibatkan seniman dan praktisi lain dengan beragam latar belakang, ia coba untuk diaplikasikan agar mendapatkan macam-macam perspektif dalam melihat permasalahan.
Terkait dengan fokus Biennale Jogja tahun ini yang mencoba melihat Asia Tenggara melalui pinggiran, bagi Pooh ia mencoba memahami pinggiran bukan sebagai kawasan. Salah satu usahanya membahas mengenai pinggiran telah dimulai dengan proyek yang sedang ia kerjakan terkait wilayah Pattani, bagian selatan Thailand. Kondisi di wilayah tersebut banyak ditekan oleh pemerintah pusat. Pinggiran baginya dapat dilihat sebagai bentuk imajinasi, bukan sesuatu yang nyata dapat dilihat begitu saja. Konsep pinggiran sendiri merupakan ciptaan manusia, bukan sesuatu yang tercipta begitu saja. Perlu adanya cara, bentuk, dan format kolaborasi yang tepat agar nantinya bisa membongkar pemahaman mengenai pinggiran ini sendiri.
Akiq AW
Arham Rahman mulai dikenal dalam skena seni di Yogyakarta terutama setelah kelompok yang ia inisiasi memenangkan kompetisi program dalam Parallel Events yang diselenggarakan oleh Biennale Jogja Ekuator #1, Indonesia bertemu India. Pada saat itu, Arham bersama teman-temannya menyelenggarakan pameran yang gagasan kuratorialnya berbasis pada penelitian mereka tentang sejarah Bugis yang tidak banyak dibicarakan dalam wacana sejarah kontemporer. Narasi yang munculkan sangat kuat, terutama untuk memberi posisi baru atas peran perempuan pejuang bernama Colliq Pujie yang memberi kontribusi besar pada perkembangan bahasa, sastra dan wacana anti-kolonial pada masyarakat Sulawesi. Tidak hanya berkaitan dengan narasi, proyek seni mereka menunjukkan ketrampilan untuk menurunkan gagasan menjadi karya-karya yang menarik, yang secara visual memberi ruang imajinasi bagi penonton.
Arham Rahman tumbuh besar di Makassar hingga ia melanjutkan pendidikannya ke Yogya pada kisaran 2011. Di Makassar, ia banyak bergelut dalam bidang sastra, mengingat juga pendidikan formal yang ia dapatkan di Fakultas Sastra Universitas Muhammadiyah Makassar. Kemudian, ia memutuskan mendalami kajian budaya dan melanjutkan sekolah di Program Studi Ilmu Religi dan Budaya di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Referensinya yang luas terhadap sejarah dan kajian-kajian Indonesia Timur, dengan perhatiannya yang besar atas teori-teori kajian dan filsafat kebudayaan, membuat Arham dengan segera masuk ke dalam lingkaran intelektual dan akademik dalam dinamika seni di Yogyakarta. Ia terlibat dalam beberapa proyek penelitian dan penerbitan, serta secara aktif menjadi pembicara atau pemandu diskusi dalam berbagai pertemuan yang melibatkan pemikir, aktivis dan seniman di Yogyakarta. Bersama teman-teman di Indonesia Visual Art Archive, pada 2017, Arham menjadi bagian dari Festival Arsip di mana ia dipercaya untuk menjadi penanggungjawab bagi program-program seminar dan diskusi di dalamnya. Dan dalam peristiwa inilah ia mulai secara intensif mendiskusikan kemungkinan keterlibatan dalam Biennale Jogja 2019 ini bersama Akiq AW.
Semenjak 2017, Arham juga mengembangkan visi kuratorial di Galeri Lorong, di mana fokus pada wacana kepengrajinan (craftsmanship) menjadi sesuatu hal yang unik yang membedakan ruang ini dengan ruang-ruang lain di Yogyakarta atau di Indonesia. Arham menunjukkan kemampuan untuk membangun gagasan-gagasan kuratorial yang menarik yang membuka kemungkinan bagi pertemuan antara praktik kerajinan dan seni kontemporer. Tema-tema yang cukup provokatif seperti “Performing Crafts”,
Ketika ditanya mengapa kemudian tertarik untuk mengembangkan lebih jauh kerja kuratorial, Arham menyatakan bahwa “Praktik kuratorial tidak mempunyai pakem atau metode yg baku. Setiap kurator bisa mengembangkan metodologi dan praktik kerjanya sendiri. Ditambah lagi, peluang untuk berdialog dengan berbagai jenis gagasan (dalam hal ini gagasan seniman) sangat terbuka, yang membuat kita terus tertantang dan terus belajar. Itu yang membuat praktik kuratorial itu menarik buat saya.”
Sebelum bergabung dalam tim kurator Biennale Jogja 2019, sebagian juga mengenal Arham sebagai bagian yang cukup penting dalam kelahiran Makassar Biennale di Sulawesi Selatan pada 2015 dan terlibat kembali dalam penyelenggaraan 2018. Pada saat itu, Arham bekerja ulang-alik di dua kota ini, dan secara khusus menyiapkan sistem kerja atau struktur yang dapat dilakukan oleh teman-teman di Makassar sendiri walaupun ia tidak secara langsung berada di sana. Berkaitan dengan pengalaman menyelenggarakan peristiwa di dua kota ini, Arham menyebut bahwa perbedaannya cukup kentara, sebab ada perbedaan praktik dan kultur kesenian di kedua wilayah ini. Keduanya tentu tidak bisa dibandingkan karena perbedaan itu tadi. Jogja mempunyai tradisi seni rupa yang kuat, seniman yang berjubel jumlahnya, serta ruang ekspresi (ruang seni dan perhelatan kesenian) yg sangat banyak. Ketika kita hendak membuat sebuah perhelatan, rasanya lebih ringan karena dukungan infrastruktur-infrastruktur tadi.
Bagi Arham, Makassar perlu dilihat secara berbeda. Dinamika keseniannya tidak bisa disamakan dengan Jogja dan memang tidak perlu sama. Makassar mempunyai gayanya sendiri. Tidak ada cukup ruang pamer yang memadai, bisa diatasi dengan bentuk presentasi di rumah2 seniman atau bahkan di halaman rumah. Nalarnya pasti berbeda, termasuk dalam soal pengelolaan perhelatan seni semacam Biennale.
Berkaitan dengan gagasan Asia Tenggara dalam penyelenggaraan Biennale Jogja tahun depan, Arham juga telah terlibat dalam jaringan Arisan Tenggara yang diinisiasi oleh Ace House Collective pada 2018 ini, sehingga menarik untuk memperluas jejaring kerja para penggerak seni generasi muda ini dalam lingkup yang lebih luas.
Arham Rahman
Keseharian Akiq AW sebagai seniman sesungguhnya cukup padat dengan aktivitas yang beragam; sesekali membuat proyek kuratorial, menunggui bengkel kerja percetakan foto yang cukup sibuk, berkumpul bersama teman-teman seniman terutama di markas Mes 56, dan, yang terpenting, mengantar jemput ketiga anaknya pergi dan pulang sekolah. Meskipun acap mendaku dirinya fotografer, ia tidak selalu siap dengan kamera. Kerja kreatifnya sebagai seniman seringkali dimulai dari amatan-amatannya atas praktik kehidupan sehari-hari yang penuh siasat dan sabotase, lalu direfleksikan melalui serangkaian pembacaan dan kajian, lalu baru gagasan dieksekusi menjadi karya.
Kerja yang mirip seperti moda kerja “etnografer” ini saya kira juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya; ia kuliah di jurusan fotografi Fakultas Media Rekam Institut Seni Indonesia, dan pada saat yang sama juga belajar di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada. Dua pengalaman ini seperti memberi pembelajaran untuk melatih pisau analisis terhadap problem dan praktik kehidupan sosial, dan juga untuk melakukan eksperimentasi artistik dalam rangka penciptaan karya.
Karya-karya Akiq AW merefleksikan bagaimana praktik dan tata nilai keseharian menunjukkan kecerdasan dan kejeniusan lokal. Semenjak akhir 2000an, ia mengembangkan seri “The Order of Things”, di mana ia merekam bagaimana benda-benda atau objek-objek disusun melalui pengetahuan dan pendekatan yang unik dalam lingkungan keseharian, hampir menyerupai citraan seni. Akiq mengangkat yang keseharian ini menjadi menjadi sesuatu yang seperti “tak lazim”. Ada absurditas imaji, ada humor kritis, ada komposisi yang artistik, yang kadang kita terima nyaris terberi.
Proyek selanjutnya yang ia kerjakan dimulai dari gagasan tentang moda-moda pendisiplinan dan propaganda yang terjadi selama Orde Baru, sampai ia memilih program Keluarga Berencana sebagai kasus yang ia angkat. Program ini merupakan program andalan yang banyak dilihat sebagai tolak ukur keberhasilan rezim Soeharto, yang secara massif dicanangkan di setiap wilayah di Indonesia. Akiq mendokumentasikan artefak-artefak propaganda KB yang berupa relief gambar keluarga yang ada di desa-desa di beberapa kota di Jawa. Citra visual keluarga ini digambarkan nyaris sama dalam hal idealisasi keluarga: bapak, ibu dan dua anak—laki-laki, perempuan. Karya ini pertama kali dipamerkan secara utuh di Ark Galerie di Yogyakarta, dan kemudian sempat melanglang ke beberapa pameran di manca negara, termasuk di EVA International Biennale di Limmerick, Irlandia (2018), di Deck Singapura (2018), di Dakkar, Senegal, dan selanjutnya juga di National Gallery of Australia di Canberra pada Juni 2019 mendatang.
Akiq juga berlaku sebagai kurator di beberapa pameran yang berlangsung di Mes 56. Sebagian besar pameran ini melibatkan seniman-seniman muda, sehingga fungsi kuratorial pada konteks ini juga acap meluas tidak saja dalam hal penciptaan karya untuk mewujudkan gagasan pameran, tetapi juga menjadi sebuah cara untuk ‘mentoring’, yang merupakan proses penting dalam skena seni di Yogyakarta. Selain itu, Akiq juga terlibat dalam proses kuratorial untuk keterlibatan Mes 56 sebagai kolektif di berbagai pameran internasional yang telah mereka ikuti. Pada 2017, Akiq menjadi Direktur Pengarah Seni pada gelaran Festival Arsip yang diselenggarakan oleh Indonesia Visual Art Archive (IVAA) di Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjosoemantri di lingkungan kampus UGM Yogyakarta. Dalam festival ini, Akiq mengundang para seniman untuk merespons gagasan tentang arsip seni dan sejarah pameran, termasuk pembacaan mereka terhadap pergeseran skena dan komunitas seni di Indonesia. Dalam mengangkat tema arsip dan sejarah seni ini sendiri, menariknya, Akiq berupaya untuk menggandeng penonton agar membuat tafsir baru atas arsip yang ditawarkan seniman, dan bahkan untuk berpartisipasi dalam penciptaan karya yang berbasis arsip tersebut. Hasilnya, banyak karya-karya yang dihasilkan para seniman ini bersifat interaktif, partisipatoris, dan juga performatif.
Dengan pengalaman dalam penyelenggaraan pameran yang kaya dan pemahaman yang cukup luas atas dinamika seni baik di tingkat lokal maupun global, Akiq AW terpilih sebagai salah satu anggota tim kurator dalam Biennale Jogja 2019 mendatang. Dengan mitra kerja Asia Tenggara, sebagaimana yang ditawarkan oleh Yayasan Biennale Yogyakarta, ada gagasan untuk tidak mempertentangkan pusat-pinggiran, tetapi lebih pada upaya untuk melihat keduanya dalam garis sejarah kebudayaan yang sejajar. Gagasan pinggiran bukankah sesuatu yang dilihat dalam cara pandang romantik, melainkan dalam kritisisme dan semangat reflektif untuk memetakan ulang relasi kuasa, baik yang oposisional maupun hirarkis.