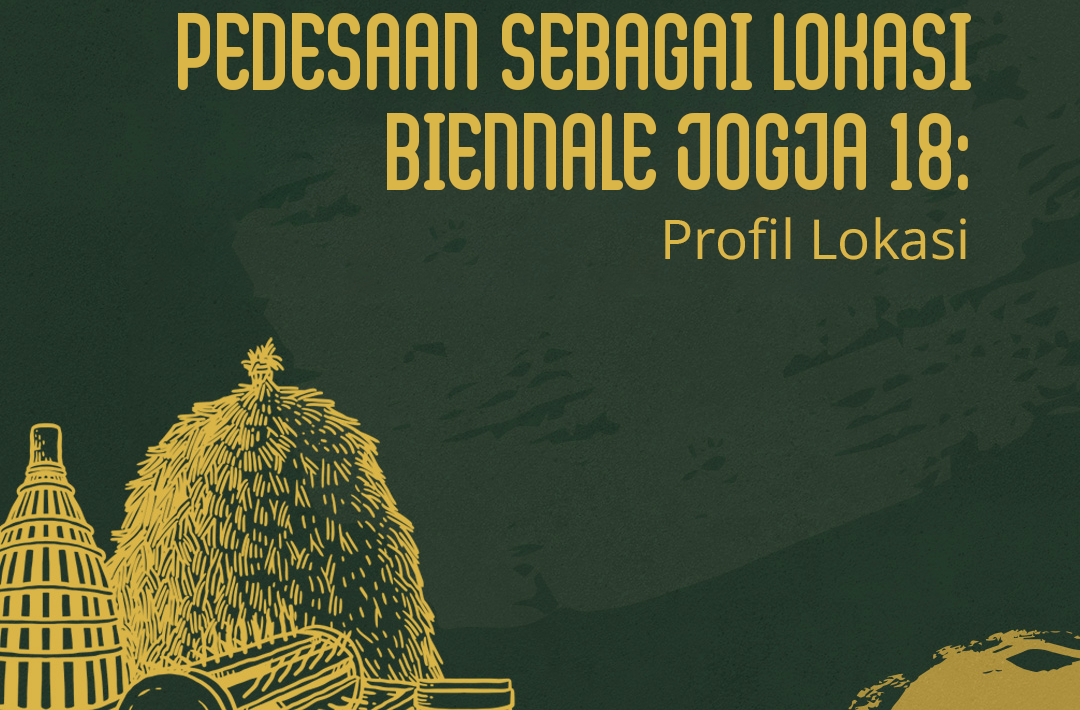Boro II: Padukuhan Tradisional di Kulon Progo yang Kaya Sejarah dan Budaya

Padukuhan Boro II merupakan salah satu padukuhan di Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo. Padukuhan ini terdiri dari empat Rukun Tetangga (RT) dan memiliki posisi unik karena dikelilingi persawahan yang luas, sehingga terlihat seperti pulau hijau dari kejauhan, pulau yang dikelilingi oleh lautan.
Awalnya, Boro II adalah bagian dari Karang Kemuning, wilayah yang didominasi rawa-rawa. Penduduk kala itu mengandalkan perahu sebagai sarana mobilitas sehari-hari. Rawa-rawa ini kemudian dikeringkan untuk dijadikan lahan produktif dan pemukiman. Nama Karang Kemuning diganti menjadi Adi Karto, “Adi” (linuwih) dan “Karto” (subur) yang dapat dimaknai sebagai tanah subur, yang kemudian wilayah ini akhirnya menjadi bagian dari Kulon Progo yang lebih luas.
Transformasi ini bukan hanya mengubah lanskap fisik, tetapi juga kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dari lahan rawa yang sulit diakses, Boro II kini menjadi padukuhan subur dengan aktivitas pertanian sebagai fondasi utama kehidupan warga. Kehidupan awal masyarakat, yang mengandalkan air dan rawa sebagai sumber kehidupan, tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya desa hingga kini.
Kehidupan Pertanian Warga
Mayoritas warga Boro II berprofesi sebagai petani. Aktivitas pertanian mengikuti ritme musim: pada musim penghujan, sawah ditanami padi, sedangkan pada musim kemarau, petani menanam palawija. Selain bertani, sebagian warga bekerja sebagai pemetik cabai atau buruh harian di lahan milik orang lain, yang mayoritas dilakukan ibu-ibu, sementara bapak-bapak lebih banyak bekerja sebagai kuli bangunan.
Kehidupan warga di desa ini sangat terstruktur. Pagi hingga sore dipenuhi dengan aktivitas produktif, siang hari digunakan untuk beristirahat atau beribadah, dan malam menjadi waktu santai di rumah atau melaksanakan agenda rutinan warga seperti Siskamling di pos ronda. Saat panen tiba, warga saling membantu, membentuk kebersamaan dan solidaritas. Bahkan, tradisi berbagi hasil panen dan membantu tetangga tetap dijaga hingga generasi muda saat ini, menunjukkan kuatnya ikatan sosial di padukuhan ini.
Infrastruktur dan Akses Transportasi
Padukuhan Boro II dikelilingi beberapa jalur transportasi penting. Di utara persawahan terdapat Jalan Raya yang menghubungkan Kulon Progo dengan Yogyakarta, sejauh ±30 km dari Titik Nol. Di sisi selatan, Jalan Lintas Selatan (JLS) mengarah ke Jembatan Pandansimo, yang kerap menjadi lokasi berkumpul dan piknik bagi muda-mudi. Sementara tak jauh dari sisi barat persawahan, terdapat Jalan Deandels Pantai Selatan menghubungkan warga menuju New Yogyakarta International Airport (NYIA).
Meskipun dikelilingi oleh infrastruktur transportasi yang ramai, Padukuhan Boro II cenderung sepi dan minim interaksi. Para warga yang telah pergi bekerja sedari pagi hingga sore menjelang malam hari, telah membuat mayoritas warga memiliki aktivitas yang sangat padat dan sibuk sehingga jarang berada di rumah pada waktu-waktu tersebut. Ketika menjelang waktu istirahat pada siang hari, mayoritas warga akan lebih meluangkan waktunya untuk beribadah. Setelah itu, mereka akan kembali lagi bekerja, kemudian saat malam hari tiba masyarakat lebih banyak yang memilih untuk kembali beristirahat di rumah masing-masing. Atmosfer yang cenderung sepi di padukuhan ini semakin lengkap dengan adanya rumah-rumah rusak yang ditinggalkan dan mulai diselimuti tetumbuhan, minimnya penerangan serta ruang-ruang untuk sekadar bercengkrama bagi para warga.
Meski demikian, secara tidak langsung infrastruktur mobilitas yang berada di sekitar padukuhan ini tetap memiliki pengaruh yang berkesinambungan. Boro II menampilkan perpaduan menarik antara arsitektur desa dan kota. Beberapa rumah memiliki fasad depan bergaya perkotaan, sementara bagian samping dan belakang tetap mempertahankan bentuk tradisional sederhana. Beberapa rumah memiliki pagar, tetapi bersifat dekoratif dan tidak membatasi akses, menunjukkan keterbukaan masyarakat; memperlihatkan penggabungan kecenderungan gaya arsitektural kota (yang tertutup) dan desa (yang terbuka).
Gaya arsitektur ini mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap modernitas tanpa meninggalkan akar tradisional. Rumah-rumah tersebut menjadi simbol integrasi antara kehidupan pedesaan dan pengaruh perkotaan, sekaligus menandai perubahan sosial ekonomi yang terjadi di Boro II.
Situs Bersejarah dan Makam
Boro II memiliki sejumlah situs bersejarah yang kaya makna, selain keunikan arsitekturalnya yang cukup menonjol. Makam Simbah Kyai Ghuro dan Makam Simbah Kyai Bandar Arum misalnya, yang menjadi petilasan penting dan menjadi penanda sejarah bahwa wilayah ini dulunya merupakan bagian dari rawa-rawa.
Di daerah utara Kapanewon Galur, bekas lokasi pabrik gula dan jalur kereta Brosot-Yogyakarta menyimpan jejak kolonial. Beberapa sisa bangunan masih ada, termasuk Kerkhof atau makam Belanda dengan lima nisan, serta rumah-rumah sisa Perumahan Dinas Pabrik Gula Sewugalur. Situs-situs ini menjadi bukti keterkaitan Boro II dengan sejarah ekonomi kolonial dan perkembangan lokal, sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang pentingnya pelestarian warisan sejarah.
Karang Kemuning Ekosistem
Di padukuhan ini, terdapat Karang Kemuning Ekosistem, ruang publik yang berperan penting di Boro II. Tempat ini menjadi pusat pendidikan kontekstual berbasis persoalan masyarakat sekitar, dimana pengetahuan diajarkan dan langsung dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.
Selain fungsi pendidikan, Karang Kemuning juga sering dimanfaatkan menjadi lokasi pentas kesenian, pertemuan pemuda, agenda posyandu, dan dialog antarwarga. Juga di dalamnya termasuk kegiatan seni seperti pertunjukan teater rakyat, latihan tari tradisional, dan festival desa kecil. Tempat ini menjadi ruang publik yang memungkinkan interaksi antara warga, pengurus desa, maupun individu dari luar desa, sehingga menjadi pusat kreativitas, kolaborasi, dan kohesi sosial Boro II.
Tradisi dan Modernitas yang Harmonis
Boro II adalah contoh nyata desa yang hidup di persimpangan tradisi dan modernitas. Sawah subur, rumah tradisional, bekas pabrik gula, dan jalur transportasi modern saling berdampingan. Aktivitas pertanian, pekerjaan konstruksi, perdagangan, dan jasa berjalan beriringan, sementara identitas budaya tetap terjaga melalui arsitektur rumah, situs bersejarah, dan ruang publik yang mendukung kesenian serta interaksi sosial.
Generasi muda Boro II aktif terlibat dalam kegiatan desa, baik dalam pertanian, kesenian, maupun pendidikan. Hal ini menunjukkan kemampuan masyarakat beradaptasi terhadap perubahan zaman, menjaga tradisi, dan memanfaatkan peluang ekonomi modern. Desa ini menjadi bukti bahwa pelestarian budaya dan kemajuan ekonomi dapat berjalan berdampingan, menenun kehidupan masyarakat di tengah sawah, jalan raya, dan jejak sejarah.
Menyusuri Panggungharjo: Warisan Budaya, Seni, dan Transformasi Desa

Panggungharjo, salah satu desa yang berada di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang letaknya sangat strategis. Desa ini hanya berjarak sekitar sembilan kilometer dari Tugu Yogyakarta atau kurang lebih 20 menit perjalanan. Di sebelah utara, desa ini berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta; di sebelah timur dengan Desa Bangunharjo; di selatan dengan Timbulharjo dan Pendowoharjo; sementara di barat berbatasan dengan Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan. Lokasinya yang berada di jalur lintas provinsi membuat Panggungharjo berkembang menjadi kawasan yang dinamis, sekaligus menjadi pintu gerbang antara perkotaan Yogyakarta dengan wilayah pedesaan Bantul.
Tak jauh dari wilayah desa, berdiri bangunan bersejarah Panggung Krapyak, bagian dari Sumbu Filosofi Yogyakarta. Kehadiran bangunan ini bukan hanya memperkaya identitas budaya, tetapi juga menjadikan Panggungharjo sebagai wilayah dengan nilai sejarah tinggi. Selain itu, di desa ini juga berdiri Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, yang ikut mempengaruhi atmosfer seni dan kreativitas masyarakat.
Struktur Wilayah dan Karakter Desa
Panggungharjo memiliki luas wilayah 560,9 hektar yang terbagi dalam 14 pedukuhan dan 119 RT. Wilayah ini memiliki sumber air tanah yang cukup melimpah, terutama di Pedukuhan Glugo dan Pelemsewu, sehingga cocok untuk difungsikan sebagai lahan pertanian. Sejak lama, wilayah desa ini dibagi menjadi tiga kawasan: kring selatan yang dikenal sebagai penghasil padi, kring tengah yang menjadi pusat pemerintahan desa, dan kring utara yang tumbuh sebagai kawasan aglomerasi perkotaan.
Namun, dalam lima tahun terakhir, pola penggunaan lahan mengalami perubahan signifikan. Alih fungsi lahan pertanian, terutama di kring utara, membuat banyak sawah berubah menjadi pemukiman, kafe, rumah makan, dan tempat penginapan. Fenomena ini mencerminkan dinamika urbanisasi sekaligus sebagai tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertanian tradisional dan kebutuhan ekonomi modern.
Demografi dan Mata Pencaharian
Berdasarkan data desa, Panggungharjo dihuni oleh 28.493 jiwa dengan jumlah laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang. Mata pencaharian utama penduduk kini didominasi oleh karyawan swasta, disusul ASN, TNI-Polri, dan buruh. Jumlah penduduk yang berprofesi sebagai buruh juga tak kalah banyaknya dengan karyawan swasta. Akan tetapi, profesi petani sudah semakin berkurang karena lahan pertanian banyak beralih fungsi, menjadi lahan pemukiman dan kegiatan bisnis.
Meski demikian, masih ada warga yang mempertahankan tradisi kerajinan. Beberapa wilayah menjadi pusat produksi kerajinan khas, seperti lurik di Krapyak dan Pelemsewu, sablon tatah di Sawit, tatah wayang, serta produksi gamelan di Cabeyan. Aktivitas kerajinan ini tidak hanya memperkuat identitas budaya lokal, tetapi juga memberi peluang ekonomi bagi masyarakat.
Kehidupan Seni yang Kondusif
Atmosfer seni di Panggungharjo dapat dikatakan sangatlah hidup dan beragam. Banyak sanggar tumbuh dan berkembang di desa ini, seperti Panggung Laras Budaya, Kudha Beksa Kudha Manunggal, Manunggal Budaya, dan Turangga Mudha Budaya Panggungharjo yang melestarikan seni jathilan.
Seni tari juga berkembang melalui sanggar seperti Sanggar Seni Anak Saraswati dan Omah Joged Pramesti. Ada pula Thek Tonk dengan kesenian klothekan, serta kelompok karawitan seperti Purbo Rini, Sekar Muda Laras, dan Sedyo Laras. Seni kethoprak dengan sentuhan religius juga tetap hidup melalui kelompok Jolelo. Sementara itu, seni rupa mendapatkan ruang di Sanggar Kalam dan Omah Kreatif Dongaji. Semua aktivitas ini membuat Panggungharjo dikenal sebagai desa seni yang mampu menjaga sekaligus memperkaya tradisi budaya.
Situs Sejarah dan Warisan Leluhur
Selain kesenian, Panggungharjo juga memiliki warisan sejarah yang tak kalah penting. Panggung Krapyak, yang sering disebut juga Kandang Menjangan, merupakan bagian dari garis imajiner Yogyakarta yang menghubungkan Gunung Merapi, Tugu Yogyakarta, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, hingga Pantai Parangtritis.
Menurut cerita masyarakat, kawasan sekitar Panggung Krapyak melambangkan fase kehidupan manusia ketika masih berada dalam kandungan. Hal ini ditandai dengan keberadaan Kampung Mijen di sebelah utara, yang namanya berasal dari kata “wiji” yang berarti benih.
Selain itu, desa ini juga menyimpan makam para leluhur yang menjadi cikal bakal nama-nama padukuhan, seperti makam Kyai Dongkel, Pangeran Soro, Kyai Sorobudin, Nyai Cabe, Nyai Padang, dan Ki Juru Purbo. Keberadaan makam leluhur ini mempertegas kedalaman sejarah sekaligus spiritualitas masyarakat Panggungharjo.
Inovasi Ekonomi dan BUMDes
Panggungharjo juga dikenal sebagai desa yang aktif berinovasi dalam bidang ekonomi. Desa ini memiliki beberapa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat. Unit usaha yang dijalankan antara lain pengelolaan sampah, rumah makan, dan gedung serbaguna.
Sebelumnya, Panggungharjo juga sempat mengembangkan swalayan desa, meski harus berhenti beroperasi sejak pandemi. Menurut Direktur BUMDes, usaha-usaha ini tidak hanya bertujuan menambah pendapatan desa, tetapi juga memberi ruang pemberdayaan bagi kelompok masyarakat yang sering terpinggirkan, seperti difabel, anak jalanan, ibu rumah tangga, putus sekolah, hingga ODGJ. Dengan begitu, BUMDes Panggungharjo menjadi contoh bagaimana desa bisa tumbuh melalui prinsip inklusi sosial sekaligus inovasi ekonomi.
Panggungharjo adalah desa yang tidak hanya menjadi saksi perubahan zaman, tetapi juga aktif beradaptasi dan berinovasi. Dari lahan pertanian yang bertransformasi, kesenian yang terus tumbuh, situs sejarah yang sarat makna, hingga BUMDes yang memberdayakan masyarakat, Panggungharjo telah berupaya untuk menghadirkan harmoni antara tradisi dan modernitas.
Di tengah tantangan urbanisasi dan alih fungsi lahan, desa ini tetap menjadi ruang hidup yang kaya akan budaya, sejarah, sekaligus inovasi sosial-ekonomi. Sebuah desa yang terus menenun identitasnya di persimpangan antara masa lalu dan masa depan.
Bangunjiwo, Desa di Persimpangan Budaya, Sejarah, dan Modernisasi

Desa Bangunjiwo terletak di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, berada di sisi barat daya Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jarak sekitar 12 km dari pusat kota. Desa ini memiliki luas wilayah 1.543 hektar yang terbagi dalam 19 dusun, berbatasan dengan Tamantirto di utara, Tirtonirmolo di timur, serta Guwosari dan Triwidadi di barat. Letak desa yang strategis ini membuat Bangunjiwo ini tak hanya menjadi bagian penting dari lanskap Bantul, tetapi juga titik temu antara sejarah, budaya, dan dinamika pembangunan.
Lanskap Kapur dan Kehidupan Sehari-Hari
Secara geografis, Bangunjiwo terbentang di antara dataran dan perbukitan batu kapur. Bagian dataran subur dimanfaatkan untuk sawah dan ladang, sementara perbukitannya yang cenderung kering dan sulit air, lebih cocok untuk difungsikan sebagai kebun kayu dan sebagian ladang kecil. Rumah-rumah warga tersebar di kedua wilayah, berdampingan dengan gudang, pabrik, rumah makan, vila, hingga studio para seniman kontemporer yang jumlahnya semakin banyak dalam satu dekade terakhir.
Pemandangan ini menandakan sebuah desa yang hidup dan terus berubah. Aktivitas warga tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada pertanian. Jika dahulu lebih dari 80% penduduk Bangunjiwo berprofesi sebagai petani, kini buruh mendominasi mata pencaharian, disusul dengan profesi sebagai pedagang, pegawai negeri, pensiunan, dan wiraswasta. Perubahan ini tidak bisa dilepaskan dari letak Bangunjiwo yang berdekatan dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Pabrik Gula Madukismo, serta jalan provinsi yang memberi akses lebih luas bagi investasi dan urbanisasi; letak yang sangat strategis.
Tradisi yang Bertahan di Tengah Perubahan
Meskipun struktur pekerjaan bergeser, sejumlah warga Desa Bangunjiwo tetap melanjutkan profesi yang berakar pada tradisi. Bangunjiwo dikenal sebagai rumah bagi para perajin wayang, pembuat topeng, pengrajin gerabah, hingga seniman tradisi lain yang menjaga keterampilan turun-temurun. Hasil karya mereka tidak hanya menjadi komoditas ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas budaya desa.
Perajin wayang, misalnya, tak hanya menciptakan tokoh-tokoh pewayangan, tetapi juga mewariskan filosofi dan nilai moral yang terkandung dalam setiap detail ukiran. Begitu pula dengan pembuat topeng dan gerabah, yang karyanya kerap digunakan dalam ritual, pertunjukan seni, maupun kebutuhan sehari-hari. Di tengah derasnya modernisasi, kerajinan ini menjadi bukti bahwa warisan budaya lokal masih berdenyut dan memiliki ruang untuk terus tumbuh di desa ini.
Alih Fungsi Lahan dan Kontras Sosial
Transformasi lain yang sangat terasa adalah alih fungsi lahan. Sawah dan kebun yang dulunya mendominasi desa ini perlahan berganti wajah menjadi perumahan, kafe, dan vila. Dusun Sekar Petak, misalnya, menjadi salah satu kawasan favorit karena panorama sawahnya yang indah dengan latar langit luas dan siluet pepohonan. Namun, kini suara mesin pemotong kayu lebih sering terdengar daripada suara cangkul atau gemericik air sawah.
Fenomena ini berdampak besar pada kehidupan sosial. Lonjakan harga tanah membuat banyak warga kesulitan membeli atau mempertahankan lahan mereka sendiri. Di beberapa titik, kontras sosial tampak begitu jelas: rumah-rumah sederhana penduduk desa berdiri berhadapan dengan bangunan mewah bergaya etnik-modern yang eksklusif dan tertutup. Situasi ini mencerminkan bagaimana modernisasi membawa peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat lokal.
Jejak Sejarah dan Ruang Spiritualitas
Tak berhenti di situ, Bangunjiwo hidup dengan menyimpan banyak situs sejarah dan spiritual yang menjadi penanda ingatan kolektif desa. Di sini terdapat Situs Lingga, Gua Wurung—yang pernah menjadi tempat persembunyian Pangeran Diponegoro sebelum pindah ke Gua Selarong—hingga makam-makam keramat seperti Makam Kyai Godeg, Kyai Joyudo, Kyai Song, dan Josedewan. Situs-situs ini tidak hanya merekam jejak tokoh bersejarah, tetapi juga menjadi bagian dari sistem nilai masyarakat setempat.
Selain itu, desa ini memiliki sejumlah mata air yang dianggap keramat sekaligus memiliki latar belakang historis. Sendang Rancang Kencono, misalnya, masih terkait erat dengan kisah Gua Wurung. Ada pula Sendang Banyu Temumpang yang dibangun pada masa Sultan Hamengku Buwana II. Tak ketinggalan Sendang Banyuripan, Sendang Pangkah, Sumur Gede, dan Sendang Semanggi yang hingga kini masih dihormati masyarakat, sebagai mata air yang dikeramatkan. Meski sebagian besar situs kini terancam oleh kurangnya perawatan dan dukungan, semua ini menjadi pengingat bahwa warisan budaya bukan hanya berupa benda atau bangunan, melainkan juga lanskap alam yang menyatu dengan kehidupan spiritual warga.
Arsitektur Desa dan Jejak Waktu
Arsitektur Bangunjiwo merekam perjalanan panjang desa. Rumah-rumah joglo dan limasan dari kayu masih bisa ditemui di beberapa dusun, meski jumlahnya semakin berkurang. Ada pula rumah-rumah berdinding batu kapur yang khas dengan suasana pedesaan. Namun, setelah gempa 2006, banyak bangunan tradisional berganti dengan rumah tembok permanen.
Setiap bentuk dan material rumah menyimpan jejak perubahan zaman. Rumah kayu mencerminkan keterampilan lokal sekaligus kesederhanaan hidup, sementara bangunan tembok menunjukkan upaya warga untuk beradaptasi dengan bencana sekaligus modernitas. Kontras ini membuat Bangunjiwo seolah menjadi ruang pamer yang memperlihatkan bagaimana arsitektur berperan sebagai saksi perjalanan sosial dan ekologis desa.
Antara Kapur, Sawah, dan Bayang-Bayang Beton
Bangunjiwo adalah desa yang terus bernegosiasi dengan dirinya sendiri. Di satu sisi, ia memelihara sejarah panjang, budaya, dan spiritualitas yang mengakar. Di sisi lain, ia harus berhadapan dengan modernisasi, urbanisasi, dan tuntutan ekonomi yang memaksa lahan serta pola hidup berubah cepat.
Namun, dibalik itu semua, Bangunjiwo tetaplah ruang yang hidup. Desa ini menunjukkan bagaimana masyarakat lokal mampu menenun harapan di antara bentangan kapur, hamparan sawah yang tersisa, dan bayang-bayang beton yang terus bertambah. Bagi siapa pun yang datang, Bangunjiwo bukan hanya sekadar desa, tetapi juga cermin perjalanan sebuah komunitas yang berusaha menjaga keseimbangan antara masa lalu dan masa depan.