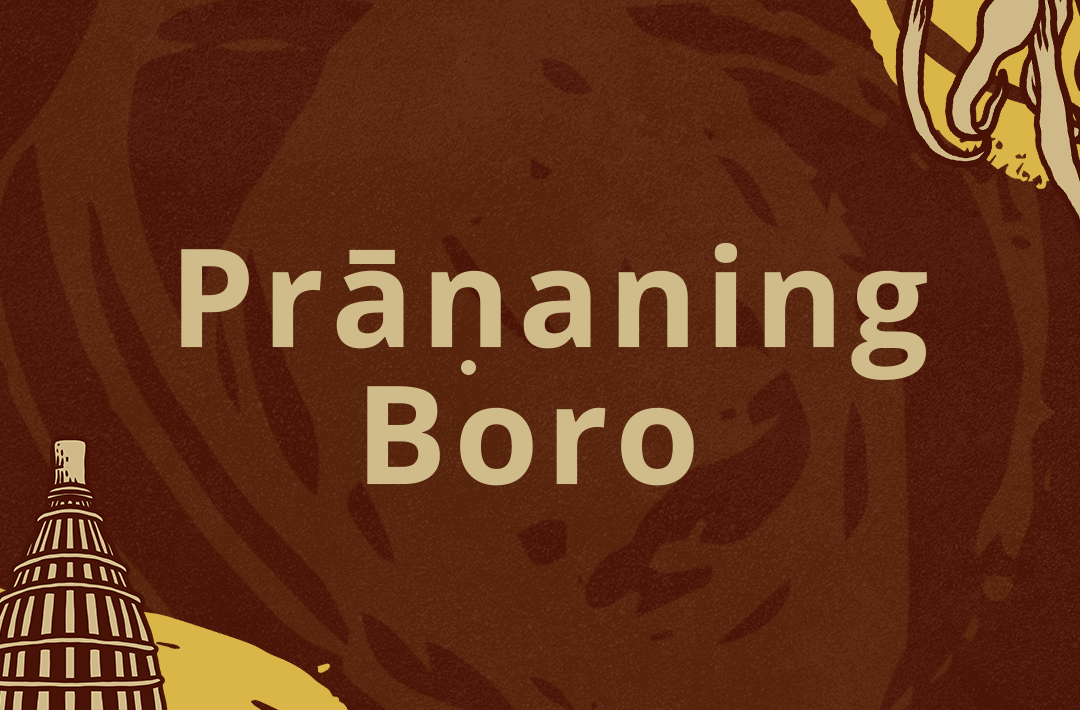Dipantik oleh pengetahuan perihal realitas keseharian di Padukuhan Boro II, sebuah desa yang terletak di Kapanewon Galur, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Prāṇaning Boro dipilih sebagai tema Asana Bina Seni 2025. Kata Prāṇaning yang memiliki arti “angin” atau “napas”, diambil dari Bahasa Kawi (Jawa Kuno). Prāṇaning Boro merepresentasikan ke-sementara-an atau ke-singkat-an kehadiran yang sekilas melintas seperti kencangnya angin pesisir yang menyapu tingginya pepohonan kelapa di Padukuhan Boro II. Kendati singkat, angin selalu datang berulang dan berbaur dengan nafas warga Boro. Begitu pula proses para Seniman beserta Penulis/Kurator Asana Bina Seni 2025 bersama warga Boro, kehadirannya yang hanya sesaat sekaligus menyatu-leburkan pengetahuan dari berbagai bidang pengetahuan dengan realitas keseharian warga Boro, menjadi rangkaian helaan nafas panjang.
Kosa kata Prāṇaning dari Bahasa Kawi yang tidak lagi akrab digunakan juga menjadi representasi permulaan pertemuan pengetahuan yang asing. Namun alih-alih menjadi sepenuhnya asing, peserta Asana Bina Seni 2025 berangkat dari ketiadaan yang kreatif, sehingga diri-peserta secara sadar memahami, memproses, dan mengartikulasikan properti-pengetahuan realitas keseharian warga, untuk memperkaya gagasan penciptaan karya yang sebelumnya telah dibentuk. Pada akhirnya kata Prāṇaning menggambarkan bagaimana pengetahuan yang ada di Padukuhan Boro II (dan sekitarnya) telah merasuk ke dalam, dan menjadi napas dari diri para peserta Asana, selama proses membangun perjumpaan, tinggal, dan berdialog bersama para warga.
Sebagai pengetahuan yang tak pernah usai, Prāṇaning Boro membawa perhelatan Asana Bina Seni 2025 sebagai awalan untuk memiliki dan berbagi angin atau napas yang sama, antara para Seniman dan Penulis/Kurator serta warga Boro II, untuk kedepannya dapat atau setidaknya telah menjadi satu-kesatuan pengetahuan. Dan sebagaimana gerak angin menerpa rimbun rumpun pepohonan di Boro, pengetahuan tersebut diharapkan akan dapat memantul ulang kembali ke arah warga, melalui karya yang dipresentasikan oleh 9 Seniman Muda; Anisyah Padmanila Sari, Barikly Farah Fauziah, Darryl Haryanto, Dionisius Caraka, I Kadek Adi Gunawan, Mailani Sumelang, Sri Cicik Handayani, dan Taufik Hidayat.
Meski berangkat dari lokus yang sama, yaitu Padukuhan Boro II yang membersamai KAWRUH: Tanah Lelaku pada Babak I perhelatan Biennale Jogja, Fioretti Vera, Gata Mahardika, dan Laboratorium Sedusun, membawa pengetahuan sebagai bagian dari Prāṇaning Boro di Panggungharjo pada Babak II Biennale Jogja. Masing-masing Seniman beserta Kurator, meniti jalan yang berbeda-beda. Maka itu, karya-karya yang ada, bila didistorsi sedemikian rupa dapat dipetakan menjadi beberapa subtema: (1) Ekologi, (2) Garis Lebur (3) Arsip dan Sejarah.
Ekologi
Kehidupan sehari-sehari di pedesaan, bila dilihat dari perspektif orang luar, mungkin akan tampak begitu sederhana. Karena aktivitas warga hanya berputar-putar pada ruang-ruang seperti: sawah, tempat ibadah dan rumah. Akan tetapi, bila ditelisik lebih dalam, terdapat sebuah kerumitan. Seperti ditunjukkan oleh Dionisius Caraka melalui karya Nyang-Nyangan, yang berupa plang penanda properti diisi dengan berbagai informasi terkait lahan dan tanah Boro, mencoba melakukan sebuah upaya negosiasi dengan menghadirkan persoalan agraria dalam bentuk simbol visual sehari-hari. Plang, yang biasanya hanya menyatakan kepemilikan atau transaksi jual-beli, kini menjadi ruang wacana yang mengangkat posisi petani dalam urusan negara, memperlihatkan ketergantungan mereka pada tengkulak, menelusuri rantai distribusi hasil panen, sekaligus membuka kemungkinan perhitungan untung rugi maupun ancaman alih fungsi lahan. Melalui cara ini, Dionisius Caraka menyingkap relasi kuasa yang tersembunyi di balik papan sederhana itu, sekaligus menunjukkan bagaimana angka-angka yang semula dimaksudkan untuk memperjelas dan memastikan sesuatu hal, justru menjelma menjadi alat distorsi. Angka kehilangan fungsinya sebagai penjelas, dan berubah menjadi instrumen yang mengaburkan kenyataan, menyingkirkan dimensi sosial, ekologi, bahkan spiritual, demi kepentingan tunggal: keuntungan.
Memudarnya kesadaran ekologis memang merupakan persoalan yang cukup krusial baik itu di perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Terlebih bila mayoritas warga mengandalkan air sebagai sumber penghidupan seperti untuk mengairi persawahan, misal. Karena tanpa adanya pasokan air bersih, tanaman yang ditanam di sawah tidak dapat tumbuh dengan optimal. Dan aliran air pun perlu dijaga bukan semata-mata karena ia menguntungkan manusia, tapi karena ia akan bergerak menuju hilir: ke laut. Membiarkan aliran sungai tercemar sama saja membiarkan bumi yang didominasi oleh laut ini porak-poranda secara ekologi. Melalui karya Wayang Kebon: Cekakak Terakhir, Anisyah Padma merespons isu ekologis tersebut, dengan menyuarakan sesuatu yang sangat dekat namun sering terabaikan menggunakan media wayang berbentuk burung Cekakak yang terbuat dari material yang berasal dari alam seperti serabut kelapa sebagai penanda akan berlangsungnya ekosistem sungai dan daerah pesisir.
Di Antara Ekologi dan Garis Lebur
Semakin lajunya kecepatan sendiri tidak dapat dilepaskan dari semakin masifnya pembangunan infrastruktur mobilitas, yang tidak hanya memantik terjadinya perubahan, tetapi juga perpindahan. Dengan berbekal harapan, individu pergi meninggalkan kampung halaman, dan seringkali disertai janji-janji akan kembali ketika harapan tersebut telah terpenuhi. Tetapi kenyataan lebih sering berkata lain, harapan dan janji seringkali dipatahkan oleh lingkungan dan rumah. Melalui karya Rumah ke Rumah yang menghadirkan rumah, tubuh, sastra lisan bersama Meneroka Indonesia; tali dan layang-layang I Kadek Adi Gunawan mencoba mengajak kita untuk merefleksikan isu lingkungan yang ada di sekitar rumah-rumah tak berpenghuni nan diselimuti sunyi. Rumah ke Rumah membangun konteks “pergi-pulang” antara lingkungan, diri, dan rumah untuk hadir saling menyilang, memahami, dan menyelaraskan kehidupan.
Garis Lebur
Ketika perpindahan terjadi, tentu tidak berhenti di persoalan lokasi atau ruang semata. Ia mengisyaratkan pertemuan individu-individu yang berlatar belakang berbeda. Di sana terjadi interaksi, terkadang berupa perselisihan, tetapi sering pula berupa pertukaran pengetahuan. Sebagaimana Sri Cicik Handayani coba tunjukkan dalam Papangghiyân, yaitu karya yang berupaya mencipta sebuah ruang untuk merayakan perjumpaan yang sederhana dan dibangun melalui serangkaian dialog di titik temu selama proses penciptaan karya. Di mana nampan kemudian digunakan sebagai media sekaligus simbol pertemuan antara Cicik dengan ibu-ibu sebagai tokoh utama dalam ruang privat. Nampan dalam karya ini merupakan salah satu dari pertemuan-pertemuan besar lain yang pernah terjadi dalam sejarah Boro dan sekitarnya.
Namun, pertemuan tak selalu mengharuskan semua pihak untuk mengeluarkan kata-kata, tetap diperlukan pendengar, karena mendengarkan pun sama pentingnya dengan berbicara. Dan terkadang, karena terlalu sibuk berbicara, kita menjadi lupa bahwa apa yang dikomunikasikan melalui kata-kata pun seringkali bukanlah apa yang sebenarnya dimaksud dan kita lupa untuk mendengarkan serta memperhitungkan bunyi-bunyi seperti tawa, gumam, desah, helaan napas yang dihasilkan oleh gerak tubuh lawan bicara kita. Berangkat dari pengalaman mendengarkan yang dilakukan secara lebih intens, bunyi-bunyi yang muncul ketika melakukan pertemuan dan percakapan bersama Ibu-ibu di Dusun Sawit, Panggungharjo. Fioretti Vera dalam Spektralieri, mencoba menggugat bagaimana cara-cara konvensional dalam memahami arsip, sejarah, dan tubuh perempuan; sebagai gantinya ia mencoba mengembalikan habitus mendengar yang tanpa sadar seringkali terjajah atas narasi dominan, dengan menghadirkan kembali ruang dengar yang utuh, di mana tubuh bukan semata alat rekam, dan bunyi bukan sekadar kebisingan maupun derau yang tak berarti, melainkan sumber memori dan pengetahuan yang hidup.
Akan tetapi, karena kecepatan dan pembangunan yang mengutamakan keuntungan, mendengarkan pun kini memang terasa begitu sulit. Sesuatu lebih sering mendekat tanpa adanya aba-aba atau persetujuan, upaya mendengarkan, dan apalagi pembicaraan seperti kota yang semakin merangsek paksa ke daerah pedesaan. Yang merupakan akibat dari sentralisasi aktivitas ekonomi di kota, yang justru kini membuatnya tampak lebih mirip pabrik raksasa, dan menjadikan daerah pedesaan menjadi seperti komplek perumahan tidak terencana untuk kelas pekerja. Desa yang bertransformasi menjadi kota penunjang. Melihat itu, Gata Mahardika dalam Griya Fantasi, mencoba menyoroti absurditas logika pembangunan sekaligus memprovokasi refleksi kritis melalui serangkaian dialog juga diskusi dengan audiens pada saat pameran berlangsung.
Kombinasi antara persebaran individu, masifnya pembangunan dan semakin lajunya kecepatan, telah menghasilkan produk berupa “ke-tidak-pemilik-an”. Meski sesuatu itu dekat dan sehari-hari, tapi asing, bukan milik kita sendiri. Sebab, sesuatu itu diberikan secara paksa dan dimediasikan sedemikian rupa, alih-alih merekah sendiri secara imediasi dari dalam dan atas kehendak diri kita. Melalui karya Quote Unquote, sebuah intervensi performativitas semantik atas material sehari-hari di Boro dan sekitarnya melalui tanda kutip yang berupa instalasi berpindah, video art dan arsip performans layang-layang, Darryl Haryanto mencoba melerai konflik antara bahasa indonesia dan kenyataan sehari-hari. Dengan cara menguraikan mediasi makna yang dilakukan oleh Bahasa Indonesia, yang bermuara pada pengaburan dan penyetrapan makna-makna keseharian agar tidak bertumbuh secara liar di luar peradaban makna resmi nasional. Karya ini beroperasi sebagai repertoar rapuh, yaitu proses (moda dan kerja) kelangsungan (liveness) dan keserentakan (concurrentness) dengan garis-garis batas kesementaraan yang kabur. Singkatnya, sebuah pertunjukan tak kasat mata.
Arsip dan Sejarah
Ketika membicarakan persoalan ekologis kita tidak dapat begitu saja melepaskannya dari kehidupan perempuan. Pasalnya, tubuh perempuan banyak menyimpan pengetahuan lokal, seperti praktik rewang. Dan bila ekologi mengalami kerusakan atau perubahan yang cukup signifikan, maka pengetahuan lokal yang menubuh pada diri perempuan seperti perihal bumbu-bumbu yang diperlukan untuk memasak makanan perlahan-lahan akan menghilang. Kiwari, perubahan-perubahan terjadi dengan begitu cepat, bahkan saking cepatnya mungkin kita tidak akan menyadari begitu sesuatu menghilang dari hadapan mata kita, untuk itu dengan menggunakan medium jarik, cyanotype, foto dan video, Barikly Farah dalam Wewarah Pawon Simbah mencoba melakukan upaya pengarsipan sekaligus penghormatan kepada perempuan yang menjadi pusat pengetahuan lokal yang kian dilupakan. Pada format lain, Laboratorium Sedusun menghimpun, merangkai dan menghadirkan kembali pengetahuan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam bentuk buku resep masakan rumahan. Resep masakan tidak sekadar catatan tentang rempah atau bumbu, namun berisikan pengalaman dan ingatan kolektif menahun.
Perubahan-perubahan kerap kali terjadi bukan atas keinginan kita sendiri, lebih sering perubahan itu disodorkan melalui paksaan, oleh entitas yang lebih berkuasa dan ini dapat dilihat pada karya Tutuwuhan, yaitu sebuah instalasi yang bermaterialkan keramik. Melalui serangkaian peristiwa sejarah yang merentang dari masa kolonial hingga saat orde baru berkuasa dalam karya ini Taufik Hidayat menawarkan berbagai hipotesis perihal sebab-sebab timbul-tenggelamnya salah satu makanan paceklik sekaligus khas Kulon Progo yaitu Growol. Seperti kapitalisme swasta pabrik gula yang mengkanonisasi tanaman tebu dan menyarankan penanaman ketela kayu kepada warga telah berpotensi kembali untuk timbulnya Growol sebagai makanan pokok; sedang rezim orde baru melalui kanonisasi tanaman padi yang mengenyampingkan varietas tanaman lain seperti singkong telah berpotensi menenggelamkan growol sebagai makanan pokok untuk kemudian digantikan oleh nasi. Dan karena karya ini lebih cenderung memberikan hipotesis alih-alih kebenaran tunggal, maka dialog perihal growol, warisan-warisan yang silih-ganti ditinggalkan, dan isu-isu yang melapisinya pun dimungkinkan untuk terjadi.
Penelusuran serangkaian peristiwa sejarah juga dilakukan oleh Mailani Sumelang, tetapi berbeda dengan Taufik yang berfokus pada objek fisik seperti makanan Growol, ia lebih berfokus pada sejarah yang bersumber di sekitar Padukuhan Boro yang terolah sebagai arsip. Arsip hadir pula dalam tubuh, menyimpan mana yang boleh dan yang tidak, mana yang ter-represi dan terekspresi. Bagaimana otot dan jaringan tubuh, yang kerap tidak disadari, berlaku sebagai pencatat riwayat dan gudang memori yang hidup. Karya ini berfokus menyadari dan merekam ingatan tubuh akan peristiwa pasca-kemerdekaan sebagai upaya mengorganisir ingatan berdasarkan empati sesama manusia, bukanya berdasar narasi dominan yang berusaha menggantikan memori ketubuhan. Dapat dilihat pada instalasi hand-cutting kupu-kupu dalam Ngramut yang memantul ke segala arah, termasuk kepada aku-kita. Ngramut mengajak kita membuka ruang sensorial sebagai tubuh yang merekam suka cita, dan sejarah yang hadir dalam sarasehan yang menjadi milik masyarakat sebagai ruang aman yang memantik perdamaian.