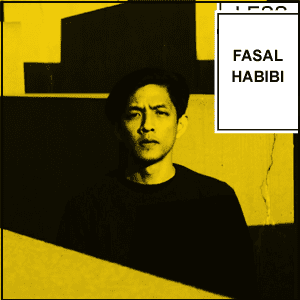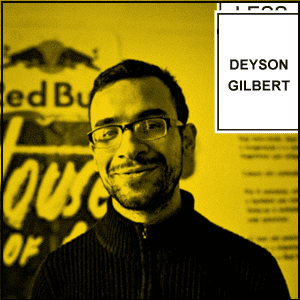Koro adalah karya video dan suara yang diajukan Waléria dalam kolaborasinya dengan seniman Yogyakarta, Lashita Situmorang, dan sebuah organisasi nirlaba, Samsara. Dalam upaya melintasi wilayah tiap-tiap orang dan bersama-sama merefleksikan dunia, karya ini mengumpulkan suara, ujaran, perasaan dari orang-orang anonim tentang pengalaman kasih sayang, jatuh cinta, dan seksual mereka. Semua rekaman ini diubah oleh senimannya menjadi gabungan banyak suara yang akan dirilis untuk publik. Gambar utama yang menampilkan sang seniman membawa sebuah bendera dan berjalan-jalan sepanjang penceritaan itu adalah sebuah tindak mendengarkan untuk mencapai proses penyembuhan itu sendiri, cara untuk melebur batas-batas—antarmanusia dan lebih luas lagi antarnegara. Karya ini ingin memecah kesunyian dengan tujuan menyembuhkan dan mengubah trauma menjadi harmoni, mengungkapkannya demi kesembuhan lahir dan batin. Dapatkah tubuh menjadi objek penyaluran? Bagaimana caranya menyatukan berbagai suara dan menyebarluaskannya dari kejauhan seperti antena?
Waléria mendapat gelar master Seni Multimedia – Pertunjukan & Instalasi dari University of Lisbon, sarjana Seni Rupa dari Fakultas Seni Rupa Grande Fortaleza, dan gelar spesialisasi Media Audiovisual dan Elektronik dari Federal University of Ceará. Sebagai perupa, karya-karyanya berkisar pada bentuk video, fotografi, instalasi, dan pertunjukan. Ia melakukan eksperimen dan menelusuri relasi yang menubuh antara seseorang dan lingkungannya, serta transisi antara penghidupan dan displacement (perasaan tidak memiliki ruang). Karya seninya disajikan dalam lintasan nonlinier, di mana fokus pada hubungan timbal balik antara tubuh dan tempat diterjemahkan ke dalam serangkaian pertunjukan site-specific dan pertunjukan yang dialihwahanakan jadi gambar, yang diwujudkan dalam bentuk benda dan instalasi atau foto dan video. Pada lapis selanjutnya, perhatian pada Liyan—dalam hal dimensi bersama dan kolaboratif yang tersirat dalam karya seni mana pun—mempertemukannya dengan pendekatan propositif, di mana materialitas percakapan dan keramahan dieksplorasi melalui pembangunan gambar lanskap yang mengundang mereka untuk mendiaminya. Akhir-akhir ini, ketertarikan khusus untuk meneliti potensi displacement sebagai sarana untuk menangguhkan dan bertahan membawanya menjelajahi perantaraan di tengah suara, kelisanan, dan performativitas.
LASHITA SITUMORANG (lahir 1977, Samarinda – Indonesia) merupakan lulusan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, jurusan Seni Murni tahun 2007. Kesenian Lashita banyak berbicara tentang isu sosial yang sering kali sensitif untuk dibicarakan di masyarakat luas. Lashita melihat hal-hal sensitif di masyarakat ini sebagai cerminan permasalahan yang kompleks dari isu-isu populer seperti gender, politik, ekonomi, lingkungan, dan lainnya. Lashita lebih tertarik pada situasi riil di sekitarnya berproses, menggali dan membangun pengetahuan bersama yang lebih solutif. Metode pengkaryaan Lashita menekankan pada proses riset, mencari tahu, bertemu, mempertemukan, mempertanyakan, dan memaparkan kembali hasil observasinya entah dalam bentuk proyek seni/komunitas, instalasi, karya 2 dimensi maupun 3 dimensi.
“Samsara bertujuan untuk meningkatkan kesehatan seksual dan reproduksi perempuan di Indonesia serta mendukung integritas dan otonomi tubuh perempuan. Melalui karya-karyanya, Samsara selalu menjunjung nilai-nilai yang didasarkan pada hak, peran serta kaum muda, layanan yang ramah bagi remaja, akuntabilitas, dan transparansi.”
samsara.or.id




![bp15[1]](https://www.biennalejogja.org/2017/wp-content/uploads/2017/03/bp151-988x659.jpg)
![br-area[1]](https://www.biennalejogja.org/2017/wp-content/uploads/2017/03/br-area1-1200x800.gif)