Tentang
- BJ 18 2025
- BJ Equator Putaran Kedua (2023-2027)
- Metode Kuratorial
- Asana Bina Seni 2025
- Tim Kuratorial
- Tim BJ 18
KAWRUH: Tanah Lelaku
Berakar dari Bahasa Jawa yang berarti pengetahuan sebagai akumulasi pengalaman yang dicerna secara kritis oleh akal budi, KAWRUH dalam lingkup Biennale Jogja ke-18 dimaknai sebagai sekumpulan keragaman praktik artistik yang berjangkar pada sikap dan upaya menyelami seluk beluk pengetahuan tersebut. Pengetahuan yang kemudian dipahami sebagai laku menubuh serta kesadaran yang berakar pada kearifan lokal dimanifestasikan dalam kerangka-kerangka artistik yang hidup selaras bersama alam dan masyarakat sekitar.
“KAWRUH: Tanah Lelaku” diproyeksikan sebagai cerminan sekaligus riak-riak nilai yang berpendar dalam lini masa perkembangan pengetahuan serta tradisi kolektif warga. Melalui judul ini, Biennale Jogja 18 2025 terus mengembangkan ruang-ruang kolaboratif dan partisipatif dengan warga untuk bisa merefleksikan sejarah lokal, merebut tafsir mitologi dan narasi leluhur, serta melihat lebih dekat dampak perubahan lanskap dan tanah terhadap kehidupan hari ini.
Biennale Jogja 18 mempertahankan komitmennya untuk berkolaborasi erat dengan berbagai kelompok sosial dan berinteraksi dengan konteks lokal guna mendorong tindakan merebut kembali sejarah, menceritakan mitologi, kosmologi, dan keyakinan sebagai cara merespons pergeseran lanskap, laut, dan gerakan sosial. Biennale Jogja 18 diikuti oleh sekitar 60 seniman dari berbagai daerah dan berbagai negara, merayakan kekayaan setiap lokalitas sebagai sumber semangat solidaritas antara warga Global Selatan.

Trans-Lokalitas & Trans-Historisitas
Melalui dua kata kunci ini, Biennale Jogja Equator Putaran Kedua berupaya untuk melanjutkan cita-cita bersama untuk menjadi bagian dari penulisan ulang sejarah seni dunia dan berkontribusi pada proyek dekolonisasi seni, terutama yang berfokus pada mempertanyakan Kembali definisi dan kerangka geopolitik dunia. Pada Biennale Jogja Equator Putaran Pertama; gagasan tentang geopolitik dan internasionalisme baru dengan jelas merujuk pada sebuah wilayah fisik dalam peta (23 derajat LU dan 23 derajat LS), dan sukses mendapatkan perhatian dari berbagai pihak terkait kritisisme yang ditawarkan dan interpretasinya atas peta dunia seni baru. Bekerja sama dengan India, Arab, Nigeria, Brazil, Asia Tenggara dan Pasifik, Biennale Jogja berhasil mempertemukan narasi-narasi sejarah yang tersembunyi, serta melihat kembali jaringan internasionalisme global selatan yang didasarkan pada banyak kesamaan lanskap, iklim, kebudayaan, spiritualitas dan dampak-dampak sejarah kolonialisme. Untuk pertama kalinya, Biennale Internasional secara khusus memberi platform pada gagasan-gagasan di luar seni rupa Barat, dan mempertemukan para pelaku seni dari Kawasan-kawasan yang selama ini tidak begitu terhubung dalam internasionalisme seni.
Gagasan global selatan dan Khatulistiwa yang menjadi titik pijak pada BJ Equator Pertama kemudian ingin dikembangkan menjadi spirit yang lebih luas, di mana BJE berupaya untuk menjalin relasi dengan negara-negara di Kawasan lain yang memiliki sejarah atau konteks yang beririsan, dalam rangka mempertanyakan relasi kuasa antara Utara- Selatan, Dunia Pertama – Dunia Ketiga, Asia/Afrika/Amerika Selatan dan Eropa/Amerika, dan sebagainya. Pada Putaran Kedua, BJE ingin membuka peluang bekerja sama dengan Kawasan lain di dunia, untuk melihat bagaimana sejarah masa lalu mempunyai spirit dekolonisasi dan keinginan untuk membongkar pola kekuasaan dari negara-negara adidaya sehingga semua negara atau semua konteks kebudayaan mempunyai posisi yang lebih berdaulat. Kami mencoba membangun khatulistiwa menjadi sebuah imajinasi kolektif bagi komunitas seni dan kebudayaan sehingga dunia seni menjadi sebuah wilayah yang lebih setara, lebih menghormati hak-hak kelompok yang terpinggir, memunculkan Kembali kebajikan dan pengetahuan lokal, serta hal-hal lain yang selama ini dipatahkan oleh dominasi kelompok-kelompok yang kuat. Kami percaya bahwa hal-hal yang berkaitan dengan politik lokasi perlu digarisbawahi untuk dapat membuka ketimpangan relasi kuasa dan melakukan eksperimen yang memungkinkan dekonstruksi relasi tersebut bisa membawa kita pada gagasan atau pengalaman kesetaraan.
Gagasan tentang translocal dan trans-historical dimunculkan untuk memberi ruang bagi sejarah yang lain dengan spirit yang sama, meskipun berada dalam Kawasan di luar global selatan. Pengalaman selama menjalankan BJE Putaran Pertama menunjukkan bagaimana pentingnya merawat kepercayaan dan pengetahuan lokal, keterampilan yang didasarkan pada filsafat tentang alam dan kehidupan, serta kedaulatan masyarakat adat. Dalam Kawasan Global Selatan, di mana masyarakat masih hidup dalam semangat komunal dan spiritualitas yang merepresentasikan kedekatan dengan alam, ada banyak sekali prinsip kehidupan yang berharga untuk menjadi pengetahuan. BJE melalui konsep translocal berupaya menghubungkan pengetahuan di satu lokalitas dengan lokalitas lain, sistem seni dan kebudayaan yang berbasis pada situasi-situasi adat spesifik, serta artikulasi pengetahuan yang lebih berakar pada bahasa-bahasa lokal. Kami membayangkan dapat mengumpulkan seniman, komunitas, ilmuwan adat dari berbagai tempat di dunia untuk menjadi platform pertemuan atau pertukaran pengalaman melalui kerja seni budaya, baik dari masyarakat aborigin, kelompok Indian di amerika, masyarakat adat di Kanada, terutama mengumpulkan seniman dan komunitas seni Nusantara dari berbagai wilayah yang kaya dan beragam, dan beberapa lainnya.
Sementara gagasan transhistorical menunjuk pada alur sejarah yang menjadi inspirasi bagi Gerakan sipil semacam Biennale Jogja untuk memberi kontribusi pada perubahan konstelasi kekuasaan dalam dunia seni. BJE Putaran pertama terinspirasi oleh Gerakan Asia Afrika (KAA) yang kemudian diterjemahkan menjadi Semangat Bandung (Bandung Spirit) di mana kami melihat bahwa Indonesia telah berhasil menginisiasi pertemuan negara-negara yang baru merdeka di Kawasan Asia- Afrika, dan gagasan ini menjadi warisan pemikiran yang sangat berharga yang bahkan gemanya sampai hingga Kawasan-kawasan di Eropa atau Amerika. Setelah KAA sendiri, Gerakan meluas hingga terbentuk Gerakan Non Blok, di mana salah satunya Presiden Yugoslavia pada saat itu, Joseph Broz Tito menjadi bagian dari inisiatif Eropa untuk membentuk aliansi yang tidak berpihak pada dua kekuasaan saat itu (Amerika dan Rusia). Kami melihat bahwa linimasa sejarah menjadi pijakan penting untuk melanjutkan spirit dekolonisasi yang kami perjuangkan, dan bagaimana kami melanjutkan kerja-kerja di masa lalu untuk bisa menjadi bagian dari spekulasi masa depan.
Kami berpikir untuk membangun jejaring dengan beragam imajinasi tentang Timur, termasuk Eropa Timur, Asia Timur, Afrika Timur, dan Kawasan lainnya, sehingga kita bisa membongkar oposisi biner di antara Barat dan Timur itu sendiri, yang selama ini telah menjadi ruang pemisahan bagi warga di dunia. Melalui upaya mempertemukan berbagai imajinasi tentang Timur, kami ingin melihat bagaimana berbagai Kawasan di dunia bisa bertemu dalam spirit dekolonisasi dan berupaya untuk mencari jalan bersama menuju kesetaraan dan kesamaan akses. Selama ini gagasan Kawasan dan pembatasan geopolitik telah menyebabkan ruang pertemuan menjadi semakin terbatas dan terkotak-kotak.
Metode Kuratorial
Laku yang bertransformasi menjadi pengetahuan, Biennale Jogja 18 (BJ18) menarasikan KAWRUH: Tanah Lelaku sebagai proyeksi lanjutan atas payung besar Khatulistiwa (Equator) putaran kedua yang berporos pada translokalitas dan transhistorisitas. Sejak dimulainya tawaran Khatulistiwa putaran kedua yang dibuka dengan Titen: Pengetahuan Menubuh-Pijakan Berubah dua tahun lalu, Biennale Jogja bergerak menelusuri jejaring kesenian di Selatan Global yang secara khusus juga mendorong upaya-upaya desentralisasi dan penguatan narasi dekolonisasi. BJ18 yang menjejaki kata kawruh maka berupaya menghadirkan ragam bentuk pembacaan atas pengetahuan dalam lintasan masa lalu, kini, serta waktu mendatang dengan orientasi pada pengalaman atau laku yang berakar.
KAWRUH sebagai kerangka kuratorial sekaligus tawaran imaji atas ranah kesenian yang berporos pada aspek keseharian, tradisi, serta ragam bentuk kearifan lokal merupakan pijakan utama dalam menyusuri makna pertemuan dan pertukaran antar budaya dengan kompleksitas sejarah yang berbeda-beda. Memaknai KAWRUH dalam akar pemahaman kebudayaan Jawa yang berarti pengetahuan sebagai akumulasi pengalaman yang dicerna secara kritis oleh akal budi, BJ18 secara khusus menyoroti kecenderungan-kecenderungan artistik yang intrapersonal sekaligus interpersonal. Kedua kecenderungan tersebut ditempatkan dalam bentuk-bentuk kerja dialogis dan interdisipliner antara seniman dan masyarakat (pelaku kreatif serta ahli dari disiplin beragam, pemangku kebijakan, dan warga setempat).
Pengetahuan sebagai laku menubuh serta kesadaran yang berakar dari kearifan lokal pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk dapat hidup selaras bersama alam dan ragam makhluk hidup di dalamnya. Kesenian, atau secara khusus seni rupa kontemporer, menjadi salah satu gerbang dalam menelusuri kembali kebudayaan serta pengetahuan-pengetahuan di berbagai masyarakat di Indonesia dan Selatan Global. Dengan melakukan dialog serta kolaborasi bersama warga setempat, komunitas-komunitas kecil, serta individu-individu yang menghayati ragam pengetahuan dan kearifan lokal tersebut, karya seni menjadi titik meleburnya individu, ruang, waktu, hingga bermacam tegangan (antara desa dan kota, kuasa dan kesenjangan sosial, hingga teknologi kini dan lampau).
Pembabakan KAWRUH dalam Tanah Lelaku Biennale Jogja 18
Putaran kedua gagasan Khatulistiwa menempatkan perihal lokalitas dan kesejarahan wilayah Selatan Global dalam imaji-imaji artistik yang berporos pada ruang lingkup pengetahuan warga. Dalam hal ini menyangkut lingkup kehidupan desa yang begitu dekat dengan alam dan sumber daya yang juga mencakup pemahaman atas pengetahuan serta karakteristik ragam elemen alam.
Sebuah penggalan dalam Ramalan Jayabaya di Abad ke-11 serta ajaran Sunan Kalijaga di sekitar Abad ke-14 mengungkapkan bahwa akan tiba waktunya peradaban manusia, khususnya Nusantara, akan mengalami kemunduran. Kalimat “kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange” (sungai kehilangan kedalamannya, pasar kehilangan keramaiannya) memiliki makna mendalam dengan interpretasi yang beragam. Sungai sebagai sumber kehidupan akan semakin dangkal, begitu pula pemahaman dan pengetahuan manusia. Pasar sebagai ruang pertemuan dan negosiasi akan kehilangan keramaiannya, menandakan hilangnya dialog dan lahirnya bermacam konflik. Ungkapan yang populer dalam tradisi Jawa tersebut merupakan gambaran bagaimana estafet pengetahuan merupakan kunci dalam memaknai kehidupan baik secara individu maupun kolektif.
Seperti halnya sungai yang memiliki peran nyata sekaligus makna simbolik dalam kehidupan manusia, begitu pula gunung dan laut yang secara umum juga memiliki kedekatan dengan konstelasi masyarakat Jawa, khususnya Yogyakarta. Termasuk ke dalam bagian Sumbu Kosmologi atau Filosofi Yogyakarta, Gunung Merapi dan Laut Selatan atau Samudera Hindia merupakan contoh lain dari manifestasi pengetahuan berbasis elemen alam. Keseimbangan dan keharmonisan alam seringkali diproyeksikan melalui personifikasi gunung sebagai bapak dan laut sebagai ibu. Keduanya merupakan titik-titik yang dihormati sekaligus pusat kelindan tradisi dan budaya masyarakat setempat.
Laut sebagai muara sungai, begitu pun gunung berapi sebagai sumber tanah yang subur. Keseluruhan elemen alam tersebut menjadi konstelasi pengetahuan kolektif yang dilestarikan secara turun temurun. Melalui pemahaman atas elemen alam, isu lokalitas dan pertemuan sejarah kemudian menjadi dimungkinkan dan masuk akal. Oleh karenanya, KAWRUH diproyeksikan sebagai pendaran pengetahuan warga setempat (mencakup tradisi serta kearifan dan sejarah lokal) yang terpancar pada kelompok masyarakat atau lingkup kehidupan bermasyarakat yang lebih luas dan lebih kompleks, sebut saja wilayah administratif kota hingga negara dan global.
Penyelenggaraan Biennale Jogja 18 menempatkan beberapa titik sebagai poros-poros pendaran. Terbagi ke dalam dua babak, KAWRUH: Tanah Lelaku Babak I di periode 19-24 September 2025 akan dilangsungkan di Padukuhan Boro, Desa Karangsewu, Kulon Progo, yang kemudian dilanjutkan dengan Babak II di Kota Yogyakarta, Desa Panggungharjo, Desa Bangunjiwo, dan Desa Tirtonirmolo pada periode 5 Oktober-20 November 2025.
Babak I dan II melibatkan sejumlah wilayah desa sebagai lokasi menyiarkan gagasan KAWRUH sebagai proses identifikasi sekaligus tumbuh kembang yang berasal dari diri sendiri dan lingkungan terdekat. Desa yang dipilih sebagai lokus kemudian menjadi contoh bagaimana pengetahuan digali dan ditemukan kembali. Karya seni berada dalam posisi serupa cermin bagi seniman dan warga dalam melihat perjalanannya masing-masing sekaligus juga sebagai jembatan dalam menelusuri pengetahuan-pengetahuan yang sempat tersendat pewarisannya untuk kemudian dialami dan dihidupkan kembali dalam laku sehari-hari untuk menjawab tantangan masa kini.
Momentum ini diharapkan dapat memantik kesadaran bersama terkait kedaulatan dan ketahanan budaya. Dimulai dari penggalian dan aktivasi pengetahuan-pengetahuan lokal serta kontekstual yang tidak hanya menjawab tantangan lokal, tetapi juga global. Desa sebagai titik pijak menjadi benteng terakhir kedaulatan atas dasar kedekatan dengan sumber daya alam, berakarnya etos kerja kolaboratif, dan tersedianya pengetahuan-pengetahuan lokal yang berumur panjang. Selain itu, kandungan nilai spiritualitas di desa masih cukup kuat sebagai pengikat atau kohesi sosial.
Pertemuan antara seni kontemporer dengan desa memosisikan seniman bukan hanya sebagai agen artistik, tetapi juga rekanan warga desa dalam upaya percepatan penggalian pengetahuan yang telah lama berakar dalam budaya dan tradisi setempat. Perjumpaan desa dan kesenian inilah yang pertama-tama dimaknai sebagai cermin. Cermin dalam artian karya seni sebagai medium untuk melihat posisi seniman sekaligus warga desa yang seringkali juga tenggelam di dalam kekayaan pengalamannya masing-masing. Seni kemudian juga berperan sebagai jembatan, yaitu media yang mengantarkan seniman dan warga desa kepada pengetahuan mengenai diri dan lingkungannya. Perihal asal muasal, kehadiran dan keberadaan diri, dan tujuan serta proyeksi masa depan. Seni menjadi jalan pulang sekaligus titik berangkat.
KAWRUH sebagai Kelanjutan Sekaligus Pijakan untuk Berdialog dengan Hari Ini
KAWRUH sebagai sebuah landasan artistik berupaya melihat kembali pengetahuan tidak hanya sebagai bentuk akumulasi kompleksitas pemikiran individu manusia, tetapi bagaimana manusia secara berkala dan secara kolektif saling membangun pengertian serta pengalaman yang melahirkan pengetahuan mengakar. Pemahaman tersebut diupayakan untuk tidak hanya bersifat lokal di Indonesia, tetapi juga di wilayah-wilayah lain di Selatan Global.
Seniman terlibat yang berasal dari sebaran wilayah Indonesia dan internasional diposisikan dalam kerangka merespons tema KAWRUH secara umum, terlibat dalam kerja-kerja kolaboratif antar seniman, atau mengikuti kegiatan residensi yang kemudian berdialog dan bekerja bersama warga. Spektrum kerja artistik tersebut merupakan upaya merangkul keragaman artistik yang melebarkan makna atas KAWRUH di berbagai budaya. KAWRUH yang berakar dari bahasa Jawa pada dasarnya melingkupi prinsip-prinsip laku kehidupan yang dapat diterapkan di bermacam kebudayaan dunia.
Biennale Jogja 18 perlu secara cermat melihat aspek keberlanjutan dari penyelenggaraan edisi ke-17 dua tahun lalu yang berporos di Kota Yogyakarta, Desa Bangunjiwo, dan Desa Panggungharjo. Oleh karenanya, keterlibatan dua desa yang disebutkan terakhir dalam penyelenggaraan edisi ke-18 di tahun 2025 ini tidak hanya menandai siasat artistik berkelanjutan dari gagasan Khatulistiwa putaran kedua, tetapi juga bagaimana relasi, jejaring, serta pengetahuan-pengetahuan yang diserap dan dicerap di edisi sebelumnya dapat dikembangkan menjadi tawaran-tawaran artistik serta apresiasi baru dari para seniman partisipan dan warga.
KAWRUH: Tanah Lelaku sekali lagi merupakan tawaran untuk kembali ke tanah tempat manusia berpijak yang sekaligus juga pijakan untuk memulai perjalanan menelusuri pengetahuan-pengetahuan mengakar. Bagaimana pengetahuan-pengetahuan mengakar tersebut dapat digali, dimaknai, dan diserap ke dalam diri untuk kemudian kembali bersiap menghadapi situasi-situasi terkini.
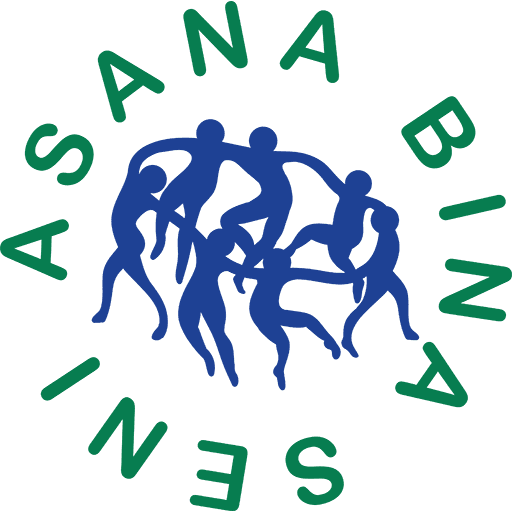
Prananing Boro
Dipantik oleh pengetahuan perihal realitas keseharian di Padukuhan Boro II, sebuah desa yang terletak di Kapanewon Galur, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Prāṇaning Boro dipilih sebagai tema Asana Bina Seni 2025. Kata Prāṇaning yang memiliki arti “angin” atau “napas”, diambil dari Bahasa Kawi (Jawa Kuno). Prāṇaning Boro merepresentasikan ke-sementara-an atau ke-singkat-an kehadiran yang sekilas melintas seperti kencangnya angin pesisir yang menyapu tingginya pepohonan kelapa di Padukuhan Boro II. Kendati singkat, angin selalu datang berulang dan berbaur dengan nafas warga Boro. Begitu pula proses para Seniman beserta Penulis/Kurator Asana Bina Seni 2025 bersama warga Boro, kehadirannya yang hanya sesaat sekaligus menyatu-leburkan pengetahuan dari berbagai bidang pengetahuan dengan realitas keseharian warga Boro, menjadi rangkaian helaan nafas panjang.
Kosa kata Prāṇaning dari Bahasa Kawi yang tidak lagi akrab digunakan juga menjadi representasi permulaan pertemuan pengetahuan yang asing. Namun alih-alih menjadi sepenuhnya asing, peserta Asana Bina Seni 2025 berangkat dari ketiadaan yang kreatif, sehingga diri-peserta secara sadar memahami, memproses, dan mengartikulasikan properti-pengetahuan realitas keseharian warga, untuk memperkaya gagasan penciptaan karya yang sebelumnya telah dibentuk. Pada akhirnya kata Prāṇaning menggambarkan bagaimana pengetahuan yang ada di Padukuhan Boro II (dan sekitarnya) telah merasuk ke dalam, dan menjadi napas dari diri para peserta Asana, selama proses membangun perjumpaan, tinggal, dan berdialog bersama para warga.
Sebagai pengetahuan yang tak pernah usai, Prāṇaning Boro membawa perhelatan Asana Bina Seni 2025 sebagai awalan untuk memiliki dan berbagi angin atau napas yang sama, antara para Seniman dan Penulis/Kurator serta warga Boro II, untuk kedepannya dapat atau setidaknya telah menjadi satu-kesatuan pengetahuan. Dan sebagaimana gerak angin menerpa rimbun rumpun pepohonan di Boro, pengetahuan tersebut diharapkan akan dapat memantul ulang kembali ke arah warga, melalui karya yang dipresentasikan oleh 9 Seniman Muda; Anisyah Padmanila Sari, Barikly Farah Fauziah, Darryl Haryanto, Dionisius Caraka, I Kadek Adi Gunawan, Mailani Sumelang, Sri Cicik Handayani, dan Taufik Hidayat.
Meski berangkat dari lokus yang sama, yaitu Padukuhan Boro II yang membersamai KAWRUH: Tanah Lelaku pada Babak I perhelatan Biennale Jogja, Fioretti Vera, Gata Mahardika, dan Laboratorium Sedusun, membawa pengetahuan sebagai bagian dari Prāṇaning Boro di Panggungharjo pada Babak II Biennale Jogja. Masing-masing Seniman beserta Kurator, meniti jalan yang berbeda-beda. Maka itu, karya-karya yang ada, bila didistorsi sedemikian rupa dapat dipetakan menjadi beberapa subtema: (1) Ekologi, (2) Garis Lebur (3) Arsip dan Sejarah.
Ekologi
Kehidupan sehari-sehari di pedesaan, bila dilihat dari perspektif orang luar, mungkin akan tampak begitu sederhana. Karena aktivitas warga hanya berputar-putar pada ruang-ruang seperti: sawah, tempat ibadah dan rumah. Akan tetapi, bila ditelisik lebih dalam, terdapat sebuah kerumitan. Seperti ditunjukkan oleh Dionisius Caraka melalui karya Nyang-Nyangan, yang berupa plang penanda properti diisi dengan berbagai informasi terkait lahan dan tanah Boro, mencoba melakukan sebuah upaya negosiasi dengan menghadirkan persoalan agraria dalam bentuk simbol visual sehari-hari. Plang, yang biasanya hanya menyatakan kepemilikan atau transaksi jual-beli, kini menjadi ruang wacana yang mengangkat posisi petani dalam urusan negara, memperlihatkan ketergantungan mereka pada tengkulak, menelusuri rantai distribusi hasil panen, sekaligus membuka kemungkinan perhitungan untung rugi maupun ancaman alih fungsi lahan. Melalui cara ini, Dionisius Caraka menyingkap relasi kuasa yang tersembunyi di balik papan sederhana itu, sekaligus menunjukkan bagaimana angka-angka yang semula dimaksudkan untuk memperjelas dan memastikan sesuatu hal, justru menjelma menjadi alat distorsi. Angka kehilangan fungsinya sebagai penjelas, dan berubah menjadi instrumen yang mengaburkan kenyataan, menyingkirkan dimensi sosial, ekologi, bahkan spiritual, demi kepentingan tunggal: keuntungan.
Memudarnya kesadaran ekologis memang merupakan persoalan yang cukup krusial baik itu di perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Terlebih bila mayoritas warga mengandalkan air sebagai sumber penghidupan seperti untuk mengairi persawahan, misal. Karena tanpa adanya pasokan air bersih, tanaman yang ditanam di sawah tidak dapat tumbuh dengan optimal. Dan aliran air pun perlu dijaga bukan semata-mata karena ia menguntungkan manusia, tapi karena ia akan bergerak menuju hilir: ke laut. Membiarkan aliran sungai tercemar sama saja membiarkan bumi yang didominasi oleh laut ini porak-poranda secara ekologi. Melalui karya Wayang Kebon: Cekakak Terakhir, Anisyah Padma merespons isu ekologis tersebut, dengan menyuarakan sesuatu yang sangat dekat namun sering terabaikan menggunakan media wayang berbentuk burung Cekakak yang terbuat dari material yang berasal dari alam seperti serabut kelapa sebagai penanda akan berlangsungnya ekosistem sungai dan daerah pesisir.
Di Antara Ekologi dan Garis Lebur
Semakin lajunya kecepatan sendiri tidak dapat dilepaskan dari semakin masifnya pembangunan infrastruktur mobilitas, yang tidak hanya memantik terjadinya perubahan, tetapi juga perpindahan. Dengan berbekal harapan, individu pergi meninggalkan kampung halaman, dan seringkali disertai janji-janji akan kembali ketika harapan tersebut telah terpenuhi. Tetapi kenyataan lebih sering berkata lain, harapan dan janji seringkali dipatahkan oleh lingkungan dan rumah. Melalui karya Rumah ke Rumah yang menghadirkan rumah, tubuh, sastra lisan bersama Meneroka Indonesia; tali dan layang-layang I Kadek Adi Gunawan mencoba mengajak kita untuk merefleksikan isu lingkungan yang ada di sekitar rumah-rumah tak berpenghuni nan diselimuti sunyi. Rumah ke Rumah membangun konteks “pergi-pulang” antara lingkungan, diri, dan rumah untuk hadir saling menyilang, memahami, dan menyelaraskan kehidupan.
Garis Lebur
Ketika perpindahan terjadi, tentu tidak berhenti di persoalan lokasi atau ruang semata. Ia mengisyaratkan pertemuan individu-individu yang berlatar belakang berbeda. Di sana terjadi interaksi, terkadang berupa perselisihan, tetapi sering pula berupa pertukaran pengetahuan. Sebagaimana Sri Cicik Handayani coba tunjukkan dalam Papangghiyân, yaitu karya yang berupaya mencipta sebuah ruang untuk merayakan perjumpaan yang sederhana dan dibangun melalui serangkaian dialog di titik temu selama proses penciptaan karya. Di mana nampan kemudian digunakan sebagai media sekaligus simbol pertemuan antara Cicik dengan ibu-ibu sebagai tokoh utama dalam ruang privat. Nampan dalam karya ini merupakan salah satu dari pertemuan-pertemuan besar lain yang pernah terjadi dalam sejarah Boro dan sekitarnya.
Namun, pertemuan tak selalu mengharuskan semua pihak untuk mengeluarkan kata-kata, tetap diperlukan pendengar, karena mendengarkan pun sama pentingnya dengan berbicara. Dan terkadang, karena terlalu sibuk berbicara, kita menjadi lupa bahwa apa yang dikomunikasikan melalui kata-kata pun seringkali bukanlah apa yang sebenarnya dimaksud dan kita lupa untuk mendengarkan serta memperhitungkan bunyi-bunyi seperti tawa, gumam, desah, helaan napas yang dihasilkan oleh gerak tubuh lawan bicara kita. Berangkat dari pengalaman mendengarkan yang dilakukan secara lebih intens, bunyi-bunyi yang muncul ketika melakukan pertemuan dan percakapan bersama Ibu-ibu di Dusun Sawit, Panggungharjo. Fioretti Vera dalam Spektralieri, mencoba menggugat bagaimana cara-cara konvensional dalam memahami arsip, sejarah, dan tubuh perempuan; sebagai gantinya ia mencoba mengembalikan habitus mendengar yang tanpa sadar seringkali terjajah atas narasi dominan, dengan menghadirkan kembali ruang dengar yang utuh, di mana tubuh bukan semata alat rekam, dan bunyi bukan sekadar kebisingan maupun derau yang tak berarti, melainkan sumber memori dan pengetahuan yang hidup.
Akan tetapi, karena kecepatan dan pembangunan yang mengutamakan keuntungan, mendengarkan pun kini memang terasa begitu sulit. Sesuatu lebih sering mendekat tanpa adanya aba-aba atau persetujuan, upaya mendengarkan, dan apalagi pembicaraan seperti kota yang semakin merangsek paksa ke daerah pedesaan. Yang merupakan akibat dari sentralisasi aktivitas ekonomi di kota, yang justru kini membuatnya tampak lebih mirip pabrik raksasa, dan menjadikan daerah pedesaan menjadi seperti komplek perumahan tidak terencana untuk kelas pekerja. Desa yang bertransformasi menjadi kota penunjang. Melihat itu, Gata Mahardika dalam Griya Fantasi, mencoba menyoroti absurditas logika pembangunan sekaligus memprovokasi refleksi kritis melalui serangkaian dialog juga diskusi dengan audiens pada saat pameran berlangsung.
Kombinasi antara persebaran individu, masifnya pembangunan dan semakin lajunya kecepatan, telah menghasilkan produk berupa “ke-tidak-pemilik-an”. Meski sesuatu itu dekat dan sehari-hari, tapi asing, bukan milik kita sendiri. Sebab, sesuatu itu diberikan secara paksa dan dimediasikan sedemikian rupa, alih-alih merekah sendiri secara imediasi dari dalam dan atas kehendak diri kita. Melalui karya Quote Unquote, sebuah intervensi performativitas semantik atas material sehari-hari di Boro dan sekitarnya melalui tanda kutip yang berupa instalasi berpindah, video art dan arsip performans layang-layang, Darryl Haryanto mencoba melerai konflik antara bahasa indonesia dan kenyataan sehari-hari. Dengan cara menguraikan mediasi makna yang dilakukan oleh Bahasa Indonesia, yang bermuara pada pengaburan dan penyetrapan makna-makna keseharian agar tidak bertumbuh secara liar di luar peradaban makna resmi nasional. Karya ini beroperasi sebagai repertoar rapuh, yaitu proses (moda dan kerja) kelangsungan (liveness) dan keserentakan (concurrentness) dengan garis-garis batas kesementaraan yang kabur. Singkatnya, sebuah pertunjukan tak kasat mata.
Arsip dan Sejarah
Ketika membicarakan persoalan ekologis kita tidak dapat begitu saja melepaskannya dari kehidupan perempuan. Pasalnya, tubuh perempuan banyak menyimpan pengetahuan lokal, seperti praktik rewang. Dan bila ekologi mengalami kerusakan atau perubahan yang cukup signifikan, maka pengetahuan lokal yang menubuh pada diri perempuan seperti perihal bumbu-bumbu yang diperlukan untuk memasak makanan perlahan-lahan akan menghilang. Kiwari, perubahan-perubahan terjadi dengan begitu cepat, bahkan saking cepatnya mungkin kita tidak akan menyadari begitu sesuatu menghilang dari hadapan mata kita, untuk itu dengan menggunakan medium jarik, cyanotype, foto dan video, Barikly Farah dalam Wewarah Pawon Simbah mencoba melakukan upaya pengarsipan sekaligus penghormatan kepada perempuan yang menjadi pusat pengetahuan lokal yang kian dilupakan. Pada format lain, Laboratorium Sedusun menghimpun, merangkai dan menghadirkan kembali pengetahuan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam bentuk buku resep masakan rumahan. Resep masakan tidak sekadar catatan tentang rempah atau bumbu, namun berisikan pengalaman dan ingatan kolektif menahun.
Perubahan-perubahan kerap kali terjadi bukan atas keinginan kita sendiri, lebih sering perubahan itu disodorkan melalui paksaan, oleh entitas yang lebih berkuasa dan ini dapat dilihat pada karya Tutuwuhan, yaitu sebuah instalasi yang bermaterialkan keramik. Melalui serangkaian peristiwa sejarah yang merentang dari masa kolonial hingga saat orde baru berkuasa dalam karya ini Taufik Hidayat menawarkan berbagai hipotesis perihal sebab-sebab timbul-tenggelamnya salah satu makanan paceklik sekaligus khas Kulon Progo yaitu Growol. Seperti kapitalisme swasta pabrik gula yang mengkanonisasi tanaman tebu dan menyarankan penanaman ketela kayu kepada warga telah berpotensi kembali untuk timbulnya Growol sebagai makanan pokok; sedang rezim orde baru melalui kanonisasi tanaman padi yang mengenyampingkan varietas tanaman lain seperti singkong telah berpotensi menenggelamkan growol sebagai makanan pokok untuk kemudian digantikan oleh nasi. Dan karena karya ini lebih cenderung memberikan hipotesis alih-alih kebenaran tunggal, maka dialog perihal growol, warisan-warisan yang silih-ganti ditinggalkan, dan isu-isu yang melapisinya pun dimungkinkan untuk terjadi.
Penelusuran serangkaian peristiwa sejarah juga dilakukan oleh Mailani Sumelang, tetapi berbeda dengan Taufik yang berfokus pada objek fisik seperti makanan Growol, ia lebih berfokus pada sejarah yang bersumber di sekitar Padukuhan Boro yang terolah sebagai arsip. Arsip hadir pula dalam tubuh, menyimpan mana yang boleh dan yang tidak, mana yang ter-represi dan terekspresi. Bagaimana otot dan jaringan tubuh, yang kerap tidak disadari, berlaku sebagai pencatat riwayat dan gudang memori yang hidup. Karya ini berfokus menyadari dan merekam ingatan tubuh akan peristiwa pasca-kemerdekaan sebagai upaya mengorganisir ingatan berdasarkan empati sesama manusia, bukanya berdasar narasi dominan yang berusaha menggantikan memori ketubuhan. Dapat dilihat pada instalasi hand-cutting kupu-kupu dalam Ngramut yang memantul ke segala arah, termasuk kepada aku-kita. Ngramut mengajak kita membuka ruang sensorial sebagai tubuh yang merekam suka cita, dan sejarah yang hadir dalam sarasehan yang menjadi milik masyarakat sebagai ruang aman yang memantik perdamaian.

ketjilbergerak
ketjilbergerak adalah sebuah kelompok terbuka dan lintas disiplin yang diinisiasi oleh Greg Andi Sindana dan Invani Lela Herliana sejak 2006. Pada mulanya, kelompok ini awalnya menggunakan medium zine untuk menyampaikan pesan. Namun karena zine dirasa bersifat satu arah, mereka kemudian bertransformasi secara bentuk dan metode untuk memungkinkan pertemuan dua atau lebih arah yang kontekstual dan relevan. ketjilbergerak berevolusi secara organik menjadi komunitas pemuda yang berfokus pada pendidikan kontekstual dan seni partisipatif. Sejak 2016, ketjilbergerak mengajak para pemuda desa untuk belajar bersama secara dialogis dan dialektis, mengenali dan membaca konteks lingkungan sekitar mereka, memperkuat posisi tawar dengan membentuk jaringan, juga mendorong produksi pengetahuan dengan metode ‘ngelmu iku kelakone kanthi laku’ (menimba ilmu harus diamalkan hingga jadi perilaku). Pada tahun 2017 ketjilbergerak memenangkan penghargaan “Gerakan Komunitas Terbaik Indonesia” dari Kompasiana.

Bob Edrian
Bob Edrian Adalah seorang kurator independen yang fokus pada perkembangan seni bunyi dan seni media, dia menerima Curatorial Research Grant 2016 yang didanai oleh Selasar Sunaryo Art Space dan Sidharta Aboejono Martoredjo (SAM) Fund for Arts and Ecology. Selain itu, ia terpilih sebagai peserta dalam Para Site Workshops for Emerging Art Professionals 2018 di Hong Kong dan CULTIVATE: Professional Development for Curators and Art Managers yang diselenggarakan oleh in-tangible institute di Bangkok (2024). Karya terbarunya telah dipublikasikan dalam The Bloomsbury Handbook of Sound Art (2020), yang diterbitkan oleh Bloomsbury Publishing, London. Ia juga diakui sebagai salah satu ‘thinkers’ dalam daftar 40 Under 40 Asia Pacific versi Apollo Magazine pada tahun 2022.

IHwa Eva Lin
IHwa Eva Lin adalah seorang kurator independen yang dikenal melalui proyek-proyek kuratorial di luar situs di tempat-tempat yang tidak konvensional seperti pabrik kertas yang terbengkalai, bunker militer, kuil, tambang bersejarah, komunitas adat di pegunungan, serta bekerja secara erat dengan komunitas lokal dan orang-orang dari berbagai bidang untuk terlibat dalam eksperimen yang membentuk praktik interdisipliner-nya. Minat Lin mendorongnya untuk berpikir alternatif dan merespons produksi budaya dalam berbagai bentuk, dengan tujuan untuk memperluas agensi dan kekuatan seni. Proyek-proyek kuratorial terbarunya mencakup Sleepless in Stone (2024 Taipower Art Festival), From Nowhere to Now Here (2023 Romantic Route 3 Art Festival), You and I Live on Different Planets (Centre Pompidou-Metz, 2022, co-kurator bersama Bruno Latour dan Martin Guinard-Terrin), kurator program publik Taipei Biennial 2020-2021, Matsu Biennial 2022 – Underground Matters, dan lain-lain. Saat ini, ia menjabat sebagai art director di mt.project.
Produser
Taman Budaya Yogyakarta
Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY
Pelaksana
Yayasan Biennale Yogyakarta
Pelindung
Sri Sultan Hamengku Buwono X
Penasehat
Dewan Yayasan Biennale Yogyakarta
Direktur Yayasan Biennale Yogyakarta
Alia Swastika
Direktur Biennale Jogja 18
Anjali Nayenggita
Kurator
ketjilbergerak
Bob Edrian
IHwa Eva Lin
Asisten Kurator
Sekar Atika
Ayu Rizki Maulani Rustandi
Sekretaris
Suryati Tri Wulansari
Monica Kristihani
Staf Umum dan Program
Biancha Arianggi
Koordinator Residensi
Putri RAE Harbie
Koordinator Magang dan Sukarelawan
Aditya Hibah
Koordinator Hospitality
Dyah Soemarno
Koordinator Program Publik
Istifadah Nur Rahma
Koordinator Pembukaan & Penutupan
Darumas Kirana
Koordinator Pameran Anak
Karen Hardini
Koordinator Produksi
Alfin Agnuba
Koordinator Media
Angkop Sekar
Staf Media
Juwita Wardah
Admin Website
Maria Santissima Trindade Borromeu
Koordinator Editorial
Balqis Nabila
Koordinator Desain Grafis
Nanda Melya Hapsari
Koordinator Dokumentasi Foto
Swandi Ranadila
Koordinator Dokumentasi Video
Muhammad Azzumar
Desainer Leaflet & Buku Panduan
Bodhi IA
Desainer Katalog
Riyan Kresnandi
MAGANG DAN SUKARELAWAN
Arsip
Samanera Gautama
Desain
Reza Farichul Fauzi
Suqya Hayiuyuni Aminah
Dokumentasi
Akhmad Nafar Awal
Messa Adi Saputra
Muhammad Alfadjar
Muhammad Atabika Firdaus
Revan Ardianta Kusuma
Hospitality
Aditya Dharma Putra
Dario Rifki Ismaila
Ratna Diah Utari
LO Seniman
Bening Gupita Esti
Laksamana Alhafizh
Mohammad Rifki Erlangga
Dinda Galuh Prameswari
Nopsi Marga
Media
Angkop Sekar Arom
Kenar Syalaisha Kanayana
Produksi
Dimas Choirul Rijal
Pradipa Arya Setya
Ratna Tri Gustavia
M. Basudewa Krisna
Bisno Jananto
Program
Bagus Mahendra
Christabel Reviana Septianingtyas
Sayyida Ruslina
Sekretariat
Adeline Chelsya Putri Trisnatu
Mutiara Cahya Dini
Reyna Defani
Cenderamata
Aisah Hidayanti
Canahyang Ekwan Puda
Dewi Sahara Kasih
Lia Ameliah Putri Kirana
Pemandu Pameran
1. Adyatma Noor M
2. Aisya Putri Millazany
3. Amanda Deafani
4. Anselma Evelyn Pramono
5. Benedicta Jovanka
6. Deswita Puteri Maharani
7. Dhea Annisa
8. Elfarizky
9. Ikvina Barirotun Nabila
10. Isti Khomah
11. Keysha Belva Slavina
12. Khofivah Maulida
13. Kune Gunda Imu
14. Laela Fitriana
15. Lutfi Nursam Sidik
16. Moneshy Padmarini
17. M. Aqsha Assyada Gunawan
18. M. Ilmi Wisnu Wardhana
19. M. Nabil Furqon
20. Nada Kamiliya Tsaqofah
21. Putri Novelia Prasetyowati
22. Raheil Anzani Vinandika
23. Riswan
24. Rizki Kurniawati
25. Safira Al Islami
26. Satria Mukti Wibowo
27. Shafrizal Kitisworo Djati
28. Viola Putri Mulyadi
29. Yoga Hanindyatama
TIM ASANA BINA SENI 2025
Koordinator
Nadia Varayandita
Kurator
Muhammad Ade Putra
Shabrina Bachri
Ayu Rizki Maulani Rustandi
Arami Kasih
Tim Riset
Bintang Assangga Aprillianto
Laurensia Dhamma Viriya
Seniman
Anisyah Padmanila Sari
Barikly Farah Fauziah
Darryl Haryanto
Dionisius Maria Caraka A.W.
Fioretti Vera
Gata Guruh Mahardika
Kadek Adi Gunawan
Mailani Sumelang
Sri Cicik Handayani
Taufik Hidayat
Laboratorium Sedusun (Kolektif)
MITRA PROGRAM RESIDENSI
Komunitas Pijiwekan, Kudus
Baladaturanga, Sumbawa
Omah Kendeng, Pati
Museum Nyah Lasem, Rembang
MITRA PROGRAM BIENNALE JOGJA 18
Bhumi Bhuvana
Murakabi
Komunitas Pijiwekan