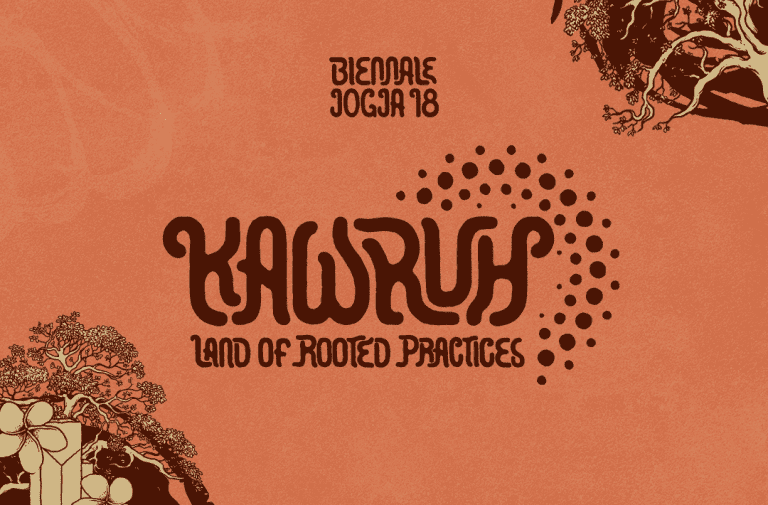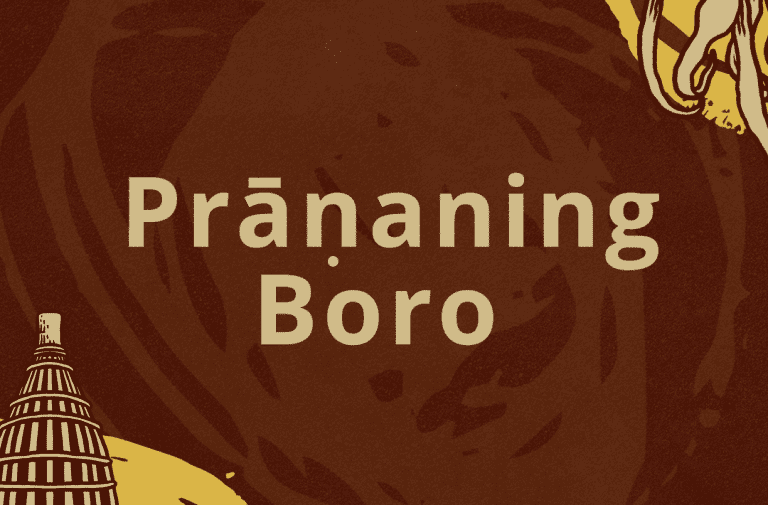Biennale Jogja 18 2025 kembali hadir di tengah kita dengan mengusung tema “KAWRUH: Tanah Lelaku”. Berakar dari Bahasa Jawa yang berarti pengetahuan sebagai akumulasi pengalaman yang dicerna secara kritis oleh akal budi, “KAWRUH” dalam lingkup Biennale Jogja ke-18 dimaknai sebagai sekumpulan keragaman praktik artistik yang berjangkar pada sikap dan upaya menyelami seluk beluk pengetahuan tersebut dengan terus membuka ruang kolaboratif dan partisipatif dengan warga dalam kehidupan hari ini.
Biennale Jogja 18 merupakan tindakan lanjutan dari “Titen: Pengetahuan Menubuh, Pijakan Berubah”, yang berlangsung pada 2023 lalu, dimana edisi Biennale Jogja 17 tersebut mencoba format baru untuk memasuki desa sebagai wilayah kerja guna mendefinisikan kembali makna seni hari-hari ini. Di desa, kita mendapati bagaimana kehidupan yang kaya ini telah sedemikian lama dinihilkan perannya, hingga pengetahuan dan lelaku ini perlahan terpinggirkan oleh ingatan para warganya sendiri. KAWRUH tidak hadir sebagai akhir pencarian, tetapi sebagai awal dari tanya—yang membuka percakapan dengan sejarah seni yang terus bergerak hingga hari ini.
Biennale Jogja 18 2025 ini akan terbagi dalam dua babak. Babak pertama merupakan sebuah repertoar bersama warga di Desa Karangsewu (tepatnya Padukuhan Boro II), Kulon Progo, pada 19-24 September 2025. Kemudian berlanjut pada Babak Kedua di wilayah Kota Yogyakarta, Desa Bangunjiwo, dan Desa Panggungharjo, di kawasan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada 5 Oktober hingga 20 November 2025 mendatang, dengan melibatkan setidaknya 60 seniman dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk seniman-seniman dari wilayah sekitar, serta seniman dari negara-negara di kawasan Global Selatan.
Merti Dusun: Seremonial Pembukaan Babak 1 dengan Tema “Prāṇaning Boro”

Dalam rangka menyambut Perhelatan Biennale Jogja Babak 1, Minggu, 21 September 2025, diselenggarakan kegiatan seremonial pembukaan berupa merti dusun bersama warga Padukuhan Boro II. Seremonial yang dibuka dengan tradisi merti dusun oleh warga setempat bersama Biennale Jogja ini menjadi penanda yang merefleksikan kolaborasi partisipatif dengan warga, sebagaimana hal ini merefleksikan tema “KAWRUH” yang berusaha membuka percakapan dengan sejarah seni bersama warga pada Babak 1 Perhelatan Biennale Jogja 18 yang berkolaborasi bersama Warga Desa Boro II. Merti dusun yang merupakan tradisi para leluhur ini sejatinya ingin menegaskan relasi antara manusia, tanah, dan pengetahuan lokal. Tradisi ini lahir sebagai ungkapan syukur sekaligus doa bersama demi kelancaran perjalanan Biennale Jogja 18.
Dalam konteks ini, merti dusun dipahami sebagai ruang pertemuan antara praktik artistik kontemporer dan kearifan desa, menghadirkan kontinuitas antara warisan budaya dengan wacana seni hari ini. Melalui merti dusun yang dirayakan secara kolektif antara warga dan Biennale Jogja 18, acara ini dimaksudkan untuk merayakan pengetahuan yang tumbuh dari desa, sembari memohon kelancaran atas serangkaian kegiatan yang akan diselenggarakan dalam serangkaian program publik Biennale Jogja 18 Babak 1, “Prāṇaning Boro”.
“Prāṇaning Boro”, yang diambil dari kata “Prāṇaning”, memiliki arti “angin” atau “napas”, diambil dari Bahasa Kawi (Jawa Kuno). Pada Babak 1 Biennale Jogja 18, Prāṇaning Boro dimaksudkan untuk menjadi napas yang mempertemukan pengetahuan lokal warga di Padukuhan Boro II dengan gagasan para seniman dan kurator dalam proses Asana Bina Seni 2025 yang tergabung dalam Babak 1 bersama para seniman lainnya. Dari perjumpaan ini lahirlah karya yang merefleksikan pertukaran pengetahuan dan pengalaman lintas disiplin.
Asana Bina Seni yang merupakan bagian dari program kelas belajar yang diselenggarakan oleh Yayasan Biennale Yogyakarta sejak 2019 ini, telah menjadi bagian dari upaya mengembangkan wacana seni kontemporer yang lintas ilmu juga disiplin seni, terkhususnya bagi para kurator dan seniman muda. Dalam babak 1 ini, terdapat 7 kurator/penulis yang merupakan peserta Asana Bina Seni 2025 dan 16 seniman terlibat, yang mana 8 di antaranya merupakan seniman Asana Bina Seni 2025.
Di antaranya; Muhammad Ade Putra, Arami Kasih, Nadia Varayandita, Shabrina Bachri, Ayu Maulani, Laurensia Dhamma Viriya, dan Bintang Asangga Aprilliantino; yang merupakan tim kurator/penulis. Sedangkan 8 seniman terlibat dari Asana Bina Seni pada babak 1 ini antara lain Anisyah Padmanila Sari, Barikly Farah Fauziah, Darry Haryanto, Dionisius Caraka, I Kadek Adi Gunawan, Mailani Sumelang, Sri Cicik Handayani, dan Taufik Hidayat; serta 8 seniman terlibat babak 1 lainnya adalah Bukhi Prima Putri, Egga Jaya, Faisal Kamandobat, Faris Wibisono, Ismu Ismoyo, Perupa Kulon Progo, Vina Puspita dan Yuta Niwa. Para seniman ini merespon pengetahuan lokal yang mereka dapatkan dari Padukuhan Boro II sebagai bagian dari karya-karya yang dipresentasikan oleh mereka dan telah melalui proses yang panjang.
Rangkaian Program Seremonial Pembukaan Biennale Jogja 18 Babak 1
Seremonial berupa kegiatan merti dusun dalam rangka menyambut “KAWRUH: Tanah Lelaku” – Babak 1: “Prāṇaning Boro” ini dimulai dengan proses kirab budaya “Lampah Pajal-Ulihan”. Peserta kirab terdiri dari para warga Padukuhan Boro II, Tim Kurator dan Seniman Asana Bina Seni 2025 dan para seniman babak 1, serta para tamu undangan dan masyarakat umum yang ingin mengikuti kegiatan pembukaan. Kirab mengelilingi jalan-jalan setapak Padukuhan Boro II ini dimulai pada pukul sembilan pagi, dimulai dan berakhir di Pendopo Karang Kemuning Ekosistem (KKE) Padukuhan Boro II, Sewugalur, Kulon Progo. Hasil bumi warga setempat yang telah disusun menjadi bentuk gunungan diarak melalui proses kirab ini, juga beberapa karya seniman ikut diarak dalam proses kirab ini.
Kemudian, rangkaian acara dilanjutkan dengan pertunjukan tari “Boro Menari” oleh Ibu-ibu Boro II, dengan koreografi yang dibuat oleh salah satu seniman Asana Bina Seni, Sri Cicik Handayani. Penampilan tari dari ibu-ibu warga setempat ini telah melewati latihan dan proses yang panjang yang membersamai Cicik dan Ibu-ibu Warga Boro II, yang nantinya akan berkaitan dengan penampilan tari yang disuguhkan oleh Cicik. Pertunjukan tari ini juga semakin meriah setelah selanjutnya juga ditampilkan Persembahan Angklung Ibu-ibu Boro II dan Penampilan Tari Angguk dari Sanggar Karya Anom.
Teriknya matahari tak menyurutkan antusiasme warga untuk menyaksikan rangkaian acara seremonial pembukaan Biennale Jogja 18. Usai menikmati penampilan memukau dari warga, rangkaian acara berlanjut dengan sambutan dari para perwakilan pihak terkait. Dimulai dengan sambutan dari Greg Sindana dan Invani Lela selaku Dukuh Padukuhan Boro II sekaligus kurator Biennale Jogja 18, Alia Swastika selaku Direktur Yayasan Biennale Yogyakarta, Dra. Purwiati selaku Kepala Taman Budaya Yogyakarta mewakili Kepala Dinas Kebudayaan Kundha Kabudayan, sambutan dari Panewu oleh Yulianta Nugraha, dianjutkan dengan Wakil Kepala Bupati Kulon Progo yaitu H. Ambar Purwoko, A.Md, dan serangkaian sambutan ini ditutup dengan prosesi simbolik peresmian seremonial berupa tradisi pecah kendi. Pecah kendi dalam prosesi pembukaan ini melambangkan awal baru, pembersihan, dan harapan kelancaran jalannya acara. Air yang tumpah menyimbolkan keberkahan, kesuburan, dan kelimpahan rezeki, sementara pecahnya wadah tanah liat menjadi pengingat akan kerendahan hati serta keikhlasan. Besar harapan, ini menjadi tanda simbolis untuk membuka jalan agar serangkaian program ke depan dapat berjalan dengan lancar.

Kegiatan berlanjut ke prosesi rayahan gunungan, yang dalam tradisi merti dusun desa merupakan prosesi berebut hasil bumi yang telah disusun menjadi gunungan, lalu didoakan dan diarak keliling desa. Gunungan melambangkan kesuburan dan kesejahteraan, sementara rayahan dimaknai sebagai perebutan berkah, di mana siapa pun yang memperoleh bagian diyakini mendapat rezeki dan keselamatan. Lebih dari sekadar rebutan makanan, tradisi ini meneguhkan nilai syukur, kebersamaan, dan gotong royong, sebab hasil bumi yang dikumpulkan akhirnya dibagikan kembali sebagai anugerah bersama bagi warga setempat. Selanjutnya, acara dimeriahkan dengan pertunjukan gamelan oleh Kelompok Gamelan Kyai Gugah Boro, dan dilanjutkan dengan “Kembul Bujana”, yaitu sesi makan bersama.
Siang harinya, agenda beralih ke tur kuratorial bersama Tim Kurator dan Seniman Asana Bina Seni 2025, mengunjungi karya-karya seniman yang terletak di berbagai titik dan tersebar di daerah Padukuhan Boro II. Tur dipandu oleh para kurator untuk memberikan pemahaman mendalam kepada peserta tentang beragam macam karya yang dibuat oleh senimannya, yang melalui proses panjang yang mendalam selama berdinamika di Dukuh Boro II. Setelah tur, warga menyaksikan bersama Penampilan “Hadrah” oleh Siswa-Siswi SD NU Galur.
Kemudian, rangkaian program dilanjutkan dengan Penampilan Tari “Rumah ke Rumah” oleh I Kadek Adi Gunawan dan Meneroka Indonesia, yang ditampilan pada rumah kosong yang menjadi lokasi karyanya. Karya “Rumah ke Rumah” ini menghadirkan rumah, tubuh, sastra lisan bersama Meneroka Indonesia. Melalui karya dan penampilan ini, Adi ingin memberikan pemahaman terkait interpretasi terhadap pergi dan pulang ataupun pergi dan tidak kembali lagi. Bentuk karya yang berupa performatif site-specific memiliki makna menolak memiliki batasan terhadap masyarakat atau penonton, dengan melibatkan penonton sebagai pemantik refleksi terhadap isu lingkungan yang telah terjadi pada masa lalu: lebih baik pada hari ini dan yang akan hadir. Setelah penampilan Adi yang dikolaborasikan bersama kuratornya, Muhammad Ade Putra, dilanjutkan dengan pertunjukan Tari Gandewa Puspawati oleh anak-anak SD Sidakan yang berlokasi di Pendopo KKE.
Setelah menyaksikan penampilan tari, para audiens dimanjakan dengan Pementasan Wayang Kebon “Cekakak Terakhir” oleh Anisyah Padmanila Sari. Karya ini lahir dari kesadaran ekologis yang tumbuh dalam keseharian relasi antara alam dan masyarakat Boro. Burung Cekakak, yang bagi masyarakat Jawa memiliki posisi penting sebagai penanda keberlangsungan ekosistem sungai dan wilayah pesisir, dihadirkan untuk menegaskan konteks yang menjadi perbincangan masa kini. Padma menggunakan dolanan anak Lir-Ilir sebagai wacana menarasikan upaya konservasi, bentuk kesadaran personal yang diharapkan dapat menjadi perhatian kita bersama. Pementasan dari Padma ini dilanjutkan dengan Penampilan Tari Jaranan Anak dari Sanggar Nimba Karsa yang tak kalah ciamik.
Rangkaian acara yang panjang tidak menyurutkan semangat audiens dari berbagai kalangan umur, termasuk dengan semangat yang diberikan oleh ibu-ibu warga Sawit, Panggungharjo, yang mempersembahkan Penampilan Gejog Lesung Maju Lancar Miri Sawit. Nyanyian dan tarian yang bersemangat menggugah antusias warga untuk ikut terlibat dan meramaikan penampilan dari Paguyuban Gejog Lesung Maju Lancar. Sebelumnya, pada perhelatan Biennale Jogja 17, paguyuban ini telah ikut andil sebagai bagian dari pementasan yang berkolaborasi dengan seniman Monica Hapsari. Setelah persembahan pementasan dari Ibu-ibu Sawit, Panggungharjo, tak kalah memikat, Sri Cicik Handayani ikut mempersembahkan tariannya dalam Pementasan Tari “Papangghiyân”. Pertukaran wawasan yang didapatkan Cicik selama berdinamika di Boro ini dituangkan Cicik dalam “Papangghiyân”, yang berarti “pertemuan” dalam Bahasa Madura. Karya ini lahir dari riset Cicik tentang Perempuan Tandhak di Madura yang berpadu dengan pengetahuan ibu-ibu Boro sebagai tokoh utama di ruang domestik.
Hari menunjukkan malam, tetapi semangat dan antusias warga untuk menyaksikan serangkaian program pembukaan Biennale Jogja 18 Babak 1 tak pernah padam. Kembali berkumpul di Pendopo KKE, Faris Wibisono menyuguhkan karyanya berupa Penampilan Wayang Beber. Perupa asal Wonogiri ini membawakan Pertunjukan berjudul “Bersih Dusun”, yang berangkat dari respons terhadap keseharian warga Boro yang kemudian diolah menjadi cerita secara lugas dan apik. Setelahnya, acara dilanjutkan dengan Pertunjukan Tari Gedruk Sewugalur oleh Sanggar Karya Anom, sebuah ruang untuk berkreasi dan pelestarian budaya yang bertujuan memperkenalkan budaya lokal ke tingkat internasional. Para pengisi penampilan ini merupakan warga setempat yang telah berlatih selama satu setengah bulan lamanya. Setelah itu, serangkaian kegiatan seremonial pembukaan pun ditutup dengan Pertunjukan Jathilan Klasik Thung Dheng oleh Jathilan Mawar Putih, Gunung Ghempal, Giripeni, Kulon Progo.
“KAWRUH: Tanah Lelaku” sebagai Upaya dan Sikap Kembali ke Akar
Pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan oleh para peserta Babak 1, termasuk di dalamnya para peserta Asana Bina Seni 2025 dengan warga Boro II telah melalui proses yang panjang dan menghasilkan pertukaran pengetahuan dan wawasan. Aktivitas ini menghadirkan kawruh sebagai pengetahuan yang lahir dari laku—dari momen ketika karya, seniman, dan publik saling bersentuhan dalam satu peristiwa yang tidak terulang. Seperti tema yang diangkat oleh Biennale Jogja ke-18, “KAWRUH: Tanah Lelaku”, yang berusaha menempatkan sikap kembali ke akar sebagai upaya menyemai pencerahan. Dalam konteks ini, pengetahuan tidak berhenti di ruang akademik atau wacana seni semata, melainkan kembali pulang kepada masyarakat sebagai sumber sekaligus tujuan, sehingga menjadi milik bersama yang hidup dalam keseharian mereka.
Biennale Jogja sejak 3 tahun terakhir telah berusaha untuk bekerja sama dan menyatu dengan keseharian warga. Harapannya, kolaborasi kali ini bersama warga Boro II dalam “Prāṇaning Boro” terjalin dengan baik dan memberikan dampak secara langsung bagi masyarakat setempat, peserta pameran, dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Kali ini Biennale Jogja 18 mempertahankan komitmennya untuk berkolaborasi erat dengan berbagai kelompok sosial dan berinteraksi dengan konteks lokal guna mendorong tindakan merebut kembali sejarah, menceritakan mitologi, kosmologi, dan keyakinan sebagai cara merespons pergeseran lanskap, laut, dan gerakan sosial.
Melalui judul ini, Biennale Jogja 18 2025 terus mengembangkan ruang-ruang kolaboratif dan partisipatif dengan warga untuk bisa merefleksikan sejarah lokal, merebut tafsir mitologi dan narasi leluhur, serta melihat lebih dekat dampak perubahan lanskap dan tanah terhadap kehidupan hari ini. Dengan demikian, pengetahuan yang semula berakar dari masyarakat menemukan jalannya untuk pulang kembali—menjadi refleksi kolektif, bukan hanya bagi mereka yang terlibat di dalamnya, tetapi bagi setiap lapisan masyarakat secara keseluruhan.