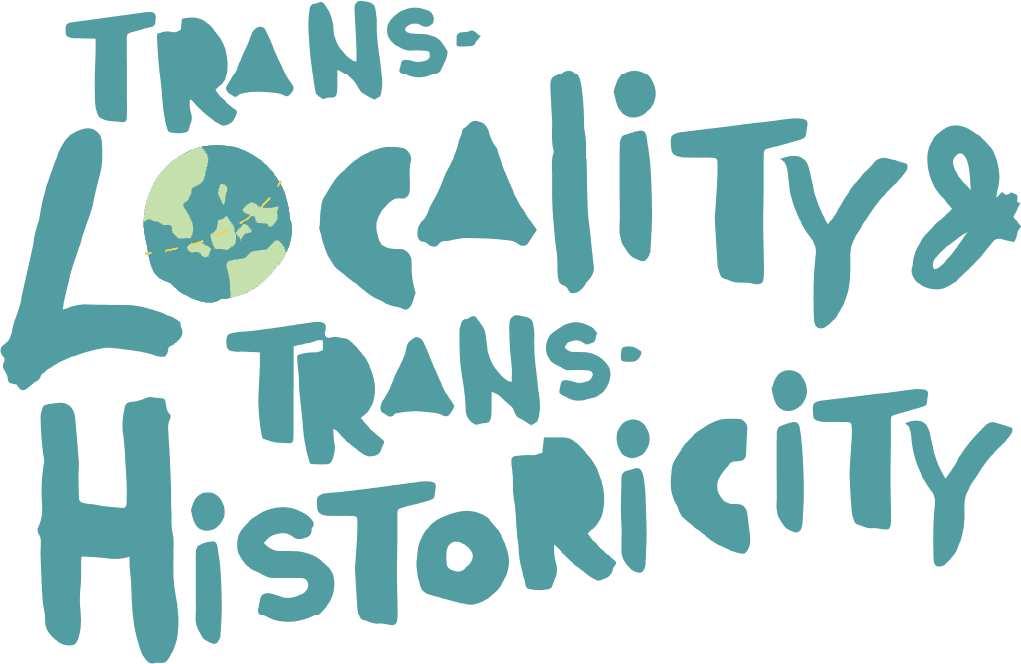Jogja Biennale 17
Di berbagai lokasi di Yogyakarta, Indonesia
6 Oktober–25 November
Yogyakarta (atau Jogja) telah lama menjadi mercusuar praktik seni kolektif Indonesia, dengan Jogja Biennale senantiasa menjunjung tinggi semangat kolaboratif dan transnasional melalui seleksi seniman yang luas dan program publik yang beragam. Edisi ke-17 ini bertajuk “Titen: Embodied Knowledge, Shifting Grounds”. Direktur Alia Swastika bersama kurator Eka Putra Nggalu, Sheelasha Rajbhandari, Hit Man Gurung, dan Adelina Luft berfokus pada tema dekolonisasi pembentukan pengetahuan dengan menggali konsep lokalitas. Tahun ini, 70 seniman lokal dan internasional diundang untuk mengkaji sekaligus menanggapi kearifan dan perlawanan yang masih hidup di dalam komunitas-komunitas kecil dari berbagai profesi di Yogyakarta dan sekitarnya.
Salah satu pendekatannya adalah dengan membongkar politik dari praktik berbasis tanah dan sejarah ekologis. Berlokasi di Gudang Bibis, dibangun instalasi berskala besar oleh kolektif Madura Lembâna Artgroecosystem berjudul Bhâko: So Which of the Favors of Your Land Would You Deny? ‘Tembakau: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?’ (2023). Subjudul mengacu ke ayat yang diulang-ulang dalam “Surat Ar-Rahman” (surat ke-55 di dalam Al-Qur’an).
Instalasi ini digunakan untuk membangkitkan rasa syukur yang kritis terhadap tanah, khususnya di Pulau Madura. Sebuah kanopi persegi yang luas didirikan dan diselimuti daun tembakau kering, yaitu tanaman subsisten yang menjadi tulang punggung industri keretek, andalan ekonomi pulau ini sejak era penjajahan Belanda. Dari tepi-tepi kanopi, bergelantungan kain-kain jumputan berhiaskan tulisan Pegon (aksara Arab yang dimodifikasi untuk menuliskan bahasa Jawa dan Madura) berisi cerita tentang musim kemarau, doa memohon hujan, dan mantra-mantra. Di bawah kanopi, pengunjung diharapkan untuk menyelami narasi kekerasan (kontrol kolonial dan kerja paksa) beraroma nikotin sekaligus perlawanan (melalui mantra dan kamu- flase linguistik) yang menjadi cara untuk memahami secara lebih mendalam kompleksitas sejarah yang tertanam di tanah Madura.
Dari sisa trauma masa lalu yang melekat di tanah hingga ke pengusiran roh-roh gelisah, muncul pendekatan ketiga, yakni penyelidikan terhadap kesakralan suatu tempat sebagai jembatan penghubung antarlokalitas yang berbeda. Dalam kolaborasi dengan kolektif Matrahita yang berbasis di Jogja, seniman Alyen Foning dari Kalimpong, India menghadirkan karya instalasi Eikam-Interconnected (2023), berupa sebuah bola dunia yang terbuat dari tekstil daur ulang, menyatukan Gunung Kanchenjunga yang dianggap suci oleh komunitas Lepcha di Himalaya Timur dengan Gunung Merapi di Jawa, Indonesia—kedua gunung ini memilikitempat istimewa dalam mitologi asal-usul wilayah masing-masing. Di dalam Bumi berjaring ini, yang dirajut dari benang-benang renda, berdiri monumen tekstil Pohon Kehidupan yang menganyam makhluk-makhluk sakral seperti Naga Air Oong Sader (simbol sungai dalam tradisi Lepcha) dan Api Naga Raja (makhluk mitologis Jawa yang menjaga bumi dari kehancuran). Di bawah bola dunia tersebut, Foning meletakkan sebutir biji tanaman yang sama-sama tumbuh di Kalimpong dan di Jawa, melambangkan ikatan translokal yang menghubungkan kedua wilayah melalui penghormatan bersama terhadap tanah leluhur yang sakral. Yang menarik, ini adalah kali pertama Biennale menampilkan karya di berbagai lokasi (edisi-edisi sebelumnya lebih sering diselenggarakan di Museum Nasional Jogja), yang pada akhirnya membuka ruang bagi komunitas lokal untuk menonjolkan produk pertanian dan ritual perayaan mereka masing-masing. Tentu saja ini upaya yang patut diapresiasi guna memulai dialog antara penyelenggara, seniman, dan warga setempat, meski cara dan kedalaman kolaborasi tersebut juga menjadi bahan pemeriksaan dan perenungan kritis. Harapannya, Titen dapat menjadi katalis bagi upaya berkelanjutan Biennale dalam membangun percakapan bermakna antar beragam kepentingan dan perspektif.
Penulis: Duong Manh